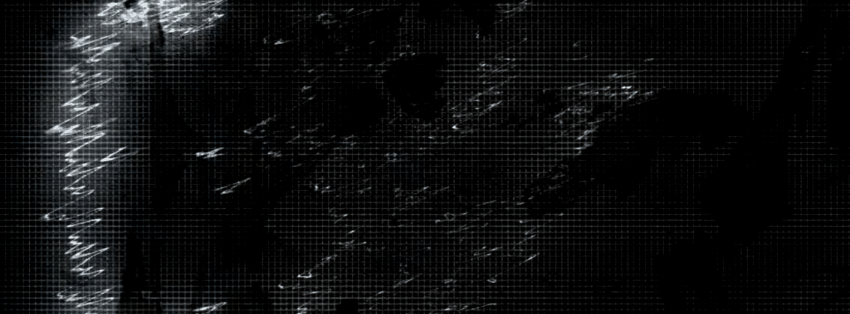Sumber gambar, Hulton-Deutsch/Hulton-Deutsch Collection/Corbis via Getty Images
-
- Penulis, Faisal Irfani
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
Presiden AS, Donald Trump, mengatakan bahwa dirinya telah memberi wewenang kepada lembaga intelijen CIA untuk melakukan operasi rahasia di Venezuela. Pernyataan ini seketika mengingatkan jejak panjang CIA di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia.
Dalam konteks Venezuela, pemberian restu ke CIA dimaksudkan untuk melenyapkan kartel narkoba yang, menurut Trump, produk-produknya telah membanjiri Amerika.
Sejumlah pakar intelijen cukup khawatir dengan langkah Trump. Mereka menilai Trump bisa saja melebarkan operasi CIA ke tujuan yang lain: menggulingkan pemerintah yang sah.
Presiden memiliki kewenangan guna mengerahkan operasi rahasia CIA selama sejalur dengan tujuan kebijakan luar negeri serta penting bagi keamanan nasional AS. Keputusan itu, secara aturan, lalu dibahas ke tingkat Kongres dan Senat.
Dalam praktiknya, presiden tidak jarang menerabas batasan yang ada. Dengan kata lain, otorisasi ke CIA hanya dipegang presiden.
Berkaca dari masa lampau, operasi rahasia CIA mencakup pembunuhan yang ditargetkan, pendistribusian senjata ke kelompok pemberontak, hingga kudeta terhadap pemerintahan yang dianggap tidak satu visi dengan Washington.
Mantan pejabat di Departemen Luar Negeri AS mengakui campur tangan CIA tidak mempunyai “rekam jejak yang bagus.”
Di Indonesia, keterlibatan CIA setidaknya dapat dilacak sejak 1958 ketika mereka mendukung aksi kelompok pemberontak dalam menggoyang kekuasaan Sukarno.
Berjarak satu dekade lebih, keikutsertaan CIA kian menjadi-jadi dengan memanggul peran sebagai mitra bagi militer Indonesia dalam mengganyang kelompok komunis.
Jutaan orang diperkirakan tewas, hilang, serta dipenjara pada periode 1965-1966, menempatkan peristiwa ini ke daftar genosida politik terburuk abad ke-20.
Manipulasi pemilu, bantuan senjata, hingga film porno
Ketika pemerintahan AS berganti pemimpin dari Harry Truman ke Dwight Eisenhower, muncul ketakutan Indonesia bakal menjadi salah satu front komunis terbesar di Asia Tenggara—bahkan dunia.
Bagi pemerintah AS, ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi itu: luas wilayah, populasi, serta cadangan sumber daya alam yang melimpah.
Ditambah, rezim sebelumnya, ketika Truman menjabat, dikritik habis-habisan lantaran dipandang gagal mencegah China dari “pelukan” komunisme, pada 1949.
Satu lagi yang membuat AS was-was: Sukarno.
Kala itu, Sukarno memutuskan Indonesia tidak memihak blok manapun: Barat atau Timur. Indonesia mengambil langkah untuk netral.
Menurut AS, sikap netral inilah yang menyimpan daya ledak. Asumsinya: tidak memihak sama dengan memihak kelompok Timur—komunis.
Apalagi dalam beberapa kesempatan, Sukarno—di balik netralitas tersebut—justru cenderung mendekat ke Timur, kata AS.
Pada 1955, Sukarno mengambil perhatian di tengah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, yang didatangi negara-negara nonblok.

Sumber gambar, Bettmann Archive/Getty Images
Sukarno adalah orator ulung yang piawai membakar semangat warga. Pesan-pesan populis yang termuat di pidatonya kerap bernuansa sosialis dan disukai masyarakat dalam negeri.
Dengan posisi Sukarno sedemikian rupa, maka AS melihatnya sebagai bentuk ancaman. Kehilangan Indonesia di Asia Tenggara ke spektrum politik Kiri bakal merugikan AS yang sedang membangun kekuatan.
Upaya menjegal pengaruh Sukarno lantas ditempuh AS melalui badan intelijen mereka, Central Intelligence Agency (CIA).
Saat Pemilu 1955 berlangsung, CIA mencoba memanipulasi prosesnya dengan—secara diam-diam—memberikan US$1 juta kepada Masyumi, partai Islam sekaligus antikomunis, merujuk Four Who Dared: The Early Years of the CIA karangan Evan Thomas (2006).
Langkah CIA gagal total. Partai Komunis Indonesia (PKI) meraih posisi empat nasional, dengan enam juta suara, di bawah PNI, NU, dan Masyumi. Bersamaan itu, Sukarno pun muncul lebih kuat dibanding sebelumnya.
Usaha “mengalahkan” Sukarno sampai di tahap yang mungkin tidak pernah terbayangkan.
Satu divisi di CIA pernah bekerja sama dengan studio di Hollywood untuk memproduksi film porno, berdasarkan penuturan agen CIA di Far East Division, Samuel Halpern, kepada mantan analis politik di Asian Studies Center, Washington, Kenneth Conboy, Maret 1998.
Film tersebut seolah-olah menggambarkan Sukarno tidur bersama mata-mata Uni Soviet—sekarang Rusia—yang menyamar menjadi pramugari maskapai penerbangan.
Rencananya, film ini bakal disebarluaskan di Asia melalui surat kabar dan majalah. Perwira senior di CIA menyadari hal itu merupakan senjata makan tuan dan urung dipublikasikan.
CIA tidak menyerah. Hanya berselang sebentar dari Pemilu 1955 dan film “porno,” mereka memperoleh lagi “momentum” untuk mempreteli posisi Sukarno.
Kali ini berwujud kelompok pemberontak di beberapa daerah yang dimotori para kolonel TNI yang tidak puas dengan cara Sukarno memerintah.
Di Sulawesi, Letnan Kolonel Herman “Ventje” Sumual menyatakan darurat militer di Indonesia Timur—sampai ke Maluku—setelah Jakarta tidak mengiyakan tuntutan tentang otonomi wilayah, menurut Barbara S. Harvey dalam bukunya, Permesta: Half a Rebellion (2009).
Sumual merasa Jakarta tidak berlaku adil terhadap masyarakat Sulawesi dengan memonopoli perdagangan kopra. Hasil perdagangan itu, nyatanya, tidak didistribusikan secara ideal. Uang hanya berputar di Jawa.
Dari situ, Sumual menuntut otonomi. Dalam bayangan Sumual, otonomi yang lebih besar—setidaknya ekonomi—merupakan konsep yang memiliki nilai.
Maret 1957, Sumual, beserta kelompoknya, menandatangani piagam pendirian Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)—menyusul darurat militer. Gerakan ini, mengutip Barbara, menguraikan niat secara sepihak untuk kewenangan khusus di bidang militer, politik, serta ekonomi. Pendeknya, Permesta ingin mengurangi tangan-tangan Jakarta.
Pemandangan tidak jauh berbeda lahir di Sumatra. Puluhan perwira TNI merapatkan barisan dan menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap Jakarta. Yang vokal menentang ialah Letnan Kolonel Ahmad Husein.
Dia memandang aspirasi daerah, seperti tempat kelahirannya, Padang, tidak digubris Jakarta, dalam hal ini Sukarno. Pemerintah pusat disebut gagal mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang jauh dari kekuasaan.
Akhir 1957, Husein mengambil alih siaran radio lokal dan mengumumkan secara terbuka bahwa tanah Sumatra tidak mematuhi apa yang diputuskan Jakarta.
Memasuki 1958, pada Februari, kelompok pemberontak di Sumatra menyatakan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan elite Masyumi sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia, Syafruddin Prawiranegara, ditunjuk menjadi perdana menteri.
Selain Syafruddin, nama Sumitro Djojohadikusumo, ekonom dan ayah dari Prabowo Subianto, presiden sekarang, menyeruak ke permukaan. Dia bergabung dengan kabinet PRRI dan ditempatkan di kursi penanggung jawab informasi dan pendidikan.
Di tengah itu, Amerika Serikat melihat kesempatan emas untuk menuntaskan misinya: Sukarno.
Mereka berpikir bahwa kolonel-kolonel militer yang membangkang dan membangun kekuatannya sendiri adalah pintu masuk yang strategis dalam mengurus masalah di Indonesia, catat Kenneth Conboy dan James Morrison lewat risetnya yang dibukukan, Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957-1958 (2018).

Sumber gambar, Beryl Bernay/Getty Images
Permasalahannya, menarik perhatian Washington bukan tujuan para perwira yang memberontak, imbuh Conboy dan Morrison. Mereka mempunyai alasan sendiri—etnis dan ekonomi—dalam melawan otoritas pusat di Jawa serta Sukarno.
Faktor “mengeyahkan komunisme,” sebagaimana yang dibawa AS, tidak masuk tujuan kelompok pemberontak.
Meski begitu, kedua titik ini akhirnya bersemuka; dihubungkan langsung dengan faktor “kebutuhan senjata.”
PRRI dan Permesta menyadari kekuatan mereka tidak cukup kokoh andaikata terlibat konfrontasi bersama TNI. Siapa yang pasokan senjatanya melimpah? Amerika Serikat.
Pemerintah AS kemudian meminta CIA turun gunung. Agen-agen lapangan diterjunkan guna membangun komunikasi ke pentolan PRRI dan Permesta. Sejak awal, walaupun antusias dengan “dukungan” di Indonesia, pemerintah AS memerintahkan kepada para agennya untuk tidak mengambil keputusan apa pun, mengacu buku Feet to the Fire.
Setelah pertemuan demi pertemuan dilangsungkan, CIA berhenti pada kesimpulan bulat: memasok persenjataan untuk kelompok pemberontak di Indonesia.
Di Washington, Direktur CIA kala itu, Allen Dulles, secara optimistis memberi tahu Presiden Eisenhower betapa kelompok pemberontak berpotensi menciptakan kekacauan untuk pemerintahan Sukarno, berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari agen-agen di lapangan.
Kekuatan kelompok pemberontak tidak sekadar berpusat di Padang (PRRI) atau Minahasa (Permesta), melainkan berpeluang menyebar ke Kalimantan, Maluku, hingga Jawa, Dulles menjelaskan.
Mengutip buku Feet to the Fire, bantuan CIA termanifestasi, misalnya, lewat setengah lusin senapan mesin kaliber yang diberikan kepada Permesta. Senjata ini dibungkus kain kanvas dan diangkut menggunakan pesawat C-47 dari Filipina.
Sedangkan untuk PRRI di Sumatra, CIA menyediakan ribuan senjata bermacam jenis, dari senapan M1, bazoka, granat, hingga peluncur roket. Pembagian senjata dilakukan dengan dua cara: via laut serta udara.
Di laut, CIA mengandalkan kapal tongkang. Di udara, giliran pesawat C-54 yang ditugaskan.
“Begitu C-54 berada di udara, kabar segera disampaikan ke Padang. Beberapa jam sebelumnya, agen CIA mengambil sebuah jeep dan melaju ke pedalaman untuk mengoordinasikan kelompok yang menerima senjata,” tulis Conboy serta Morrison.
Senjata-senjata itu dijatuhkan dari udara. Pasukan PRRI mengambil kotak-kotak berisikan senjata dari hutan “dan menumpuknya di atas enam truk yang menunggu dalam satu barisan,” merujuk keterangan Feet to the Fire.
Keterlibatan CIA pada misi rahasia di Indonesia diberi kode “Haik.” Proyek Haik menonjol lantaran efisiensinya. Berbeda dengan misi CIA yang merepresentasikan kebijakan luar negeri AS yang masif, Haik sebaliknya: dia operasi yang disetujui di lingkup terbatas—presiden beserta lingkaran elite CIA saja.

Sumber gambar, IKPNI/KOMPAS
Nasib PRRI dan Permesta tidak bertahan lama. Hanya dalam kurun waktu tiga tahun sejak mereka mengobarkan perlawanan, TNI, di bawah komando AH Nasution, berhasil meredam gerak-geriknya. Ini sudah mencakup penangkapan pilot AS, Allen Pope, yang dituduh hendak mengebom kampung di Ambon, Maluku.
Penangkapan Pope turut membongkar keterlibatan intens CIA di pemberontakan PRRI dan Permesta.

Sumber gambar, WIKIMEDIA
Dalam analisisnya, Kenneth Conboy dan James Morrison mengungkapkan kegagalan PRRI dan Permesta disumbang kondisi lemahnya dukungan politik di kalangan akar rumput. Dari sisi eksternal, atau campur tangan CIA, retorika antikomunisme ternyata dianggap tidak segenting itu untuk diperjuangkan.
Kegagalan PRRI dan Permesta, Conboy dan Morrison melanjutkan, seketika menampar wajah CIA yang sebelumnya, dengan penuh kepercayaan diri, membuat klaim bahwa pemerintahan Sukarno dapat dikendalikan.
Kandas di Permesta dan PRRI, CIA ‘menebusnya’ pada Peristiwa 1965.
Metode Jakarta
Menguatnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kecenderungan Sukarno merapat ke mereka telah membikin TNI Angkatan Darat (AD) sekaligus Washington cemas, seperti diarsipkan J. D. Legge dalam Sukarno: A Political Biography (1972).
Memasuki dekade 1960, PKI menjelma sebagai kekuatan politik besar di Indonesia, dengan total keanggotaan resmi menyentuh tiga juta orang—belum termasuk organisasi yang terafiliasi ke mereka seperti Gerwani, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia (BTI), atau Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat).
Hitung-hitungan tiga juta orang ditulis oleh sejarawan Geoffrey B. Robinson lewat bukunya bertajuk The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres, 1965-66 (2018).
Angka tersebut menjadikan PKI sebagai partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah China dan Uni Soviet.
Kekuatan PKI turut memengaruhi kebijakan di tingkat nasional. Contohnya: reforma agraria. Dalam praktiknya, PKI menempuh apa yang disebut dengan “aksi sepihak” untuk “mengembalikan” kepemilikan tanah ke para petani.
Di luar reforma agraria, Sukarno mengusulkan pembentukan “Angkatan Kelima,” berisikan rakyat biasa yang dipersenjatai.
Baik reforma agraria, atau aksi sepihak, dan Angkatan Kelima sama-sama membuat militer geram sebab menyenggol kepentingan-kepentingan yang selama ini mereka jaga.
Maka, dari situ, tentara dan Washington—pemerintah AS—bersekutu dalam rangka membangun kemitraan antikomunis, mengutip buku The Jakarta Method (2020) yang disusun Vincent Bevins.
Indikatornya terlihat, contohnya, melalui pengiriman tentara Indonesia untuk mempelajari taktik operasi, intelijen, dan logistik ke Amerika. Per 1962, berdasarkan The Jakarta Method, terdapat lebih dari 1.000 tentara yang menuju ke basis militer di AS, mayoritas di Fort Leavenworth, sehubungan kegiatan pelatihan.
Dinamika politik antara TNI, PKI, dan Sukarno berubah ketegangan serta memuncak pada September 1965 dengan pembunuhan enam perwira tinggi di tubuh militer, salah satunya Ahmad Yani, yang saat itu menjabat Panglima TNI Angkatan Darat (TNI AD).
Militer lalu bereaksi dengan menjadikan PKI sebagai dalang di balik pembunuhan para jenderal dan turut menuduh mereka hendak mengudeta pemerintahan Sukarno, menurut analisa John Roosa di Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’Etat in Indonesia (2006).
Perburuan orang-orang Kiri, serta yang terhubung ke PKI, dijalankan secara besar-besaran tidak lama setelahnya.
Di sinilah CIA—dan Amerika Serikat—punya kontribusi yang tidak sedikit.

Sumber gambar, KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via Getty Images
Oktober 1965, mengutip The Jakarta Method, kantor CIA di Bangkok memasok persenjataan kepada kontak militernya di Jawa Tengah “untuk digunakan melawan PKI,” bersamaan dengan persediaan medis yang bakal dikirim dari kantor yang sama.
Tidak cuma senjata dan obat-obatan, CIA memberikan elemen lain yang begitu penting: informasi.
“Anda tidak membutuhkan persenjataan yang sangat canggih untuk menangkap warga sipil yang hampir tidak memberikan perlawanan. Namun, bagi tentara [Indonesia], yang benar-benar dibutuhkan adalah informasi,” papar Bevins.
Analis CIA membantu pihak Kedutaan Besar AS menyusun daftar yang memuat nama-nama yang termasuk anggota atau diduga PKI. Jumlahnya ribuan. Daftar ini diserahkan kepada tentara sehingga dapat dibunuh dan dicoret, terang Bevins.
Seorang pejabat Kedubes AS di Jakarta mengatakan bahwa daftar itu “benar-benar membantu tentara.”
“Mungkin saya memiliki banyak darah di tangan saya. Tapi, itu bukan hal yang sepenuhnya buruk,” tegasnya.
Ini kali ketiga sepanjang sejarah saat taktik “pembuatan daftar komunis” dirumuskan oleh intelijen AS dan pejabat kedutaan besar, sebut Bevins. Yang pertama di Guatemala (1954). Kedua di Iran (1963).
Skala kerusakan di Indonesia melampaui apa yang sudah terjadi di dua negara sebelumnya.
Distribusi daftar “orang komunis,” jelas Saskia Wieringa dalam Propaganda and Genocide in Indonesia: Imagined Evil (2018), dibarengi dengan gencarnya militer memproduksi proganda buruk terhadap PKI; bahwa mereka menyiksa jenderal TNI secara sadis dan telah menyiapkan kuburan massal bagi orang-orang yang akan mereka bunuh.

Sumber gambar, Dirck Halstead/Getty Images
Wakil Menteri Luar Negeri AS, George Ball, saat 1965 meletus, dilaporkan menghubungi Direktur CIA, Richard Helms, guna menanyakan apakah mereka “berada dalam posisi yang secara tegas dapat menyangkal keterlibatan operasi CIA di Indonesia.”
Helms, seperti dituturkan di The Jakarta Method, membalas “ya.”
Dalam sebuah kabel rahasia, CIA mengaku sudah mengetahui sosok Soeharto setidaknya sejak September 1964.
Di situ, CIA menyatakan Soeharto sebagai salah satu jenderal militer yang dianggap “bersahabat” dengan kepentingan AS dan antikomunis. Kabel tersebut juga mengajukan gagasan ihwal koalisi militer dan sipil antikomunis yang mampu merebut kekuasaan dari rezim sebelumnya.

Sumber gambar, UPI/Bettmann Archive/Getty Images
Pembantaian 1965 adalah kemenangan besar untuk AS dan CIA yang kemudian diterapkan dengan akurasi yang kurang lebih serupa di operasi lain, seperti yang terjadi di Chile.
Di Chile, CIA memegang peran krusial dalam menurunkan kekuasaan Salvador Allende dari Partai Sosialis yang berhaluan Kiri. Jargon yang diusung Allende terangkum dalam “La via chilena al socialismo” atau sosialisme Chile.
Amerika tidak suka dengan Allende dan mulai mempreteli pemerintahannya. CIA membikin propaganda dan membiayai politikus Kanan untuk bertarung melawan Allende dalam pemilu.
Tak cukup, CIA bersekutu dengan militer dan memutuskan mengudeta Allende pada September 1973. Posisi Allende digantikan jenderal bernama Augusto Pinochet. Didukung Amerika, rezim Pinochet memberangus semua yang terhubung ke komunis. Ribuan orang hilang, dibunuh, dan dimasukkan penjara.
Operasi penyingkiran Allende dikenal dengan “Operation Jakarta,” sebuah metafora dan kode yang dipercaya terinspirasi dari penggulingan Sukarno dan pembantaian massal terhadap kaum kiri pada 1965-1966, terang Peter Dale Scott dalam The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967 (1985).

Sumber gambar, Bettmann Archive/Getty Images
Di Amerika Latin, ujar Bevins, nama “Jakarta” menemukan makna baru. Dia tak lagi dikenal sebatas “ibu kota Indonesia,” tapi juga wajah bagaimana CIA—dan Amerika—menciptakan teror maupun kekerasan kepada kelompok Kiri.
“Penghancuran PKI, kejatuhan pendiri gerakan Dunia Ketiga [Third World Movement], serta kebangkitan kediktatoran militer antikomunis di Indonesia memicu tsunami politik di hampir setiap sudut dunia,” tutur Bevins.
“Skala kemenangan gerakan antikomunis dan metode pemusnahan yang kejam di Indonesia lantas mengilhami pembasmian komunis yang sama di berbagai tempat. Itu menjadi bayang-bayang di balik ibu kota Jakarta.”