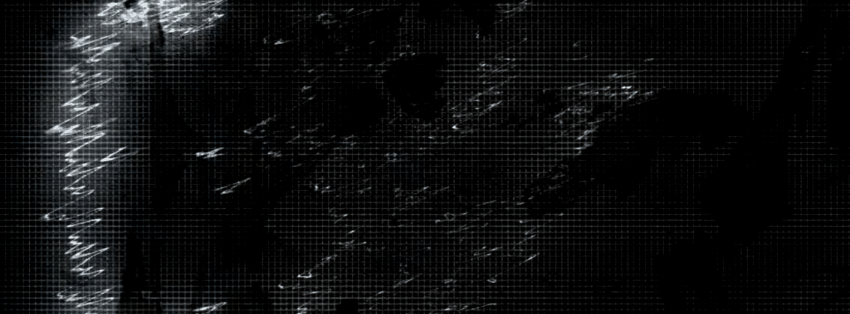Sumber gambar, Fenamad
-
- Penulis, Stephanie Hegarty
- Peranan, Global population correspondent
Tomas Anez Dos Santos sedang bekerja di sebuah lahan terbuka di Hutan Amazon, Peru, ketika dirinya mendengar langkah kaki mendekat di rimba terbesar kedua di dunia itu.
Dia menyadari dirinya telah terkepung dan seketika membeku.
“Salah satu dari mereka berdiri, membidik saya dengan anak panah,” katanya. “Entah bagaimana dia menyadari keberadaan saya di sini dan saya langsung berlari.”
Tomas rupanya berhadapan langsung dengan Suku Mashco Piro.
Selama beberapa dekade, Tomas—yang tinggal di Desa Nueva Oceania—sejatinya bertetangga dengan suku nomaden yang menghindari kontak dengan orang luar.
Namun, baru-baru ini, dia bertemu mereka.
Mashco Piro memilih untuk terisolir dari dunia selama lebih dari satu abad. Mereka berburu dengan busur dan anak panah, serta mengandalkan Hutan Amazon untuk memenuhi semua kebutuhan mereka.
“Mereka mulai berputar-putar dan bersiul, menirukan suara binatang, berbagai jenis burung,” kenang Tomas saat itu.
“Saya lantas bilang: ‘Nomole‘ (saudara). Lalu mereka berkumpul, mereka merasa lebih dekat, jadi kami menuju sungai dan berlari.”

Sebuah laporan baru dari organisasi Survival International mengatakan setidaknya terdapat 196 kelompok yang disebut “kelompok tak tersentuh” dengan dunia luar. Suku Mashco Piro diyakini sebagai kelompok terbesar.
Laporan tersebut menyatakan separuh dari kelompok ini bisa punah dalam dekade mendatang jika negara-negara tidak berbuat lebih banyak untuk melindungi mereka.
Paparan di dalam laporan itu juga mengklaim risiko terbesar terhadap suku terisolir berasal dari industri ekstraktif seperti kehutanan, pertambangan, dan perminyakan.
Para misionaris yang melakukan penginjilan dan pemengaruh media sosial yang mencari penonton juga disebut-sebut menimbulkan ancaman.
Baru-baru ini, orang-orang Mashco Piro semakin banyak datang ke Nueva Oceania, menurut penduduk setempat.
Desa kecil itu merupakan komunitas nelayan yang terdiri dari tujuh atau delapan keluarga. Lokasinya berada di tepi Sungai Tauhamanu di jantung Hutan Amazon, Peru.
Kawasan tersebut tidak diakui sebagai cagar alam untuk masyarakat adat dan perusahaan penebangan kayu beroperasi di sana.
Tomas berkata, terkadang suara mesin pemotong kayu terdengar siang dan malam.
Suku Mashco Piro menyaksikan hutan mereka diganggu dan dihancurkan.
Di Nueva Oceania, masyarakat setempat mengaku menghadapi dilema.
Pada satu sisi, mereka takut akan ancaman panah Suku Mashco Piro. Namun, pada sisi lain, mereka sangat menghormati “saudara-saudara” yang tinggal di hutan dan ingin melindunginya.
“Biarkan mereka hidup apa adanya, kita tidak bisa mengubah budaya mereka. Itulah sebabnya kita menjaga jarak,” ucap Tomas.

Sumber gambar, Survival International
Penduduk Desa Nueva Oceania juga khawatir mata pencaharian Suku Mashco Piro dirusak, ancaman kekerasan, dan penularan penyakit yang kemungkinan datang dari para penebang kayu. Penularan penyakit bisa berbahaya karena suku tersebut tak memiliki kekebalan tubuh yang memadai karena mereka terisolir dari dunia luar.
Saat kami berada di desa, Suku Mashco Piro muncul kembali. Letita Rodriguez Lopez, seorang ibu muda yang mempunyai putri berusia dua tahun, sedang berada di hutan memetik buah ketika mendengar suara mereka.
“Kami mendengar teriakan, jeritan mereka. Seolah-olah ada sekelompok orang yang berteriak,” ujar Letita.
Itu adalah pertama kalinya Letita bertemu Suku Mashco Piro dan ia pun langsung lari. Satu jam kemudian, kepalanya masih berdenyut karena ketakutan.
“Karena ada penebang kayu dan perusahaan yang menebang kayu, mereka melarikan diri, mungkin karena takut dan akhirnya berada di dekat kami,” ungkapnya.
“Kami tidak tahu bagaimana reaksi mereka terhadap kami. Itulah yang membuat saya takut,” sambungnya.
Pada 2022, dua penebang kayu diserang oleh Suku Mashco Piro saat sedang memancing. Salah satu dari mereka terkena panah di perut. Orang itu selamat, tapi pria lainnya ditemukan tewas beberapa hari kemudian dengan sembilan luka panah di tubuhnya.

Sumber gambar, Google/BBC
Pemerintah Peru melarang masyarakat awam berkontak dengan suku terisolir. Karena itu, memulai interaksi dengan mereka tergolong tindakan melanggar hukum.
Kebijakan ini bercermin dari Brasil. Di sana, kelompok-kelompok hak asasi masyarakat adat menyuarakan selama puluhan tahun agar masyarakat awam tidak berkontak dengan suku terisolir setelah melihat bahwa berkontak dengan orang-orang yang terisolir menyebabkan kelompok tersebut punah akibat penyakit, kemiskinan, dan malnutrisi.
Pada 1980-an, ketika orang-orang Nahau di Peru pertama kali berhubungan dengan dunia luar, 50% populasi mereka meninggal dalam hitungan tahun.
Kemudian pada 1990-an, Suku Muruhanua menghadapi nasib yang sama.
“Masyarakat adat yang terisolasi sangat rentan. Secara epidemiologis, kontak apa pun bisa menularkan penyakit sehingga penyakit yang paling sederhana pun bisa memusnahkan mereka,” ujar Issrail Aquisse dari kelompok hak asasi masyarakat adat Peru, Femanad.
“Secara budaya juga, kontak atau berhubungan apa pun sangat berbahaya bagi kehidupan dan kesehatan mereka.”
Bagi masyarakat yang hidup di dekat suku-suku yang tidak tersentuh dunia luar, larangan berkontak bisa jadi rumit.
Saat Tomas menunjukkan tempat dia bertemu dengan Suku Mashco Piro, ia berhenti, bersiul di sela-sela jarinya, lalu menunggu dalam diam.
“Kalau mereka menjawab, kita bisa pulang,” katanya.
Tapi yang kami dengar hanya kicauan serangga dan burung.
“Mereka tidak di sini,” cetus Tomas.
Tomas merasa pemerintah telah membiarkan penduduk Desa Nueva Oceania menangani sendiri situasi ini.
Itu mengapa, dia akhirnya menanam bahan makanan di kebunnya untuk dimakan oleh Suku Mashco Piro. Ini adalah langkah-langkah keamanan yang dia dan penduduk desa lainnya buat untuk membantu suku tersebut sekaligus melindungi diri sendiri.
“Andai saja saya tahu kata-kata yang tepat untuk mengatakan, ‘Ini pisang raja, ini hadiah. Kalian boleh mengambilnya sesuka hati. Tapi jangan tembak saya’.”

Cerita dari pos patroli
Hampir 200 kilometer ke arah tenggara di seberang hutan lebat, situasinya sangat berbeda. Di sana, di tepi Sungai Manu, Suku Mashco Piro tinggal di kawasan yang secara resmi diakui negara sebagai cagar hutan.
Kementerian Kebudayaan Peru dan LSM Fenamad mengelola pos kendali “Nomole” di sana, yang dikelola oleh delapan petugas. Pos kendali ini didirikan pada 2013 ketika konflik antara Mashco Piro dan desa-desa setempat menyebabkan kematian.
Sebagai kepala pos kendali, tugas Antonio Trigoso Ydalgo adalah mencegah hal itu terjadi lagi.
Suku Mashco Piro muncul secara teratur, terkadang beberapa kali seminggu.
Mereka adalah kelompok yang berbeda dari kelompok di dekat Desa Nueva Oceania. Para petugas meyakini mereka tidak saling kenal.

Sumber gambar, Fenamad
“Mereka selalu keluar di tempat yang sama. Di situlah mereka berteriak,” tutur Antonio menunjuk ke seberang Sungai Manu yang lebar ke pantai kecil berkerikil.
Antonio menambahkan, mereka biasa meminta pisang raja, singkong, atau tebu.
“Jika kami tidak menjawab, mereka duduk di sana sepanjang hari untuk menunggu,” katanya.
Para petugas pos kendali berusaha menghindari situasi itu, demi berjaga-jaga jika ada turis atau perahu lokal yang lewat. Jadi mereka biasanya menuruti permintaan itu.
Pos kontrol tersebut mempunyai kebun kecil, tempat mereka menanam bahan makanan. Ketika kebun itu habis, mereka meminta persediaan dari desa setempat.
Jika persediaan di desa tidak tersedia, para petugas meminta Suku Mashco Piro untuk kembali dalam beberapa hari. Sejauh ini cara tersebut berhasil, dan baru-baru ini hanya ada sedikit konflik.
Ada sekitar 40 orang yang rutin ditemui Antonio, kebanyakan pria, perempuan, dan anak-anak dari berbagai keluarga.
Mereka menamai diri dengan nama hewan. Kepala suku disebut Kamotolo (Lebah Madu).
Para petugas mengatakan Kamotolo adalah orang yang tegas dan tidak pernah tersenyum. Pemimpin lainnya, Tkotko (Burung Nasar) lebih suka bercanda, ia banyak tertawa dan mengolok-olok para petugas.
Ada juga seorang perempuan muda bernama Yomako (Naga) yang menurut para agen memiliki selera humor yang baik.
Suku Mashco Piro tampaknya tidak terlalu tertarik dengan dunia luar, namun terpikat pada kehidupan pribadi para petugas yang mereka temui.
Mereka biasanya akan bertanya tentang keluarga dan tempat tinggal para petugas.
Ketika seorang petugas sedang hamil dan cuti, mereka membawa mainan kerincingan yang terbuat dari tenggorokan monyet untuk dimainkan oleh sang bayi ketika lahir.
Mereka juga tertarik pada pakaian para petuigas, terutama baju olahraga berwarna merah dan hijau.
“Saat kami mendekat, kami mengenakan pakaian lama yang robek dengan kancing yang sudah lepas, agar mereka tidak mengambilnya,” tutur Antonio.
“Sebelumnya, mereka mengenakan pakaian tradisional yaitu rok yang sangat indah terbuat dari benang serat serangga yang mereka bikin sendiri. Tapi sekarang, beberapa dari mereka, ketika kapal wisata lewat, menerima pakaian atau sepatu bot,” kata Eduardo Pancho Pisarlo, seorang petugas di pos kontrol.

Sumber gambar, Fenamad
Namun, setiap kali petugas pos kontrol bertanya tentang kehidupan mereka di hutan, Suku Mashco Piro langsung menutup percakapan.
“Pernah saya bertanya bagaimana mereka menyalakan api?” tanya Antonio.
“Mereka bilang, ‘Kamu punya kayu lho‘. Tapi saya bersikeras bertanya dan mereka menjawab, ‘Kamu sudah punya semua ini, kenapa kamu ingin tahu?'”.
Jika seseorang dari Suku Mashco Piro tidak muncul cukup lama, para petugas akan bertanya di mana mereka berada.
Seandainya seseorang dari Suku Mashco Piro berkata, “Jangan tanya”, itu artinya orang tersebut sudah meninggal.
Setelah bertahun-tahun berkomunikasi, para petugas masih tak banyak tahu tentang bagaimana Mashco Piro hidup dan mengapa mereka tetap tinggal di hutan.
Diyakini mereka mungkin keturunan penduduk asli yang melarikan diri ke hutan lebat pada akhir abad ke-19, kabur dari eksploitasi yang merajalela dan pembantaian yang meluas oleh orang-orang yang disebut “saudagar karet” — sebuah peristiwa yang berkaitan dengan komersialisasi karet dan genosida masyarakat adat di wilayah Amazon.
Para ahli berpendapat Mashco Piro mungkin berkerabat dekat dengan Yine, penduduk asli dari Peru tenggara. Mereka berbicara dengan dialek kuno dari bahasa yang sama, yang telah dipelajari oleh para agen, yang juga dari suku Yine.
Tetapi, Suku Yine telah lama menjadi navigator sungai, petani, dan nelayan. Sementara Suku Mashco Piro tampaknya telah melupakan cara-cara itu.
Mereka mungkin telah menjadi nomaden dan pemburu-pengumpul demi keamanan.
“Yang saya pahami sekarang adalah mereka tinggal di satu daerah untuk sementara waktu, mendirikan kemah, dan seluruh keluarga berkumpul,” ujar Antonio.
“Setelah mereka berburu semua yang ada di sekitar tempat itu, mereka pindah ke lokasi lain.”

Sumber gambar, Fenamad
Issrail Aquisse dari LSM Fenamad mengatakan lebih dari 100 orang datang ke pos kontrol pada berbagai waktu.
“Mereka meminta pisang dan singkong untuk diversifikasi makanan mereka, tetapi beberapa keluarga menghilang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah itu,” ujarnya.
“Mereka hanya berkata: ‘Saya akan pergi selama beberapa bulan, lalu saya akan kembali’. Dan mereka mengucapkan selamat tinggal.”
Mashco Piro terlindungi dengan baik di daerah ini, tetapi pemerintah sedang membangun jalan yang akan menghubungkan ke daerah di mana penambangan ilegal tersebar luas.
Namun, jelas bagi para petugas bahwa Suku Mashco Piro tidak ingin bergabung dengan dunia luar.
“Dari pengalaman saya di pos ini, mereka tidak ingin menjadi ‘beradab’,” tegas Antonio.

“Mungkin anak-anak menginginkannya, ketika mereka tumbuh dewasa dan melihat kami mengenakan pakaian, mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Tetapi orang dewasa tidak. Mereka bahkan tidak mau kami di sini,” ujarnya.
Pada 2016, sebuah rancangan undang-undang pemerintah disahkan untuk memperluas cagar alam Mashco Piro hingga mencakup Desa Nueva Oceania. Namun, RUU ini belum pernah disahkan.
“Kami ingin mereka bebas seperti kami,” ujar Tomas.
“Kami tahu mereka hidup dengan sangat damai selama bertahun-tahun, dan sekarang hutan mereka dibabat habis, dihancurkan.”