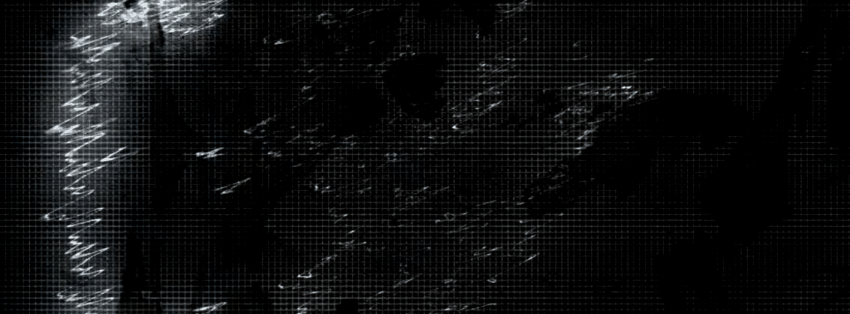Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Rencana cetak sawah dan kebun tebu untuk bioethanol hingga tiga juta hektar di Merauke, dikhawatirkan menyebabkan apa yang disebut sebagai “etnosida” atau pemusnahan budaya, terhadap salah satu suku terbesar di Papua Selatan, suku Malind Anim.
Bagi suku Malind Anim, hutan adalah “mama” dan akar jati diri mereka. Hutan adalah tempat “sakral”, tempat manusia Malind itu diciptakan. Pembongkaran hutan sama artinya dengan kepunahan.

Proyek pangan dan energi yang dimulai sejak masa pemerintahan Joko Widodo memicu diskusi di kalangan suku Malind Anim dan para akademisi tentang pelucutan budaya sejak masa penjajahan Belanda, gelombang pendatang, hingga kehadiran perusahaan yang menawarkan modernitas.
“Waktu awal dari zaman Belanda itu, kita orang Malind Anim sudah ditindas. Ketika ada perjanjian lagi transmigrasi masuk, tanah-tanah yang di lokasi ini diambil cuma-cuma begitu,” kata Yakobus Mahuze, generasi terkini Malind Anim.
“Pemerintah langsung dia bilang, ‘Tanah ini saya punya, ini sudah disertifikatkan, ini sudah keputusan pemerintah’. Kita punya tanah banyak yang sudah hilang cuma-cuma saja.”
Di sisi lain, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, berjanji membuat instrumen kebijakan untuk mengaudit perusahaan dan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar HAM dalam PSN.

Sumber gambar, Albert K. Barume/UNSR
Di tengah situasi ini, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, Albert K. Barume, berkunjung ke Jayapura di Papua, pada awal Juli silam.
Dalam kunjungan informal—bukan undangan pemerintah—ia mendengarkan keluhan masyarakat adat di Tanah Papua.
“Untuk melihat, dan untuk mendengar. Lalu, saya bisa terlibat diskusi dengan pemerintah [Indonesia]. Dari apa yang saya pahami, dari apa yang saya lihat,” kata Barume.
Dalam keterangan resminya, Barume mengatakan kunjungannya “menyoroti perlunya melibatkan pemerintah secara lebih aktif dalam implementasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) sebagai instrumen yang dirancang untuk mendamaikan negara-negara dengan masyarakat adat mereka”.

Sumber gambar, Pusaka Bentala Rakyat
Menurut laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)—salah satu penyelenggara acara—masyarakat mengeluhkan tanah adat mereka yang dirampas, salah satunya oleh PSN lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan.
“Negara telah melakukan kejahatan dengan merampas tanah adat kami. Perampasan tanah adat ini terjadi di seluruh tanah Papua dari Sorong sampai Merauke,” kata Shinta salah seorang korban PSN dari Suku Malind Anim, dalam keterangan tertulis.
Anak muda dari Malind Anim, Natalis M. Kuyaka, yang tidak ikut dalam acara itu, berharap kunjungan pelapor khusus PBB bisa menggaungkan suara mereka atas keluhan, “perampasan, pencaplokan, penyerebotan yang dilakukan oleh berbagai korporasi terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat”.
“Ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup kami orang Papua, khususnya orang asli Malind,” katanya.
Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke sedang ditarget pemerintah menjadi area persawahan dan kebun tebu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Di pengujung 2024, Menteri Koordinator bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, mengungkap pembukaan lahan di Merauke bisa mencapai tiga juta hektare.
Masing-masing dua juta hektare untuk cetak sawah dan satu juta hektare untuk perkebunan tebu.
Luas lahan ini setara dengan lima kali Pulau Bali atau 45 kali luas daratan Jakarta.
Proyek yang menjadi bagian dari program Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke ditargetkan selesai waktu lima hingga tujuh tahun ke depan.
“Kalau kita mau swasembada [pangan], presiden perintahkan menterinya, termasuk swasembada energi yang mendasar, tentu ini memerlukan buka lahan baru,” kata Zulhas.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengklaim tak ada deforestasi besar-besaran dalam proyek lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan.
“Kawasan food estate di Papua Selatan itu dimulai dengan 60% lahan kosong. Tidak ada kayu, tidak ada hutan. Maka deforestasi tidak sebesar itu,” kata adik dari Presiden Prabowo itu.
Perubahan nomenklatur

Baru-baru ini atau 10 September 2025 lalu, pemerintah mengubah status PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, Provinsi Papua Selatan menjadi Program Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.
Perubahan ini dilakukan melalui Permenko bidang Perekonomian No.16/2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri bidang Perekonomian No.07/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Kami telah menghubungi pejabat di Kemenko Perekonomian pada Selasa (27/01). Namun, sampai berita ini dipublikasi, belum ada respons.
Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante perubahan nomenklatur ini tidak berdampak apa-apa di lapangan.
“Di sana, aktivitas korporasinya masih terus berjalan,” katanya.

Sumber gambar, Yayasan Pusaka
Perubahan nama juga tidak menjadi solusi atas persoalan utama yang selama ini terjadi: pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat, kata Franky.
Dengan perubahan nomenklatur, proyek ini akan diperluas cakupan wilayah dan programnya di Papua Selatan yaitu Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.
“Jadi itu artinya diperluas ke seluruh provinsi Papua Selatan,” tambahnya. Hal ini akan dibarengi dengan perubahan fungsi Kawasan hutan.
Pada awal September, pemerintah mengubah istilah PSN wilayah Merauke menjadi Program Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.
Tapi, perubahan nomenklatur tidak menyelesaikan persoalan di lapangan. Menurut Yayasan Pusaka, program ini semakin luas cakupan wilayah dan proyeknya di Papua Selatan.


Di lapangan, rencana ini disambut kecemasan sebagian suku asli yang mendiami Merauke, Malind Anim. Setidaknya itu direfleksikan dari raut wajah Yakobus Mahuze di Kampung Senayu, Distrik Tanah Miring.
Tatapannya selalu curiga melihat orang-orang asing yang datang.
Ayah tiga anak mengatakan terpaksa melepas 5.000 hektare tanah adatnya bersama marga lain kepada sebuah perusahaan untuk ditebang dan diubah menjadi kebun tebu—bagian dari PSN.
“Karena kita juga berpikir jangan sampai ada hal-hal buruk yang terjadi pada keluarga kita orang,” katanya.

Dampak dari pembukaan perkebunan tebu ini sudah nyata di depan mata. Sumber air yang biasa digunakan kebutuhan sehari-hari, telah keruh karena tercampur tanah dari pembongkaran hutan. Ikan-ikan di rawa dan sungai yang menjadi hewan buruan juga kemungkinan sudah lari entah ke mana.
Yakobus mengeklaim keluarganya masih punya 50.000 hektar hutan adat, dan ia bersikeras tak akan memberi sejengkal tanah pun untuk dibongkar dan dijadikan perkebunan.
“Kalau kita kasih semua terus binatangnya mau tinggal di mana? Terus hutan itu kan kita orang Malind, kita punya budaya itu kan kita harus ambil dari hutan,” katanya.
Siapa suku Malind Anim?
Yakobus Mahuze adalah salah satu generasi terkini kaum Malind Anim. Suku ini diperkirakan sudah menempati wilayah Papua bagian selatan ribuan tahun lalu.
Suku Malind hidup di wilayah yang terletak di antara pulau Kolepom (Pulau Dolok/Yos Sudarso) di sebelah barat, kali Digul di sebelah utara, dan perbatasan dengan Papua Nugini di sebelah timur.
Mereka mendiami daerah aliran Sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Muting. Secara administrasi, daerah itu masuk dalam Kabupaten Merauke yang tersebar di Distrik Okaba, Merauke, Kimaam, Muting, Anim-ha dan Naukenjerai.
Di Merauke, populasi mereka paling besar dibandingkan suku-suku asli lainnya, seperti suku Yei, Kanum, Mandobo dan Muyu.

Sumber gambar, KITLV
Malind Anim masih mempertahankan sistem klan atau marga yang berpusat pada sistem kepercayaan yang disebut sebagai Dema.
Saat ditanya tentang arti Dema, Yakobus sempat terdiam dan menurunkan nada bicaranya.
“Itu kan kepercayaan kita sebenarnya. Kita punya leluhur itu, kita punya moyang itu, yang mereka bilang di sini, Dema itu tuan tanah,” katanya.
Ia meyakini leluhurnya itu telah mengalihkan hak kepadanya sebagai generasi hari ini untuk menjaga tanah.
“Kalau kita kasih [tanah pada perusahaan] semua, kan berarti kita sudah mengkhianati kita punya leluhur,” tambah Yakobus.
Beberapa orang Malind menggambarkan Dema sebagai roh leluhur, atau sosok (fisik) hewan, tumbuhan atau benda-benda yang belum menjadi manusia.
Kehadirannya diyakini masih ada sampai hari ini, dan menempati hutan, sungai, rawa—apa yang disebut sebagai “tempat-tempat sakral untuk ritual adat”.
Kalangan antropolog masih punya pandangan yang berbeda tentang Dema.
Ada yang menyebutnya sebagai mitologi asal-usul manusia Malind, mencipta dan mengatur, tapi dianggap tak berpengaruh lagi setelah berlalunya masa pendahuluan mitos—beberapa tahun pertama kehidupan manusia hingga kanak-kanak.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Antropolog asal Belanda, Jan Van Baal, mengatakan Dema sebagai makhluk yang hidup di era mitos.
“Biasanya mereka mengambil bentuk manusia, tetapi kadang-kadang berubah menjadi hewan atau muncul berbentuk binatang,” tulisnya dalam tesis berjudul Dema: Description and Analysis of Marind-Anim Culture (1966).
Tak banyak yang bisa menggambarkan Dema secara utuh, bahkan generasi Malind anim saat ini.
Menurut sebuah penelitian, hal ini dikarenakan sejarah Dema sengaja ditutupi para generasi Malind di masa lalu.

Sumber gambar, KITLV
Bagaimana pun, kalangan peneliti sepakat Dema adalah nenek moyang dari marga dan sub-marga dan berkaitan dengan totem—benda, tumbuhan atau binatang yang dianggap suci—Malind Anim.
Suku Malind Anim memiliki beberapa marga dan submarga, yaitu Gebze (kelapa), Mahuze (sagu), Kaize (kasuari), Samkakai (walabi), Balagaize (buaya), Basik-Basik (babi), dan Ndiken (burung Ndik).
Kehadiran PSN di Merauke berpengaruh terhadap kemelekatan totem Malind Anim. Musababnya, semua totem ini menggantungkan hidupnya dari alam.

Ketua Forum Masyarakat adat Malind dan Kondodigun di Merauke, Simon Petrus Balagaize, yang memiliki totem buaya, mengatakan keberadaan hutan, rawa dan sungai berkaitan dengan hidup-mati suku mereka.
“Ketika buldozer atau perusahaan, hutan hilangkan rawa-rawa itu, hilangkan tempat persembunyian [buaya], otomatis dia hilangkan roh saya.” tutur Simon.
“Maka ketika buaya itu habis, roh saya kemudian lambat laun akan menjadi lemah,” katanya kemudian.

Ketua Forum Perempuan Penjaga Hutan Merauke, Emiliana Ugahiwag Gebze, bicara mewakili perempuan Malind Anim.
“Hutan kami adalah identitas kami”.
Baginya hutan adalah “kami pu (punya) supermarket'”.
“Obat-obatan, terus di situ juga untuk seperti bahan baku, bahan pangan lokal yang ada. Jadi hutan adalah segala-galanya bagi kami perempuan,” kata Emilia.
Hutan dibongkar, populasi orang asli Papua menyusut
Kami juga berbicara dengan salah satu tetua adat Malind Anim, Paulinus Naki Balagaize.
Pria berusia 72 tahun ini memiliki totem buaya dan burung garuda yang ia sebut “penguasa air dan langit”.
Bagi orang Malind, kata Paulinus, tanah, pohon dan hewan-hewan mewakili leluhur mereka, termasuk kehidupan dan diri mereka sendiri.
“Ketika dia tanahnya hilang, dia berpaling antara [tali] pusar dengan dia punya tanah. Dia terputus. Dia sudah tidak punya tujuan hidup lagi, mau ke mana,” kata Paulinus.
Ia menambahkan, “penyambungan tanah ini terjadi karena persatuan antara laki dan perempuan… makanya dianggap sakral karena itu”.

Pastor Pius Cornelius Manu di Merauke, menjelaskan relasi laki-laki dan perempuan Malind Anim dilakukan “di tanah leluhur mereka yang disakralkan”.
Hampir di seluruh ragam subetnik Malind Anim mengasosiasikan hutan, rawa dan sungai, yang bagi mereka adalah tempat-tempat sakral, dengan mama, ibu atau rahim mama.
Tapi tempat-tempat sakral itu semakin terdesak napas pembangunan dengan kehadiran pembalakan liar, pemukiman, dan yang terbaru kehadiran PSN Merauke, kata Pastor Pius.

Sumber gambar, AFP/BAY ISMOYO
Hal ini ia hubungkan dengan populasi Malind Anim yang tidak berkembang.
Sejauh ini, jumlah populasi Malind Anim terbaru belum tersedia secara rinci. Tapi, satu abad silam tak ada yang bisa menyangkal, mereka mendominasi wilayah Papua bagian selatan.
Pada 1900, diperkirakan jumlah Malind Anim khususnya di wilayah pesisir Laut Arufuru antara 8.500 hingga 10.000 jiwa, sedangkan di wilayah pedalaman mencapai 6.000 jiwa.
Namun, sebuah penelitian mengungkap jumlah suku Malind Anim saat ini hanya sekitar 19% dari seluruh populasi di Kabupaten Merauke.
Di sisi lain, para pendatang lewat transmigrasi atau pun migrasi spontan meningkat dari 4% di tahun 1970-an menjadi 41% di tahun 2005; sedangkan orang Papua pada periode yang sama dari 96% turun drastis menjadi 59%.
‘Etnosida’
Di tengah proyek yang berdampak pada hutan, dan penyusutan populasi, beberapa orang Malind menyinggung kekhawatiran soal “etnosida”—istilah yang pertama kali dikenalkan seorang Yahudi Polandia, Raphael Lemkin (1944) pada era perang dunia II atas kekerasan yang dilakukan Nazi.
Makna etnosida sering kali berkelindan dengan genosida. Tapi, menurut PBB, genosida melibatkan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama.
Sebaliknya, meskipun etnosida tidak selalu disertai dengan kekerasan fisik, tapi melibatkan bentuk penghancuran yang lebih halus—ditargetkan pada elemen-elemen tak berwujud dari identitas suatu kelompok.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Peneliti Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Cahyo Pamungkas, melihat etnosida merupakan genosida secara perlahan.
“Ketika mereka sudah kehilangan tanahnya, mereka akan tergusur, tidak memiliki akses terhadap hutan, tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan dan pekerjaan. Sehingga sama saja membunuh mereka pelan-pelan,” katanya.

“Ketika mereka sudah kehilangan tanahnya, mereka akan tergusur, tidak memiliki akses terhadap hutan, tidak memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan dan pekerjaan. Sehingga sama saja membunuh mereka pelan-pelan,” katanya.
Pius Cornelius Manu, pemuka agama yang kritis terhadap proyek pembangunan di Papua, menilai etnosida terhadap Malind Anim bukan sesuatu yang baru. Ini proses yang terus berlangsung.
Indikasinya, kata dia, penyusutan hutan karena proyek perkebunan dan cetak sawah dimulai dari era Belanda—ini biasanya diikuti dengan gelombang transmigran, sampai pemekaran wilayah yang membuat orang Papua “baku sepak”.

Di sisi lain, populasi orang asli Papua menyusut dengan kualitas rendah—indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan hampir seluruh wilayah Papua di bawah rata-rata nasional.
“Kalau seandainya orang Melanesia yang merupakan warga negara Indonesia di tanah Papua, kemudian tidak berkembang dan menuju kepunahan, ini dosa negara,” katanya.
Manusia sejati
Banyak penelitian menunjukkan jati diri Malind Anim mulai dikoyak sejak kehadiran Belanda di Merauke pada 1902—dengan pembukaan pos di muara Kali Maro.
Pada tahun ini juga lahirlah Kota Merauke—yang namanya diambil dari kesalahpahaman pendatang saat bertanya suatu perkampungan kepada warga setempat yang dijawab “Maro-ke” yang artinya “Itu sungai Maro”.
Pendudukan wilayah Merauke oleh Belanda dilatarbelakangi keluhan pemerintah Inggris terhadap kebiasaan mengayau (perburuan kepala manusia) Malind Anim ke wilayah-wilayah hingga Papua Nugini—yang saat itu dikuasai Inggris.
Sejumlah literatur, mengatakan tujuan mengayau bukan memperluas wilayah atau memakan daging manusia, tapi memperoleh nama dari target yang diserang agar bisa diberikan kepada anak-anak keturunan Malind Anim.

Sumber gambar, KITLV
Sasaran yang diserang, sebelum kepalanya ditebas ditanyakan dulu namanya. Nama ini yang kemudian diberikan kepada keturunan laki-laki mereka.
Pendeta asal Belanda, J.P.D Groen, menceritakan seorang ahli bahasa bernama Pastor Drabbe pernah menemui seorang Malind dengan “nama yang aneh”.
Menurut bahasa suku lain, namanya itu berarti “Ibu, tolong saya!”, yang lainnya memiliki nama “Saya mati”.
“[Tapi] sebelum awal abad ke-20 praktik mengayau itu lama-kelamaan mulai ditinggalkan,” tulisnya dalam situs yang merekam sejarah gereja lokal Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia–Papua (GGRI-P).

Jan van Baal, antropolog yang kemudian menjabat Gubernur Nugini Belanda pada 1953, mengatakan, maraknya pemburuan kepala manusia oleh Malind Anim kala itu, dimotivasi ketersediaan nama yang sudah habis.
Pada saat bersamaan, ada begitu banyak éwati—pejuang Malind anim yang punya hasrat besar bertarung.
Bagaimanapun, analisis antropologis terkait praktik pemburuan kepala di komunitas adat Malind Anim, masih terbatas.
Dalam perkembangannya, sejumlah antropolog pada era pascakolonial menyebut praktik pemburuan kepala semestinya tidak diinterpretasi dalam sudut pandang tunggal, apalagi diidentikkan dengan masyarakat non-Barat yang terbelakang.
“Kami tidak melihat pemburuan kepala sebagai bentuk ‘peperangan primitif’ pada tahapan evolusi… juga bukan sebagai ekspresi dari ‘sifat agresif manusia’ atau ‘kekerasan tak terelakkan’ dalam masyarakat tanpa negara akibat persaingan memperebutkan sumber daya yang langka,” tulis Janet Hoskins, profesor ilmu antropologi di University of Southern California.

Sumber gambar, KITLV
Terlepas dari interpretasi praktik pemburuan kepala mereka, istilah Malind Anim diyakini diambil dari perawakan mereka yang tinggi dan berotot serta ketangkasan berburu-bertarung. Kata “anim” berarti manusia.
Menurut penuturan keturunan Malind Anim dan sejumlah antropolog, komunitas asli di Papua Selatan ini disebut ditakuti oleh berbagai kelompok lain di sekitar ruang hidup mereka.
Orang-orang Malind Anim menyebut pencapaian identitas diri sebagai Anim-ha (manusia sejati).
Sebutan ini adalah representasi kedewasaan seorang Malind dengan kekuatan fisik dan atribut adat yang melekat di tubuh, dan memiliki kekuatan gaib.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Leonardus Moiwend, anggota MRP Merauke menyebut bangsa Malin Anim sebagai Anim-ha.
“Karena kamilah di wilayah ini, Papua ini yang menerima matahari duluan, daripada mereka di Sorong dan Jayapura”.
“Matahari itu dia bisa kasih hidup pohon, air bisa jernih, ikan bisa hidup, segala macam bisa hidup,” katanya.
Peneliti Fellow di Centre of Transdisciplinary and Sustainability Science (CTSS) IPB, Laksmi Adriani Savitri, mencatat dulunya penamaan anak laki-laki Malind terdiri dari tiga bagian: nama pertama berasal dari perburuan kepala, nama kedua diambil dari nama tanah (igih), dan ketiga berasal dari nama marga atau submarga.
Nama pertama ini, ia sebut sudah hilang seiring larangan kebiasaan perburuan kepala oleh misi Katolik dan pemerintah kolonial Belanda periode 1902-1931.
“Tetapi nama kedua tetap ada sebagai tanda asal-usul dan kepemilikan tanah,” tulisnya di Journal of Rural Indonesia (2013).
Pendudukan oleh Belanda
Salah satunya dengan mendirikan pos di Sarira atau Salerika—daerah pesisir timur. Tapi gagal.
November 1982, kapal “de Zwal” membawa residen Ternate dan Calon Kepala Pos Sarira, van Ahee bersama 10 polisi, 10 pegawai pertanian dan orang narapina untuk membangun rumah berpagar sebagai tempat perlindungan di sana.
Tapi sebulan kemudian, pos ini diserang orang Malind pada malam hari. Sebanyak 10 orang cedera dan seorang tewas, serta semua barang dicuri.
Belanda kembali mengirimkan banyak kapal untuk menemukan titik pos baru. Tapi upaya ini kembali mendapat serangan dari kaum Malind Anim yang menyebabkan tiga perwira kapal tewas.

Sumber gambar, KITLV
Aksi balasan dari Belanda terus berlanjut, salah satunya dengan straf expedite (ekspedisi hukuman) pada 1900.
Namun, tak banyak sumber yang menjelaskan dampak serangan ekspedisi ini terhadap bangsa Malind anim.
Singkatnya, pada 1902 setelah pos Belanda berdiri di Merauke, “program peradaban” yang sistematis perlahan menghapus ritual-ritual Malind Anim, hingga ke titik mereka kehilangan budaya.
Belanda mengerahkan persenjataan dan hukuman, yang mengubah kebiasaan Malind Anim.
‘Demam besi’ dan wabat penyakit
Jeroen A. Overweel dalam buku The Marind in a Changing Environment (1992), mencatat pengaruh kolonial Belanda di Merauke terhadap Malind Anim dimulai dari transaksi mereka dengan pedagang China atau Indonesia.
Orang Malind biasa menyebut pendatang sebagai pu-anim (“pu” diasosiasikan dengan suara senapan, “anim” berarti manusia).
Sejak berdiri pos Belanda di Merauke, orang Malind mulai menukar kelapa dengan besi.
Besi, bagi mereka adalah barang baru, karena secara tradisional, mereka menggunakan batu untuk kerja berat seperti mengolah sagu dan membuat perahu.
Dengan besi, kerjaan menjadi lebih mudah. Maka saat itu, terjadilah “demam besi”.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Perkakas logam ini kemudian membuat laki-laki Malind mengalihkan pekerjaan menebang pohon sagu kepada perempuan.
Perempuan dianggap bisa mengolah sagu dengan kapak besi karena itu adalah pekerjaan mudah.
“Meskipun tidak disengaja, pengenalan peralatan besi sebagai alat barter untuk kelapa menyebabkan pergeseran dalam pembagian kerja di antara kedua jenis kelamin,” kata Overweel.
Selain perdagangan, kehadiran Misi Katolik Roma juga memengaruhi budaya Malind Anim, dimulai dari kedatangan empat misionaris “Hati Kudus” pertama di Merauke pada 1905.
Dari kacamata Barat, bangsa Malind Anim dianggap primitif dan tidak bermoral, sehingga kalangan misionaris membawa sikap khas abad ke-19 yaitu “misi peradaban”.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Pada tahun-tahun pertama, para misionaris lebih banyak digunakan untuk belajar bahasa lokal, sisanya mengobati orang sakit.
Dalam prosesnya, ditemukanlah wabah yang dimulai sekitar 1909—belakangan diketahui sebagai penyakit menular seksual granuloma veneris.
Beragam spekulasi muncul tentang asal usul penyakit ini, termasuk yang dikatakan Paulinus Naki Balagaize, sebagai salah satu tetua adat Malind Anim.
Ia meyakini penyakit tersebut sengaja disebarkan.
“Karena orang Belanda [saat itu] masih di [kota] Merauke ini saja. Mereka takut jalan ke hutan ke mana-mana, takut pasti kami dibunuh… disebarlah penyakit itu,” katanya.
Betapapun, belum ada bukti sejarah tentang klaim ini.
Namun demikian, sebagian besar peneliti meyakini wabah ini berasal dari orang luar.
Wabah yang membunuh banyak kaum Malind ini berlangsung tepat setelah Kota Merauke berdiri.

Sumber gambar, KITLV
Maaike Derksen, pengajar budaya dan sejarah di Radboud University Nijmegen, menyebut misionaris Katolik memegang peran dalam struktur kolonial yang diterapkan Belanda di wilayah Papua Selatan.
Bukan cuma menjalankan apa yang mereka klaim sebagai “misi peradaban”, Maaike menyebut misionaris Katolik juga melakukan pasifikasi terhadap orang-orang Malind Anim.
Istilah pasifikasi, dalam konteks kolonialisasi, salah satunya didefinisikan sebagai “upaya mengeliminasi masyarakat adat yang dengan cara membangun masyarakat baru di tanah yang dirampas”.
Pada konteks Malind Anim, Maaike Derksen menyebut, “kolaborasi misionaris Katolik dari ordo Kongregasi Misionaris Hati Kudus (MSC) dengan otoritas kolonial Belanda makin intensif pada dekade 1920-an, dalam rangka pasifikasi Nugini Belanda wilayah selatan”.
Salah satu wujud proyek pasifikasi yang disebut Maaike adalah mendirikan “kampung-kampung percontohan” untuk memukimkan komunitas Malind Anim.

Sumber gambar, KITLV
Angka kematian akibat wabah di tanah Malind Anim telah memangkas seperempat populasi mereka.
Di tengah situasi ini, muncul gagasan mengurangi penyebaran penyakit, dengan mendirikan “Desa Teladan” yang dimulai pada 1913 di Okaba, dan yang kedua pada 1914 di Merauke.
Desa teladan ini bertujuan mencegah penyebaran penyakit dengan membuat rumah-rumah bagi Malind Anim sebagaimana orang Barat: tinggal di rumah keluarga yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya—hal yang bukan menjadi tradisi Malind.
Tradisi Malind Anim adalah mereka memiliki tempat tinggal terpisah antara laki-laki dan perempuan, bahkan saat mereka sudah menjadi ‘suami-istri’.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Untuk mengatasi wabah, rumah sehat juga didirikan. Gunanya, memisahkan mereka yang sakit dan sehat.
Orang-orang Malind mulai diberikan pakaian—yang secara otomatis memaksa mereka melepas atribut adat yang melekat di tubuh.
“Salah satu orang Malind di bagian selatan daratan Merauke, mengingat dan mengisahkan cerita yang diwarisi dari neneknya yang menyaksikan orang Malind menangis terisak-isak ketika atribut adat dilepaskan dari tubuhnya,” tulis Muntaza.
Sebaran penyakit ini juga diperparah dengan wabah influenza yang terjadi pada 1918.
Akibatnya, populasi Malind makin berkurang rata-rata 18,5% dalam waktu dua pekan.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Serangan penyakit menular yang membunuh orang Malind Anim ini telah menjadi perhatian para misionaris, karena mereka menganggap suku Malind sudah berada di ambang kepunahan.
Salah satu misionaris yang menaruh perhatian terhadap penyelamatan ini adalah Pastor Vertenten.
Ia memulai kampanye dengan menulis artikel Zuid-Nieuw-Guinea sterft uit (Nugini Selatan punah) di koran-koran Hindia Belanda pada 1919 dan 1920.
Pemerintah Belanda kemudian mulai melakukan intervensi dengan penelusuran jenis penyakit hingga pengobatan.
Oada 1948, Malind Anim disebut telah terbebas dari penyakit granuloma veneris.
Bagaimana budaya Malind Anim memudar?
Menurut Overweel, kehadiran Belanda di tanah Merauke membawa aturan-aturan, termasuk larangan perburuan kepala.
Aturan ini secara tidak langsung ikut melenyapkan kebiasaan mereka, terutama laki-laki: berperang.
Dampaknya, laki-laki Malind mengurangi kegiatan membuat persenjataan, dan perahu perang.
Pesta yang disertai tari-tarian yang berkaitan dengan mengayau juga semakin dibatasi.
Program ‘desa teladan’ untuk mengurangi wabah penyakit, secara tidak langsung juga melucuti budaya Malind Anim.
Semua pesta adat, dan tarian yang terkait dengan ritual kesuburan dilarang.
Di desa-desa ini kemudian menjadi “pusat peradaban”, tempat sekolah-sekolah misi didirikan.

Sumber gambar, KITLV
Program yang diusulkan Pastor Vertenten ini dianggap berhasil karena “penyakit pes menghilang di wilayah pesisir, dan jumlah bayi baru lahir yang sehat kembali meningkat”.
“Namun, dari sudut pandang budaya, program ini benar-benar mengubah masyarakat Malind dengan menyingkirkan aspek-aspek yang memainkan peran penting dalam keseluruhan kompleks sosio-religius, yang terpenting adalah perburuan kepala dan upacara inisiasi dan kesuburan,” kata Overweel.

Sumber gambar, Nationaal Archief/Kantor Informasi dan Penyiaran Radio Belanda Nugini
Kehadiran korporasi dan kendali atas Malind Anim
Laksmi Adriani Savitri dalam bukunya Korporasi dan Politik Perampasan Tanah (2013), menyebut program Desa Teladan sebagai awal penguasaan dan pengendalian tanah Malind anim.
Kaum Malind Anim di setiap kampung-kampung kecil yang tersebar, sudah punya tatanan sosial budaya yang mengatur siapa tuan tanah dan siapa yang bukan.
Mereka juga sudah punya aturan siapa yang berhak memanen, menanam, dan mengambil, dan siapa yang tak memiliki hak tersebut. Nama tengah Malind Anim juga merujuk pada asal usul tanah.

Sumber gambar, Nationaal Archief/Kantor Informasi dan Penyiaran Radio Belanda Nugini
“Kalau pada awalnya semua menjadi tuan di tanah sendiri, setelah masa-masa penyatuan kampung, ada yang menjadi ‘penumpang’,” tulis Laksmi.
“Artinya, ia tidak memiliki hak atas tanah yang ditinggali, kecuali hak untuk menjaga yang diberikan oleh si tuan tanah atau tuan dusun.”
Kendali atas tanah Malind Anim berlanjut dengan proyek padi Kumbe Belanda pada 1954, ketika perusahaan swasta asing diberikan konsesi areal seluas 10.000 hektare.
Pembukaannya, dimulai 60 hektare di wilayah Kurik sampai Kumbe sebagai percobaan.

Sumber gambar, Nationaal Archief/Kantor Informasi dan Penyiaran Radio Belanda Nugini
Rencana menjadikan Papua bagian selatan sebagai pusat pertanian dan peternakan, tak lepas dari rencana enam negara Barat, yaitu Belanda, Australia, Selandia Baru, Prancis dan Amerika Serikat untuk pengembangan daerah Pasifik Selatan.
Saat itu disebut belum ada tenaga kerja dari luar. Oleh karena itu, warga setempat (Muyu dan Malind) dilibatkan sebagai pekerja kasar, seperti membuat polder.

Sumber gambar, Nationaal Archief/Kantor Informasi dan Penyiaran Radio Belanda Nugini
Hasil produksi padi pada 1956 mencapai 32 ton—diangkut dari Kurik ke Merauke. Beras juga dikirim sampai ke Holandia (sekarang Jayapura) dan Biak.
Namun tidak semua hasil sawah memuaskan, karena di beberapa tempat bentuk padi gepeng dan banyak yang hampa. Hal ini karena tanahnya berpasir dan asam.
“Rice estate ini berproduksi mulai dari 1956 sampai 1962, bahkan awalnya direncanakan untuk dikembangkan sampai ke perkebunan tebu,” jelas Laksmi.
“Usaha ini berhenti ketika terjadi peralihan pemerintahan dari Belanda ke Indonesia.”

Sumber gambar, Merauke.go.id
Pada era orde baru, situs padi Kurik ini berubah menjadi Balai Benih Industri, dengan wilayah kendali penanaman mencakup 60 hektare.
Proyek kolonial Belanda ini lalu dijadikan bukti kejayaan pengusahaan padi berskala luas oleh Bupati Merauke, John Gluba Gebze.
Ia kemudian mengajukan konsep Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) pada 2001.
Gayung bersambut, pemerintah pusat kemudian menggodok MIRE menjadi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE).
Proyek yang dimulai pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini kemudian menuai polemik, termasuk adanya ancaman hilangnya 200.000 hektare hutan alam.

Sumber gambar, bkpm.go.id
Pertama, program ini akan mengganti produsen pangan dari petani ke tangan koorporasi. Imbasnya, kendali perut masyarakat nantinya berada di tangan pengusaha, mulai dari produksi, distribusi hingga harganya.
Kedua, terjadi perampasan tanah masyarakat, kerusakan lingkungan, hingga kegagalan proyek yang berulang.
MIFEE yang kandas dilanjutkan dengan program cetak sawah yang ditargetkan 1 juta hektar, dan terealisasi 10.000 hektar pada 2015-2017 atau program Lumbung Pangan Nasional (LPN). Kini, berlanjut dengan program optimalisasi lahan (Oplah) yang menjadi bagian dari PSN di Merauke.

Sumber gambar, BPMI Setpres/Rusman
Kehadiran perusahaan membawa uang untuk tanah menimbulkan perbedaan pandangan di antara kaum Malind: menolak dan menerima.
“Ini menjadi sumber dari pertikaian dalam keluarga, antara paman dan keponakan, antara kakak dan adik, atau antara satu kampung dan kampung lain,” kata Laksmi.
Selain itu, terjadi pergeseran pandangan sebagian Malind Anim tentang alam yang dapat dikomodifikasi. Tanah kemudian disewakan untuk memperoleh uang.
“Ini satu pengetahuan yang baru terhadap makna dan nilai dari tanah sebagai komoditi yang kemudian masuk ke dalam logika orang Malind berhadapan dengan komodifikasi alam,” katanya.

Sumber gambar, Yayasan Pusaka
Bagaimana pun, seluruh proyek cetak sawah yang pernah, dan sedang berlangsung tak membuat orang Malind menjadi petani, kata Laksmi.
“Karena akses terhadap permodalan, akses terhadap teknologi, akses terhadap pengetahuan, semuanya terjadi secara diskriminatif dan rasialis… Ketidakpercayaan kepada kemampuan orang Malind untuk menabung atau mengambil kredit di bank misalnya, itu memustahilkan mereka untuk terintegrasi kepada sistem pertanian,” tambah Laksmi.
Gelombang transmigrasi

Sumber gambar, Nationaal Archief/Kantor Informasi dan Penyiaran Radio Belanda Nugini
Masih berdasarkan catatan Laksmi Adriani Savitri, gelombang transmigrasi juga punya pengaruh terhadap kehidupan Malind Anim.
Hal ini ia tulis juga dalam riset Nekropolitik Negara: Militerisasi Produk Pangan di Tanah Malind Anim yang diterbitkan Yayasan Pusaka Bentala (2025).
Dari catatannya, sejak Belanda membuka pos di muara kali Maro, mereka sudah mendatangkan orang-orang Jawa sebagai pembantu rumah tangga residen, kontrolir dan staf pemerintahan kolonial Belanda.
Namun seiring dengan bertambahnya pegawai dan penduduk di Kota Merauke, Belanda mulai kesulitan memasok bahan pangan.
Solusinya, mereka mendatangkan lebih banyak orang Jawa pada 1908 untuk menanam padi dan sayur-mayur yang ditempatkan di Kuprik, Distrik Semangga.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Selain itu, kedatangan mereka juga disertai penempatan orang-orang dari pulau Rote dan Timor untuk beternak dan menjaga sapi serta kuda milik pegawai-pegawai Belanda.
“Semua itu dijalankan dengan peperangan yang mengakibatkan kepala-kepala suku Malind itu ada yang dibuang ke Ambon.”
“Jadi, sejak saat itu sampai hari ini, sebenarnya moda yang dilakukan untuk menaklukkan bangsa Malind adalah moda-moda kolonial,” kata Laksmi.
Kedatangan orang-orang Jawa ini berlanjut pada 1910, seiring dengan penempatan mereka ke Fiji dan Suriname sebagai buruh kontrak di perkebunan-perkebunan milik orang Belanda.
Mereka yang didatangkan pada 1910 ditempatkan di Spadem dan Mopah lama. Arus kedatangan mereka terus berlangsung sampai 1925.

Sumber gambar, Wereld Museum Collection
Lalu, transmigrasi ke Merauke pada masa pemerintahan Suharto (1982-1984) dirancang untuk mobilisasi tenaga kerja demi produksi beras.
Para transmigran sebagian besar ditempatkan di wilayah yang dialokasikan atau pernah dibuka untuk pertanian padi sawah.
“Sebelum itu, ada operasi militer besar-besaran di wilayah Merauke sebetulnya dari ujung utara sampai dengan ujung selatan,” katanya.
“Di Merauke ini dipimpin Jenderal Benny Moerdani yang mengakibatkan banyak bangsa Malind ini mengungsi ke PNG. Dalam kekosongan tanah dan kekosongan penduduk seperti itu, kemudian transmigran datang.”
Kehadiran transmigran perlahan juga membawa perubahan pola makan Malind anim. Dalam dua dekade terakhir, beras dan mi instan kian mendominasi, menggeser sagu dan umbi-umbian.
Laksmi menyebut istilah culturecide (pembunuhan kebudayaan) Malind Anim, yang dimulai sejak pendudukan Belanda hingga pemerintahan Indonesia.

“Jadi sekarang ini kondisi bangsa Malind ini berada di titik yang super darurat dari masa kolonial sampai dengan sekarang,” katanya.
Hal ini disampaikan langsung oleh sebagian kaum Malnd Anim.
“Sebenarnya yang saya rasakan itu sebenarnya saya rasa seperti sedang dalam pemusnahan atau mereka lagi bunuh saya dari semua sisi,” kata Leonardus.
Simon Petrus Balagaize melihat proyek PSN ini adalah yang terbesar dalam melucuti budaya Malind anim dibandingkan gelombang perubahan sebelumnya.
“Ini berarti sejarah Indonesia, sejarah dunia untuk menghilangkan suku-suku,” katanya.

Sumber gambar, Dok. Pribadi
Patricius Samkakai dari Distrik Okaba, menyebut kampungnya sudah masuk titik koordinat PSN.
“PSN ini bukan bagian dari Malind. Itu [bagian] dari pu-anim.”
“Kami sudah lakukan salib merah menandakan bahwa sasi itu sudah kami lakukan, agar pemerintah masuk pun kami sudah punya lambang itu bahwa kami tidak terima perusahaan seperti itu,” kata Patricius.
Natalis M. Kuyaka juga bertanya-tanya tentang dalih pembangunan dan kesejahteraan yang kerap dibawa pemerintah di tanah kelahirannya.
“Kalau Indonesia betul-betul mau membangun kami orang Papua, kami sudah harusnya sejahtera sudah sejak tahun 60-70-an, bukan di tahun-tahun modern sekarang ini,” katanya.
Tuduhan pelanggaran HAM di PSN Merauke
Komnas HAM telah melakukan pengamatan situasi di lokasi PSN di Merauke pada 22-25 Juni lalu dan melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan, serta pemerintah setempat.
Pengamatan ini bertujuan mendalami situasi HAM dalam pelaksanaan sejumlah PSN, khususnya program cetak sawah untuk ketahanan pangan dan perkebunan tebu untuk bioethanol dalam rangka ketahanan energi, yang berdampak langsung pada masyarakat adat.
Hasilnya, lembaga ini menemukan beberapa persoalan, antara lain: pengabaian prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), tidak diakuinya hak-hak ulayat masyarakat adat, dan berkurangnya ruang hidup dan sumber kehidupan masyarakat adat.

Sumber gambar, Komnasham.go.id
Selain itu, lembaga ini juga menemukan adanya penggusuran paksa atas lahan masyarakat adat, kerusakan lingkungan dan budaya lokal, serta keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan PSN.
PSN di Merauke juga sudah menjadi sorotan PBB. Sembilan pelapor khusus PBB menduga telah terjadi pelanggaran hak-hak masyarakat adat akibat PSN Merauke.
Mereka mengirim surat kepada pemerintah Indonesia, dan perusahaan PT Global Papua Abadi.
“Kami juga menerima laporan bahwa komunitas adat menghadapi intimidasi dan kriminalisasi seiring dengan kehadiran militer yang mendampingi perusahaan dalam proses pembukaan lahan hutan,” tulis pelapor PBB.
Dalam balasannya, pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa mengatakan, pengembangan PSN Merauke telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan tata guna lahan dan rencana tata ruang.
“Proyek ini berada dalam kawasan Hutan Produksi yang telah ditetapkan di Provinsi Papua Selatan, dan hingga saat ini belum ada permohonan dari pihak mana pun untuk mengklasifikasikan wilayah tersebut sebagai tanah adat,” bunyi surat yang ditandatangani oleh Dubes Achsanul Habib, Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) PTRI Jenewa.
Pemerintah pun menegaskan bahwa kepemilikan lahan PT Global Abadi, salah satu perusahaan yang terlibat dalam proyek ini, telah didukung secara hukum dengan Hak Guna Usaha (HGU).

Sumber gambar, Yayasan Pusaka
Dalam penutup surat itu, Achsanul Habib menegaskan kembali, pemerintah Indonesia akan “terus berkomitmen secara maksimal dalam memajukan dan melindungi HAM” bagi seluruh rakyatnya.
BBC News Indonesia mengkonfirmasi tuduhan soal etnosida yang sedang berlangsung di Papua bagian selatan ini kepada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto. Tapi ia menanggapinya dengan gerakan menyatukan telapak tangan di depan dada.
Menteri HAM, Natalius Pigai, mengaku pihaknya memiliki beberapa standar yang harus dipatuhi terkait pembangunan PSN.
“Izin harus [ada] partisipasi masyarakat yang mengizinkan. Tanah harus clean and clear… Negara harus mesti untung dan perusahaan juga untung. Kelestarian alam harus diperhatikan,” katanya.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Dia kemudian mengatakan, Kementerian HAM juga telah memiliki instrumen bernama Prisma, yang pada masa datang akan menerapkan mandatori audit perusahaan dan menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar.
“Tetapi itu mungkin 2026 atau 2027, setelah semua aturan dan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan sudah berjalan,” jelas Natalius.
Bagaimana pun, situasi di lapangan menunjukkan perpecahan. Sebagian masyarakat Malind Anim menerima melepas tanahnya, sebagian lainnya menolak keras, sebagaimana Yakobus Mahuze yang tak akan memberikan sejengkal tanah adatnya.
“Kalau kita tinggal diam terus, kita nanti diinjak terus, makanya kalau memang ada yang datang dari pihak manapun saya harus hadapi apapun yang terjadi… Saya tidak akan pernah mau lari, saya tidak lari,” tutur Yakobus.