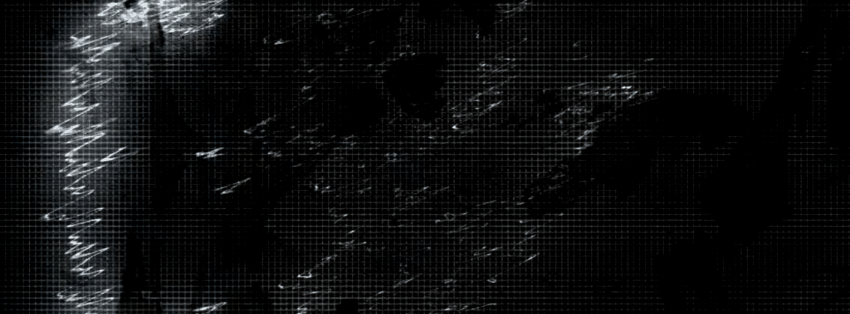“Kesedihan emak enggak punya anak,” ungkap Ronasih dengan suara yang lirih. Sorot matanya gelisah seakan ingin membalikkan waktu ke masa lalu.
Namun Ronasih hanya pasrah dan terbaring lemah di atas tikar tipis sebagai alas tidurnya, saat ditemui di rumahnya pada 2019 silam.
Ronasih adalah penyintas “ianfu”, perempuan yang dipaksa menjadi budak seks militer Jepang saat pendudukan Jepang pada 1942-1945, di Sukabumi, Jawa Barat.
Kala berusia 14 tahun, perempuan yang akrab disapa Mak Acih ini diculik tentara Jepang saat hendak berangkat ke sekolah. Dia lalu disekap di barak dekat desanya.
Akibat apa yang dialami, Ronasih dan puluhan ribu “ianfu” lainnya di Indonesia mengalami trauma berat akibat kekerasan fisik, psikologis, trauma seksual, ketidakseimbangan mental, penderitaan sosial dan ekonomi.
Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 14 Agustus 1945—atau 15 Agustus, menurut kalender Jepang—Ronasih mencoba menata kembali hidupnya yang hancur.
Namun pernikahannya kandas dan mimpinya memiliki anak pun sirna. Di usia senja, Ronasih hidup sebatang kara.
Ditemani kucing kesayangan bernama Desi, Ronasih hidup seorang diri dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.
Gubuk yang reyot ditempati sungguh tidak layak ditinggali.
Dinding dari bambu sudah mulai bolong, angin akan leluasa berhembus melaluinya. Sarang laba-laba menggantung di langit rumah.
Saat hujan, air menetes ke dalam rumah karena sela-sela genteng yang mulai renggang. Kakus pun tak ada.

Sumber gambar, Rahmad Azhar Hutomo
Selain kondisi rumah yang tak layak huni, kondisi kesehatan Mak Acih pun tak lagi mumpuni.
Tubuhnya kurus. Lemas dan sakit kepala sering dirasakannya.
Bahkan, ia hanya bisa merangkak karena lututnya tak kuat menopang berat badannya.
Meskipun kondisi kesehatan fisik kian memburuk, namun ingatan Mak Acih masih tajam.
Di tengah malam yang sunyi, Ronasih menggenggam tasbih dan melantunkan doa.

Sumber gambar, Rahmad Azhar Hutomo
Sama seperti Ronasih, Umi Kulsum dijadikan “ianfu” saat berusia belasan.
Dua kakak perempuannya, Otih dan Ismaya, diculik di depan kedua orang tua mereka. Mereka lantas dibawa di ianjo yang berlokasi tak jauh dari rumah mereka.
Malang bagi kedua kakak Umi, mereka tak berumur panjang akibat pemerkosaan yang mereka alami selama disekap di ianjo—sebutan untuk rumah bordil militer Jepang.
Sedangkan Umi yang baru berusia 11 tahun, diperkosa dua tentara Jepang di ianjo yang tak jauh dari rumahnya.
Suatu hari sepulang dari menengok kedua kakaknya di ianjo, Umi Kulsum dicegat oleh dua tentara Jepang yang membujuknya masuk ke dalam asrama yang letaknya berada di belakang bangunan utama yang difungsikan sebagai ianjo.
Di sana, dia mengalami kekerasan seksual bertubi-tubi. Umi Kulsum meninggal pada 2019 silam.
Berbeda dengan para “ianfu” lainnya yang tak memiliki anak, Umi Kulsum dikaruniai empat orang anak, termasuk Nendra Sanhita.
“Saya ingin pemerintah Jepang meminta maaf kepada ibu saya, dan korban “ianfu” lain, selain itu untuk para korban diberikan kompensasi atas penderitaan yang telah dialami akibat perang,” ujar Nendra.

Sumber gambar, Rahmad Azhar Hutomo
Keberanian Nendra Sanhita bersikap tegas menyuarakan isu ini memunculkan perspektif lain bagaimana memahami luka dan trauma kekerasan seksual terwariskan ke generasi berikutnya.
Indonesia memiliki tiga versi angka penyintas “ianfu”. Versi pertama dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mencatat 1.156 orang pada tahun 1993.
Mereka berasal dari Yogyakarta, Gunungkidul, Sleman, Bantul, Kulonprogo, Banyuwangi, Magetan, Lampung, Salatiga, Karanganyar, Magelang, Sukoharjo, Probolinggo, Surakarta, Temanggung, Semarang, dan Nusa Tenggara Timur.
Versi kedua, berdasarkan pernyataan Forum Komunikasi Eks Heiho Indonesia, mencatat 23.277 orang pada tahun 1996. Versi ketiga, menurut Yayasan Yugun “ianfu” Sulawesi Selatan, mencatat 1.696 orang pada tahun 2003.
Sementara itu, menurut akademisi Yoshiaki Yoshimi, setidaknya 50.000 hingga 200.000 perempuan menjadi korban. Mereka berasal dari Jepang, Korea, China, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.
Beberapa dari mereka bahkan berasal dari negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan Portugal.
Tapi, 80 tahun setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia merdeka, hingga ini luka dan trauma para penyintas “ianfu” tak lekang oleh waktu.
Perbudakan seksual terbesar yang pernah terjadi sekitar tahun 1942–1945 belum pernah benar terselesaikan, dan tragedi ini dibungkam sebagai hal tabu oleh masyarakat.

Sumber gambar, Rahmad Azhar Hutomo
Tahun 2000 menjadi tonggak sejarah saat Tribunal Internasional menyoroti hak-hak “ianfu” yang belum terpenuhi. Namun, meski menarik perhatian internasional, hal itu tidak serta-merta mengarah pada komitmen politik untuk memenuhi hak para penyintas.
25 tahun setelah tribunal, tuntutan para penyintas belum semua terpenuhi. Saat ini, isu “ianfu” telah menjadi isu global melalui berbagai kelompok solidaritas, tidak hanya di negara-negara Asia dan Amerika Serikat, tetapi juga melalui keterlibatan parlemen dan majelis kota dari berbagai negara serta organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Gerakan ini menuntut pemerintah Jepang bertanggung jawab atas penderitaan para penyintas, serta mengakui adanya unsur paksaan dalam mobilisasi perempuan untuk praktik perbudakan seksual selama periode Perang Asia-Pasifik.
Gerakan ini pula menuntut pemerintah Jepang mengadili para pelaku kejahatan perang dan kejahatan mobilisasi seksual yang telah mereka lakukan.
Selain itu, pemerintah Jepang dituntut memberikan permintaan maaf resmi atas luka sejarah dengan bahasa yang jelas dan bersih, tanpa praktik bahasa yang sewenang-wenang atau ambigu.
Lebih spesifik lagi, permintaan maaf tersebut harus disertai kompensasi langsung dari kas negara kepada para penyintas.
Keempat, pemerintah Jepang membuka seluruh arsip terkait “ianfu”, serta mengajarkan materi sejarah “ianfu” dalam buku pelajaran sekolah sebagai bagian dari ingatan sejarah bangsa, agar pelajaran dari peristiwa ini dapat diwariskan ke generasi berikutnya.
Praktik sistem “ianfu” adalah isu yang masih diperjuangkan hingga tahap internasional dengan menggunakan instrumen-instrumen perangkat hukum internasional.
Pelapor Khusus PBB, Radhika Coomaraswany, mengatakan Perjanjian Perdamaian San Fransisco yang ditandatangani pada 8 September 1951 dan berbagai perjanjian bilateral Indonesia-Jepang (1958), Korea-Jepang (1965), China-Jepang (1972) tidak mencantumkan pasal atas kerusakan kemanusiaan akibat pelanggaran hak-hak kemanusiaan secara umum atau perbudakan seks militer secara khusus.
Dengan demikian, menurut Radhika, pemerintah Jepang tetap harus bertanggung jawab secara legal atas pelanggaran-pelanggaran hukum kemanusiaan internasional.
Foto dan teks oleh fotografer lepas Rahmad Azhar Hutomo