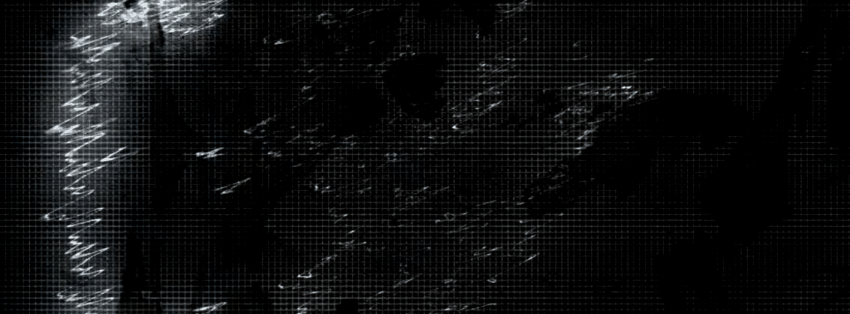Sumber gambar, ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Presiden Prabowo Subianto mengeklaim persentase pengangguran Indonesia berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998. Mengapa klaim ini dianggap tidak menggambarkan kenyataan di lapangan?
Para pengamat berpendapat metode perhitungan tingkat pengangguran yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS)—yang kemudian dicuplik Prabowo—memiliki keterbatasan indikator, problematik, dan tidak mampu menggambarkan realita masyarakat.
Salah satu indikator problematik BPS adalah mendefinisikan seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam sepekan ke dalam kelompok masyarakat bekerja dan bukan pengangguran, kata seorang pengamat ketenagakerjaan.

Sumber gambar, Muhammad Fadli/Bloomberg via Getty Images
“Kalau seseorang hanya bekerja sejam [dalam] seminggu, apakah ia bisa memenuhi kebutuhan hidup?” kata pengamat ketenagakerjaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), El Bram Apriyanto.
BBC Indonesia juga mewawancarai sejumlah masyarakat yang dikecualikan BPS dari kelompok pengangguran, tapi bekerja di sektor informal dengan jam kerja panjang, tanpa kontrak, dan jaminan sosial.
Kondisi inilah yang membuat mereka berpotensi tergelincir ke dalam kelompok pengangguran dan kemiskinan versi BPS.
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan penurunan angka pengangguran sebagai kewenangan BPS, tapi tak menutup mata soal keluhan kesulitan mencari pekerjaan oleh masyarakat.
Penyebab pengangguran turun – perhitungan rumus, keterbatasan indikator
Penurunan angka pengangguran dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.
Ia merujuk hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dirilis BPS enam bulan sebelumnya.
Kala itu, BPS mencatat tingkat pengangguran per Februari sebesar 4,76% atau turun 0,06 dari periode sama tahun sebelumnya.
Adapun pada Februari 1998, angka pengangguran tercatat 5,46%.
“Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo.
Klaim Prabowo ini dipertanyakan sejumlah pengamat, karena dianggap tidak dapat menggambarkan realita di lapangan.

Sumber gambar, JUNI KRISWANTO/AFP
Pengamat ketenagakerjaan BRIN, El Bram Apriyanto mengatakan, definisi ‘bekerja minimal satu jam seminggu” memang selaras dengan poin 94 International Conference of Labour Statisticians (ICLS) ILO yang disepakati 1982.
Namun, terang Bram, “definisi itu sudah berusia lebih dari 40 tahun.”
Ia mengatakan, definisi bekerja minimal satu jam seminggu memang dapat digunakan untuk tujuan statistik dan memudahkan perbandingan global.
Tapi, sambungnya, terlalu sempit jika dipakai untuk memaknai kesejahteraan masyarakat.
Untuk memahami kondisi tenaga kerja sebenarnya, pemerintah dinilai perlu juga melihat indikator lain seperti tingkat underemployment (setengah pengangguran) yang menunjukkan bahwa seseorang bekerja tapi pendapatannya tidak mencukupi.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Kondisi underemployment (setengah pengangguran) sendiri tidak diklasifikasikan BPS sebagai pengangguran.
Selain itu, pemerintah juga perlu melihat jumlah pekerjaan informal; median upah dibandingkan dengan upah minimum; berapa % pekerja yang punya kontrak; jumlah pekerja yang sudah terdaftar jaminan sosial; serta bagaimana kualitas hidup mereka.
“Inilah keterbatasan indikator TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka). Angka TPT bisa turun, tapi tidak serta-merta berarti kesejahteraan membaik. Perlu indikator lain,” kata Bram.
“Sekadar mengatakan angka pengangguran turun tidak otomatis rakyat lebih sejahtera.”
Perihal indikator yang problematis juga disampaikan Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.

Sumber gambar, BAY ISMOYO/AFP via Getty Images
Ia mengatakan, data itu seharusnya dikonfrontir dengan indikator lain untuk kemudian bisa menjelaskan realita di lapangan.
Beberapa indikator tersebut, antara lain, data bahwa mayoritas angkatan kerja Indonesia saat ini bekerja disektor informal dengan ketiadaan perlindungan sosial, upah kecil, tapi jam kerja lebih panjang.
“Sebaiknya pemerintah tidak menggunakan klaim secara makro… Ini membuat klaim pengangguran terendah sejak 1998 itu patut diragukan karena harus dikonfrontir dengan berbagai indikator ketenagakerjaan lainnya,” tutur Bhima.
Pengamat ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Qisha Quarina menjabarkan, turunnya persentase angka pengangguran di data BPS yang dilansir pada Februari lalu sejatinya berakar pada rumus perhitungan angka pengangguran yang membagi total pengangguran dengan total angkatan kerja nasional.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Angkatan kerja Indonesia yang dalam rumus dinamakan “bilangan penyebut” naik dibanding 2024, sehingga nominal pembagi dalam rumus menjadi lebih besar yang otomatis bakal mengecilkan hasil akhir.
“Bilangan penyebut lebih tinggi, ya, makanya dia [tingkat pengangguran] turun,” kata Qisha.
Secara umum, jumlah total pengangguran di Indonesia yang diistilahkan sebagai “pengangguran absolut” sejatinya naik dibanding 2024, terang Qisha.
Per Februari 2025, jumlah pengangguran Indonesia tercatat 7.278.307 jiwa atau meningkat dibanding periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 7.194.862.
Jumlah pengangguran terendah sejak krisis 1998 sendiri tercatat pada Februari 2019 yakni 6,82 juta orang.

Sumber gambar, Adem Salvarcioglu/Anadolu Agency/Getty Images
Alhasil, terang Qisha, “Kuncinya, jangan melihat dari satu sisi. Ketenagakerjaan itu kompleks.”
Menteri Tenaga Kerja, Yassierli enggan berpolemik soal data pengangguran dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah kewenangan BPS.
Namun, Yaasierli mengaku tidak menutup mata atas keluhan masyarakat soal kesulitan mendapat pekerjaan.
“Itu hal yang kami perhatikan,” kata Yassierli di laman Detik.com.
Menurutnya, pemerintah terus melakukan banyak hal agar lapangan pekerjaan terus tersedia, seperti lewat Koperasi Merah Putih dan Program Magang ke Luar Negeri.
Waspada peningkatan pekerja informal
Alih-alih “menjual” tingkat pengangguran yang turun, para analis berpendapat, pemerintah semestinya memperhatikan perihal maraknya pekerjaan informal di Indonesia.
Merujuk BPS, proporsi pekerja informal di Indonesia mencapai 59,40% per Februari 2025, dari sebelumnya 59,17% pada Februari 2024.
Sementara proporsi pekerja formal turun menjadi 40,60% per Februari 2025, dari sebelumnya 40,83% pada Februari 2025.
Data itu menunjukkan bahwa kenaikan pekerja tidak diikuti dengan perbaikan kualitas pekerjaan.
Sejawat Qisha di UGM, Nabiyla Risfa Izzati yang berfokus pada studi hukum ketenagakerjaan menambahkan, peningkatan proporsi pekerja informal harus menjadi perhatian pemerintah.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Pasalnya, pekerja informal tidak akan mendapat perlindungan hukum ketenagakerjaan yang kuat dan jaminan sosial sehingga potensi membangun kehidupan yang lebih bermartabat berkurang.
“Sektor informal kan tidak terlindungi. Apa yang disebut descent work tidak bisa didapat,” kata Nabiyla.
Nabiyla menyebut fenomena peningkatan pekerja informal sebagai “sinyal bahaya” perekonomian Indonesia.
“Yang paling jelas, [sinyal] industrialisai yang tidak berjalan. Sektor formal kan bergerak ketika ada infustrialisasi,” katanya.
Dalam jangka panjang, ia pun mengkhawatirkan perekonomian Indonesia tidak akan meningkat jika fenomena ini tidak diatasi dengan baik.

Sumber gambar, Yuli Seperi/Getty Image
“Secara ekonomi, agak sulit menggenjot ekonomi kalau hanya berasal sektor informal. Formal lebih punya power untuk menggerakan ekonomi,” ujarnya.
“Percuma juga kita punya UMR, UMP, tapi yang banyak adalah pekerja informal.”
Senada pernyataan El Bram Apriyanto, yang menilai pekerja informal umumnya tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan.
Artinya, terang Bram, mereka tidak memikiki perlindungan finansial jika sakit, kecelakaan kerja, atau mengalami pemutusan kerja
Lantaran tidak ada kontrak kerja tertulis, posisi tawar pekerja lemah juga di hadapan pemberi kerja atau konsumen, kata Bram.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Selain itu, status yang tidak tercatat secara formal juga membuat pekerja informal akan sulit mengakses kredit perbankan, pelatihan, atau program peningkatan keterampilan.
Akibatnya, produktivitas mereka stagnan dan sulit naik kelas ke sektor formal.
“Kerentanan ekonomi pekerja informal juga berimbas pada keluarga mereka. Anak-anak dari keluarga pekerja informal sering kesulitan mengakses pendidikan yang memadai, sehingga berisiko mengulang pola yang sama: menjadi pekerja informal di masa depan,” ujar Bram.
Cerita pekerja informal yang tak dihitung pengangguran — dibayar murah, terpaksa mengutang, hingga bekerja overtime
BBC berbincang dengan beberapa masyarakat yang tidak diklasifikasikan BPS ke dalam kelompok pengangguran karena bekerja di sektor informal.
Mereka menyambung hidup dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga atau pengemudi ojek online, tanpa jaminan sosial, bayaran di bawah upah yang dipatok pemerintah, serta kontrak kerja yang jelas.
Telapak tangan Wahyu Dwi Kawarti (45) yang sehari-hari bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah di kawasan Nayu, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, itu begitu terasa kasar.
Saban hari, ia berangkat dari rumah kontrakannya menuju rumah majikan yang masih dalam satu kelurahan sekitar pukul 06.00 WIB.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Sejak pagi, ibu empat anak itu akan mulai beraktivitas mulai dari membersihkan rumah hingga mencuci pakaian milik majikan dan keluarganya. Kegiatan itu akan rampung hingga jarum jam menunjukkan pukul 12.00 WIB.
Setelah cukup istirahat, Wahyu akan kembali memulai aktivitas sebagai pembantu di rumah majikannya itu untuk menyetrika pakaian hingga pukul 16.30 WIB. Setelah semua pekerjaan selesai, ia pun kembali ke rumah kontrakannya.
Rutinitas itu dilakoninya selama enam tahun terakhir.
Dari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga itu, Wahyu setiap bulannya mendapatkan bayaran sebesar Rp1,3 juta.
Mengingat jumlahnya di bawah UMK, ia pun berusaha memanfaatkan uang segitu untuk mencukupi biaya kehidupan sehari mulai dari makan, uang saku sekolah anak bungsunya hingga biaya kontrakan dirasa sangat mepet.
“Ya, cukup enggak cukup dengan jumlah uang seperti itu. Kalau bersisa, ya, sekitar Rp100-200 ribu,” kata Wahyu, seraya menambahkan bahwa kadangkala ia pun terpaksa mengutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Adapula kisah Ida Fitriani yang bekerja sebagai pengemudi ojek online Solo.
Perempuan 54 tahun itu hampir selalu bekerja lebih dari delapan jam saban hari.
Dalam kondisi normal, Ida menyebutkan jumlah order pesanan yang masuk bisa sampai 15 kali.
Dengan pesanan sebanyak itu, ia mengaku dalam sehari bisa mendapatkan uang sebesar Rp 180 ribu.
“Kalau khusus hari Sabtu dan Minggu itu dapatnya Rp 200-220 ribu. Ya, dari jumlah itu, uang yang diterima bersih sekitar Rp 150 ribu,” kata Ida.
Menurut Ida, nominal uang itu hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat ini ia menjadi tulang punggung keluarga setelah sang suami jatuh sakit dan tidak bisa bekerja lagi.
“Untuk nabung, ya, jelas enggak bisa, mepet banget. Suami sakit dan masih ada tanggungan biaya satu anak,” katanya.
Dengan penghasilan yang tidak pasti sebagai pengemudi ojek online, Ida sempat berpikir untuk mencari pekerjaan lain, tapi kemudian teradang usia yang tak lagi muda.

Sumber gambar, ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
“Ya, [pengin] mencari, tapi susah. Dengan usia sudah tua, mungkin [digaji] Rp 50 ribu. Kalau dari ojol kan masih mending. Kalau kerja sama orang, mungkin lebih kecil lagi [penghasilannya],”ujar dia.
Sebagai pengemudi ojek online, Ida menyadari pekerjaannya sangat berisiko. Terlebih dirinya juga tidak memiliki jaminan sosial.
“Itu yang bikin sedih,” katanya.
Tak jauh berbeda pernyataan beberapa warga di Papua.
Provinsi tersebut memiliki tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan catatan BPS, mencapai 6,92%—di atas angka nasional.
Seorang pekerja kebersihan di lingkungan pemerintah daerah yang mengidentifikasi dirinya sebagai Hesti, bekerja tanpa jaminan sosial dan kontrak yang jelas.
Belum lagi perkara pembayaran gaji yang sering terlambat.
Ia mengaku sempat berupaya mencari pekerjaan lain dengan status yang lebih jelas dan kepastian pembayaran, tapi belum membuahkan hasil.
“Kadang khawatir juga karena saya kan masih kontrak. Jadi bisa saja diberhentikan tiba-tiba,” kata Hesti yang mendapat bayaran Rp 3 juta per bulan.
Ia pun berharap pemerintah dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan formal yang lebih bisa menjamin kehidupan dirinya dan ketiga anaknya.
“Saya ingin supaya ada lapangan kerja lebih banyak di Papua, gaji lebih layak, dan persyaratan kerja jangan terlalu menyulitkan. Karena di sini susah sekali cari kerja,” katanya.
Wartawan di Solo, Fajar Sodiq dan wartawan Muhammad Ikbal Asra di Jayapura berkontribusi dalam laporan ini.