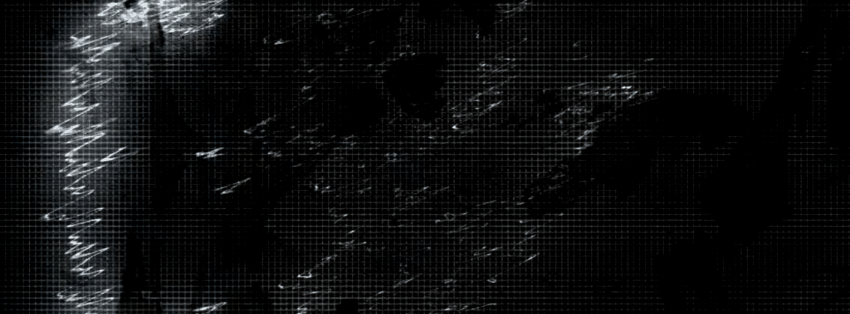Sumber gambar, Arie Firdaus
Pemerintah DKI Jakarta berencana melarang penggunaan ondel-ondel untuk mengamen di jalanan. Pelarangan dimaksudkan Gubernur Pramono Anung demi menjaga muruah salah satu kesenian Betawi tersebut. Namun, rencana ini menyelipkan masalah lain: menambah potensi pengangguran di Jakarta.
Pengamen ondel-ondel mengaku tak memiliki pekerjaan lain dan khawatir bakal kehilangan pendapatan jika pemerintah daerah betul-betul merealisasikan pelarangan itu.
“Kalau ondel-ondel dilarang, mau makan apaan? Ini doang [mengamen] pencarian saya,” kata salah seorang pengamen bernama Achmad Muchsin kepada wartawan Arie Firdaus yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Pemilik sanggar ondel-ondel meminta Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan alternatif seperti memfasilitasi lokasi pertunjukan jika akhirnya resmi melarang penggunaan ondel-ondel untuk mengamen.
Selama ini, ia mengaku terpaksa menyewakan ondel-ondel yang dimiliki untuk mengamen karena keterbatasan lokasi tampil.
Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menyatakan pelarangan dialamatkan kepada penggunaan “ondel-ondel untu mengamen, tapi tidak sesuai pakem”. Mereka pun menyatakan akan memberikan pembinaan dan memfasilitasi pegiat seni ondel-ondel untuk tampil di berbagai kegiatan.
Mengapa mengamen menggunakan ondel-ondel?
Ahmad Muchsin mengangkat leher kaos belelnya yang telah longgar, menunjukkan memar sekitar 4 sentimeter yang memanjang vertikal di bahu kiri.
“Biasanya, bisa [memar] lebih merah lagi,” kata pria 23 tahun itu.
Ia menunjukkan memar tersebut di sela-sela waktu istirahat setelah memikul ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen selama sekitar 30 menit di seputaran Senen, Jakarta Pusat.
“Berat itu! Ada [seberat] lima kilogram,” seorang perempuan yang ikut mengamen bersama Muchsin, ikut menimpali.
Hari itu, Kamis (28/8), Muchsin mengamen ondel-ondel bersama dua perempuan: Wati (28 tahun) dan Yuni (35 tahun).
Sepanjang perjalanan mengamen, mereka berbagi tugas. Muchsin memikul ondel-ondel, sementara kedua perempuan itu bertugas membawa ember kecil sebagai wadah menampung uang hasil mengamen.
Namun, Wati mengaku, ia sesekali juga mengambil peran Muchsin untuk memikul ondel-ondel.
“Gantian aja,” kata perempuan itu seraya terkekeh, “Kuat saya mah.”

Sumber gambar, BBC Indonesia
Wartawan Arie Firdaus menemui Muchsin Cs sekitar pukul 13.00 WIB. Matahari di atas ubun-ubun. Hawa panas dengan suhu 31 derajat celcius melingkupi kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Muchsin dan rombongannya beristirahat sejenak dengan mengambil tempat di bawah bayang-bayang sulur pohon. Mereka melepas penat sembari menunggu pengemudi bajaj langganan untuk pindah mengamen ke lokasi lain di Jakarta.
Siang itu, mereka berencana meneruskan mengamen di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, hingga sore. Selepas magrib, mereka berencana pindah ke area Mampang, Jakarta Selatan.
Rutinitas berkeliling itu dilakukan Muchsin hampir saban hari, mulai selepas zuhur hingga sekitar pukul 22.00 WIB.
Dengan jam kerja yang panjang —sembilan hingga sepuluh jam, berjalan beberapa puluh kilometer, dan harus memikul ondel-ondel seberat beberapa kilogram— Muchsin mengaku memar di pundak tak lagi menjadi perhatiannya.
Baginya, ada perkara yang lebih penting: mencari uang untuk makan.
“Enggak ada kepintaran [keahlian] lain. Daripada enggak ngapa-ngapain di rumah,” ujar pria lulusan SMP itu.
Muchsin bertubuh kurus dengan tinggi 160-an sentimeter. Saat ditemui, ia mengenakan kaus berwarna kuning yang telah pudar, celana panjang hitam, dan sendal karet abu-abu yang sedikit kebesaran untuk kakinya.
Ia mengatakan telah ikut mengamen ondel-ondel sejak masih remaja. Kala itu, ia ikut rombongan lain berkeliling.
Setelah beranjak dewasa, ia kemudian memutuskan mengamen sendiri dan mengajak beberapa rekan lain. Terkadang, rombongan berisi dua orang. Lain hari, gerombolannya beranggotakan tiga orang.
“Kadang-kadang juga berempat. Tapi, berempat susah nyari duitnya, [karena] [masing-masing] paling dapat Rp20 ribu,” kata Muchsin.
Muchsin menambahkan, ia memang harus berhitung soal pendapatan dari mengamen ondel-ondel. Pasalnya, semakin banyak orang ikut mengamen dalam kelompok, maka penghasilan setiap orang bakal kian mengecil.
Saat sedang mujur, Muchsin mengaku bisa mendapat uang total di atas Rp200.000. Namun, saat apes karena hujan, ia menyebut pendapatan dari mengamen ondel-ondel hanya berkisar Rp100.000.
Hanya saja, seluruh pendapatan dari mengamen itu tak sepenuhnya masuk ke kantong Muchsin.
Ia harus menyisihkan untuk beragam hal lain, mulai dari sewa bajaj atau angkutan kota yang digunakan membawa ondel-ondel ke suatu titik, biaya makan sepanjang perjalanan, hingga menyewa speaker kecil yang digunakan untuk memutar musik serta sebuah ondel-ondel.
Untuk menuju Kemanggisan di Jakarta Barat yang berjarak sekitar delapan kilometer dengan bajaj, misalnya, ia harus membayar Rp35.000.
Pengeluaran akan lebih besar jika ia dan rombongan mengamen ke daerah yang lebih jauh dan harus menggunakan angkot. Mereka harus merogoh kantong untuk membayar sewa setidaknya Rp50.000.
Belum lagi uang sewa untuk speaker kecil sebesar Rp10.000 dan sebuah ondel-ondel seharga Rp30.000 kepada pemilik sanggar.
Saat ditanya pendapatan yang akan dapat dibawa pulang per hari dari mengamen ondel-ondel, Muchsin menukas singkat, “Enggak menentu.”
“Paling [per orang] dapat Rp30.000-Rp40.000,” ujarnya.
Apakah mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya yang belum memiliki istri dan anak, Muchsin membalas, “Secukupnya aja.”
Muchsin mengaku sudah mendengar kabar Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang berencana melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen.
Lantas, apa rencananya jika pelarangan itu betul-betul diterapkan?

Sumber gambar, BBC Indonesia
Munchsin mengaku bingung, belum dapat membayangkan alternatif pekerjaan yang bakal dilakoninya.
Meski telah lama berinteraksi dan mengenal pemilik ondel-ondel, ia tidak diajak tatkala sanggar tampil di acara tertentu lantaran tidak bisa bermain musik tradisional atau kesenian Betawi lainnya.
Alhasil, terang Muchsin, “Kalau ondel-ondel dilarang, mau makan apaan? Ini doang [mengamen] pencarian saya…”
Muchsin menyewa ondel-ondel dari Mulyadi, pemilik sanggar Irama Betawi yang berlokasi di Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat.
Sanggar ini berdiri pada 2009 dan berfokus pada kesenian ondel-ondel.
Sebagai seniman Betawi, Mulyadi mengaku sejatinya mendapati pergolakan batin saat harus melepas ondel-ondel miliknya untuk mengamen.
Di satu sisi, ia ingin ondel-ondel tampil di tempat yang baik dan layak —bukan di jalanan. Namun, di sisi lain ia tak mau ondel-ondelnya rusak akibat tak dipakai mentas.
“Daripada saya punya barang [ondel-ondel] enggak dimanfaatin, lebih baik dimanfaatin [disewakan],” ujarnya.
“Kedua, ini juga sambil kita mengenalkan budaya Betawi ke masyarakat [lewat mengamen].”
Saat ini, Mulyadi memiliki tiga pasang ondel-ondel. Sepasang ondel-ondel dengan kondisi terbaik disimpannya jika sewaktu-waktu ada undangan mengisi acara.
Sementara dua pasang lain disewakan kepada para pengamen, salah satunya kepada Muchsin.
Kepada para penyewa, Mulyadi tak melepas sepasang ondel-ondel.
Sekelompok pengamen terkadang hanya mengarak satu ondel-ondel.
Pertimbangan lain adalah karena ia ingin membantu warga di sekitar kediamannya yang rata-rata tidak memiliki pekerjaan tetap.
Kawasan Pasar Gaplok, daerah kediaman Mulyadi, merupakan salah satu daerah padat penduduk di Jakarta Pusat.
“Daripada mereka melakukan hal-hal yang dilarang sama pemerintah, misalnya, mencuri atau hal-hal yang merugikan orang lain, mendingan dia ngamen,” kata Mulyadi.
“Orang, [kalau] masalah perut bisa ngebunuh orang.”

Sumber gambar, ANTARA FOTO
Berdiri sejak 2009, Irama Betawi sedari awal tak menyewakan ondel-ondel untuk mengamen.
Pada tahun-tahun awal berdiri, Mulyadi menyebut sanggarnya aktif berpartisipasi dalam sejumlah lomba yang digagas pemerintah daerah.
Dari rangkaian keikutsertaan itu, nama Irama Betawi kemudian membesar. Panggilan mentas pun berdatangan.
Sepanjang 16 tahun usia Irama Betawi, Mulyadi menyebut 2014 sebagai periode emas sanggarnya.
Kala itu, ia bisa tampil empat hingga lima kali dalam sebulan. Ia mengisahkan periode itu dengan senyum tipis tersungging di bibir.
Situasi berbalik pada awal 2020. Pandemi Covid-19 menghantam sanggarnya lebih keras.
Panggilan tampil di sebuah acara, “belum tentu sebulan sekali atau bahkan setahun sekali.”
Untuk menyambung hidup, Mulyadi kemudian membuka toko kelontong yang menjual mi instan dan rokok.
Beruntung, ia juga adalah seorang perajin ondel-ondel. Ia mendapat uang tambahan dari membuat ondel-ondel yang terkadang dipesan hotel, perusahaan, atau kantor pemerintahan.
Untuk ukuran 2,5 meter —ukuran normal—ia mematok harga Rp5 juta untuk sepasang ondel-ondel. Sepasang ondel-ondel berukuran lebih kecil yakni dua meter, ia menjualnya seharga Rp4 juta.
Ada pula beragam miniatur ondel-ondel yang dipatok dengan harga beragam, mulai dari Rp800.000 (ukuran 80 sentimeter), Rp250.000 (40 cm), dan Rp150.000 untuk sepasang ondel-ondel berukuran 20 sentimeter.

Sumber gambar, ANTARA FOTO
Di kediaman Mulyadi di Pasar Gaplok yang juga dikenal sebagai “Kampung Ondel-ondel” pada Kamis (28/8), sejumlah rangka miniatur tampak berjejer di pinggir jalan —tempat ia biasa merakitnya.
Lantas, apakah pendapatan dari menjual ondel-ondel itu cukup membuat dapurnya ngebul?
Ia hanya berkata singkat, “Insya Allah.”
Perihal rencana Pemerintah Daerah DKI Jakarta melarang penggunaan ondel-ondel untuk mengamen, Mulyadi mengaku sudah mengetahuinya.
Namun, ia berharap pemerintah dapat bersikap bijak dengan menyiapkan solusi seperti memperbanyak akses lokasi pertunjukan atau anggaran pembinaan bagi sanggar, terutama yang tidak terafiliasi komunitas seperti dirinya.
“Sebelum ditutup [dilarang], diarahkan dulu. Bakal ditempatkan di mana?” kata Mulyadi.
“[membuat] Sepasang ondel-ondel itu kan enggak murah. Biaya paling kecil Rp2 juta. Itu [uang] besar buat kami rakyat kecil.”
Mengapa mengamen menggunakan ondel-ondel akan dilarang?
Rencana larangan menggunakan ondel-ondel untuk mengamen disuarakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di sela-sela seremoni penandatangan kesepakatan bersama pelestarian budaya Betawi di Hotel Borobudur, Jakarta, pada 28 Mei 2025.
Lima hari berselang, dalam pidato di Sarasehan III Kaukus Muda Betawi di Ancol, Jakarta Utara, ia mengulang seruan serupa.
Pramono beralasan, rencana pelarangan itu didasarkan keinginannya menjaga muruah kesenian Betawi itu.
“Supaya budaya Betawi ini kita naikkan, kita buat menjadi sesuatu budaya yang sangat dihormati oleh siapa pun. Bukan kemudian budaya untuk ngamen,” ujar Pramono kala itu.

Sumber gambar, ANTARA FOTO
Dalam kesempatan itu, Pramono juga menyebut akan menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pelarangan tersebut. Aturan itu nantinya juga akan mencantumkan sanksi bagi mereka yang ngotot menggunakan ondel-ondel untuk mengamen.
Namun, Pramono kala itu tak memerinci sanksi yang disiapkan dengan alasan detail aturan masih dibahas pemerintah daerah bersama tokoh-tokoh Betawi.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pada 2 Juni juga sempat menargetkan bahwa peraturan daerah soal pelarangan itu sudah akan terbit pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta pada 22 Juni lalu, tapi sampai saat ini beleid yang dijanjikan belum juga rampung.
Sejumlah seniman dan tokoh Betawi diwawancarai terkait rencana pelarangan ondel-ondel untuk mengamen di ibu kota.
Mereka bersepakat, Pemerintah Daerah DKI Jakarta memang sudah sepatutnya mengatur perihal fenomena mengamen dengan ondel-ondel.

Sumber gambar, BBC Indonesia
Bachtiar, seorang seniman Betawi di Rawabelong, Jakarta Barat, mengatakan ia kerap mendapati pengamen ondel-ondel yang serampangan menggunakan simbol kesenian tersebut kala berkeliling.
Ia merujuk arakan ondel-ondel yang tidak sesuai pakem kesenian Betawi, seperti diarak tidak berpasangan atau diiringi musik seadanya.
Belum lagi para pengamen yang disebut Bactiar tidak menggunakan pakaian tradisional Betawi —bahkan kerap hanya mengenakan kaus lusuh saat berkeliling, atau tetap membunyikan musik saat azan berkumandang.
Jika dibiarkan berlarut, ia khawatir fenomena itu dapat menghadirkan imaji buruk soal ondel-ondel bagi masyarakat, terutama mereka yang baru pertama kali menyaksikannya.
“Ketika marak ondel-ondel yang tidak berdasarkan kepatutan, efeknya justru berdampak buruk bagi orang Betawi. Karena diwakili ondel-ondel yang tidak layak,” kata Bachtiar.
“Keresahan kami hari ini [adalah] hilangnya kebanggaan sebagai anak Betawi untuk melihat ondel-ondel yang layak, bagus, dan diiringi musik yang rapi.”
Bachtiar mendirikan sanggar Si Pitung pada 1995. Sanggar ini mengelola banyak cabang kesenian Betawi seperti ondel-ondel, pelatihan tari, lenong, dan palang pintu.
Pria 54 tahun itu mengaku beberapa kali juga pernah menegur pengamen ondel-ondel yang kebetulan lewat di seputaran kediamannya di Rawabelong.
Pemicunya beragam. Mulai dari pengamen ondel-ondel yang berkeliling dan tetap memutar musik saat azan atau membawa anak kecil saat mengamen Ada pula temuan pengamen ondel-ondel yang berbuat tidak senonoh saat beristirahat mengamen.
“Pengaturan ondel-ondel ngamen ini lumayan mendesak,” terangnya.
“Bagaimana budaya [Betawi], istilahnya, dicaplok dan digunakan untuk mengamen yang kemudian menimbulkan image yang buruk, bahkan bagi masyarakat Betawi sendiri.”
Budayawan Betawi, Yahya Andi Saputra, menilai fenomena pengamen yang tidak sesuai pakem telah mereduksi nilai-nilai ondel-ondel.
Yahya mencontohkan pengamen yang hanya mengarak satu ondel-ondel—tidak sepasang —yang dinilainya telah bertentangan dengan filosofi kesenian tersebut.
“Ondel-ondel yang dibuat sepasang itu simbolisasi keseimbangan,” kata Yahya.
Alhasil, ia pun mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang melarang penggunaan ondel-ondel secara sembarangan untuk mengamen, serta menyiapkan solusi komprehensif agar fenomena itu tak terulang di masa mendatang.
“Oknum [menggunakan ondel-ondel untuk mengamen] kan selalu berganti. Satu sadar, tapi ada generasi berikutnya.”

Sumber gambar, ANTARA FOTO
Tudingan merendahkan nilai ondel-ondel sempat dialami Muchsin saat mengamen.
Suatu sore, saat sedang berkeliling di daerah Kemanggisan, Jakarta Barat, seseorang tiba-tiba berteriak ke arahnya.
“Eh, budaya gue lu pakai ngamen! Bikin gue malu aja lu!” kata Muchsin, mengulang teguran tersebut.
Beruntung, tidak ada serangan fisik yang menimpanya. Namun, ia diminta segera meninggalkan lokasi tersebut.
“Cuma dimaki doang,” kata Muchsin, seraya menambahkan, “Saya jawab, ‘ya, bagaimana pak? Pekerjaan saya cuma main ondel-ondel’.”
Adapun Mulyadi, pemilik sanggar Irama Betawi yang menyewakan ondel-ondel kepada para pengamen, enggan berkomentar soal tudingan mereduksi nilai-nilai kesenian.
“Saya enggak bisa bicara [berkomentar]. Mereka [mengamen] untuk menghidupi anak dan istri,” ujar Mulyadi.
Sejak kapan ondel-ondel digunakan untuk mengamen?
Dikutip dari siniar Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, budayawan Yahya Andi Saputra mengatakan, catatan sejarah menunjukkan ondel-ondel untuk mengamen sudah ada sejak era kolonial, awal abad ke-20.
Bagaimana situasi mengamen kala itu?
Yahya mengatakan, pemerintah kolonial tergolong keras terhadap arak-arakan ondel-ondel, bahkan menerbitkan sejumlah aturan yang harus dipatuhi para pengeman.
Salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah kewajiban menggunakan sepasang ondel-ondel untuk mencari uang.
Selain itu, pemerintah kolonial juga mengatur soal hari dan titik-titik tertentu yang boleh digunakan untuk mengarak ondel-ondel.

Sumber gambar, BBC Indonesia
Pengaturan itu, terang Yahya, dilakukan pemerintah kolonial lantaran para pengamen juga dikenakan pajak.
“Pada awal abad ke-20 itu sudah diatur, yang mau mengamen silakan, tapi sesuai pakem,” kata Yahya.
Andaikata melanggar, sejumlah sanksi pun diberikan pemerintah kolonial. Salah satunya adalan penyitaan ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen.
Nantinya, para pengamen dapat menebus ondel-ondel tersebut setelah membayar denda dengan besaran tertentu.
Yahya menduga, ondel-ondel yang diarak beramai-ramai —entah untuk mendapatkan uang atau tidak— sejatinya sudah berlangsung jauh sebelum awal abad ke-20.
Ia berpijak pada nama terdahulu ondel-ondel yang disebut “barongan” atau “barungan”.
Istilah itu, terang Yahya, berasal dari bahasa Betawi klasik yang berarti serombongan. Hal ini merujuk pada ondel-ondel yang diarak segerombolan orang.
“Jadi, enggak ada kaitan dengan barong di Bali. Itu bahasa Betawi arkais,” kata Yahya.
Perubahan nama dari barongan menjadi ondel-ondel, lanjut Yahya, baru terjadi pada awal abad ke-20, tapi ia mengaku tak mengetahui penggagasnya.
Ia hanya mengatakan, “Ondel-ondel itu bahasa Betawi lama juga, artinya lincah dan fleksibel.”
Yasmine Zaki Shahab, antropolog Universitas Indonesia yang meneliti soal kebudayaan Betawi, menambahkan, ondel-ondel sendiri secara fisik turut berubah seiring waktu.
Pada masa lalu, ondel-ondel digambarkan berwajah seram dengan taring panjang. Penggambaran itu disebabkan ondel-ondel digunakan sebagai penolak bala oleh masyarakat.
Lantas, apakah perubahan itu bentuk lain mereduksi nilai ondel-ondel?
Yasmine berpendapat, perubahan sebuah kesenian seperti ondel-ondel adalah perihal normal mengingat kultur masyarakat Betawi juga berubah seiring waktu.
“Apalagi itu [simbol penolak bala] berhubungan dengan animisme. Sementara masyarakat Betawi seiring waktu lekat dengan nilai-nilai Islam,” pungkasnya.
Bagaimana komentar Pemda DKI Jakarta?
Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, mengatakan, larangan mengamen yang digagas Gubernur Pramono Anung sejatinya menyasar ondel-ondel yang tidak sesuai pakem.
Miftahulloh pun menyebut, ondel-ondel yang digunakan untuk mengamen, tapi tidak sesuai pakem bahkan “dapat dikategorikan sebagai mengemis.”
Sikap tegas pemerintah daerah itu, terang Miftahulloh, bertujuan agar ondel-ondel dimanfaatkan sesuai muruahnya, sebagai bagian kebudayaan Betawi.
Mengenai peraturan daerah yang sempat dijanjikan Wakil Gubernur Rano Karno terbit pada 22 Juni, Miftah mengatakan lembaganya sampai saat ini terus membahas detail aturannya bersama para pemangku kepentingan terkait.
“Untuk memastikan substansi aturan sesuai dengan tujuan pelestarian kebudayaan Betawi,” kata Miftahulloh.
Ia mafhum penertiban para pengamen ondel-ondel berpotensi membuat sejumlah orang kehilangan sumber pendapatan, mulai dari pemilik sanggar yang menyewakan ondel-ondel hingga mereka yang biasa mengamen di jalanan.
Miftahulloh belum memerinci kebijakan yang dilakukan.
Ia hanya mengatakan, “[Pemerintah] memberdayakan mereka dalam berbagai kesempatan misalnya HUT DKI, Karnaval Budaya, Lebaran Betawi, acara resmi lainnya.”