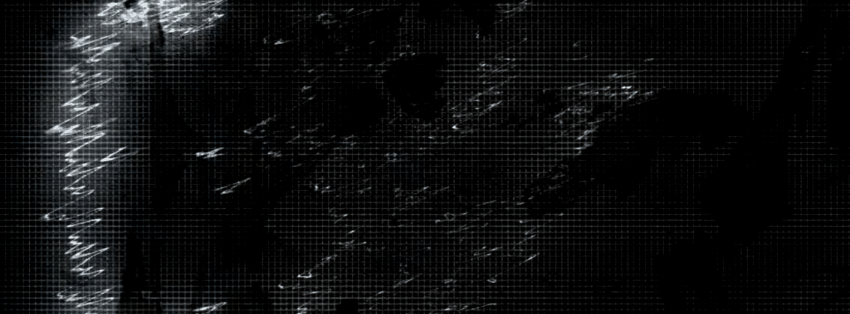Sumber gambar, DimaBerkut/Getty Images
-
- Penulis, Tri Wahyuni
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
Di balik julukan “destinasi wisata unggulan”, Bali menyimpan sisi kelam. Orang-orang Bali disebut “tertawan” pariwisata karena tidak ada sektor lain yang dinilai lebih menguntungkan. Kebanyakan warga Bali disebut takut bersuara karena sudah ‘dikondisikan’ untuk tidak memprotes perkembangan pariwisata. Mengapa dan sejak kapan ini bermula?
Gelombang demonstrasi yang memprotes kinerja anggota dewan dan tindakan represif polisi pada akhir Agustus lalu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Umumnya aksi protes ini dianggap mewakili amarah masyarakat secara keseluruhan.
Namun, di Bali, demo itu direspons berbeda.
“Warga Bali asli enggak suka demo,” komentar salah satu akun di unggahan video demo yang tersebar di media sosial TikTok.
“Jangan aneh-aneh di Bali. Bali tenang kerja saja,” kata yang lain berkomentar di media sosial Thread.
Demonstrasi, apalagi yang berakhir ricuh, dianggap mengganggu stabilitas yang bisa mengancam sumber pundi-pundi dari pariwisata.
I Wayan Suyadnya, dosen sosiologi di Universitas Brawijaya, menjelaskan sikap orang Bali yang tidak menyukai protes dan demo merupakan gambaran dari budaya koh omong atau malas berbicara.
Orang Bali menghindari keributan yang lebih besar. Mereka menghindari perdebatan panjang demi menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis.
Wayan menyebut “orang Bali sangat pandai menyimpan segala macam masalah”.
Dia menjelaskan, jika dirunut ke belakang sikap orang Bali yang malas bicara itu mulai tumbuh sejak 1965, setelah tragedi pembantaian massal.
Peristiwa itu jadi “hantaman yang luar biasa” bagi orang Bali.
Tragedi 1965 diperkirakan menewaskan 80.000–100.000 jiwa serta menyisakan trauma mendalam bagi para penyintas, keluarga korban, dan masyarakat luas.
“Orang Bali itu tertawan pariwisata. Sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan dirinya karena ada struktur sosial yang lebih kuat,” ujar Wayan.
Padahal sebelum tragedi berdarah itu, menurut Wayan, orang Bali adalah orang-orang yang kritis, dinamis, dan aktif dalam menyampaikan aspirasi.

Sumber gambar, LightRocket via Getty Images
I Ngurah Suryawan, putra Bali yang menjadi dosen antropologi di Universitas Papua, mengatakan “salah besar” kalau menganggap orang Bali tidak kritis.
Sebab, hingga era 1960-an pun orang Bali masih berani melawan.
Dalam buku Berebut Tanah: Pertarungan atas Ruang dan Tata Kelola (Wardana, 2024) dituliskan, pada era itu para petani melawan tuan tanah, memprotes aturan pertanahan yang tidak adil.
Perlawanan ini, pada masanya, dicap sebagai gerakan komunis. Hasilnya, mereka jadi sasaran “pembersihan”, bersama dengan aktivis buruh dan perempuan, juga para cendekiawan.
“Menurut saya, tradisi berpikir kritis orang Bali itu, ditumpas sampai ke akar-akarnya dan kemudian orang Bali diubah menjadi manusia ataupun subjek yang tunduk pada pariwisata,” ujar Ngurah.
‘Tertawan pariwisata’
Bukan tanpa alasan I Wayan Suyadnya menyebut orang Bali tertawan pariwisata.
Pada 2019 lalu, dia membuat penelitian tentang dampak perkembangan pariwisata di beberapa wilayah di Bali.
Dia memotret kondisi warga yang “terjepit” antara perkembangan pariwisata dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Salah satu wilayah yang diteliti adalah Canggu.
Waktu itu desa di Kecamatan Kuta Utara itu sedang tenar-tenarnya ketika Wayan datang.
Beberapa media asing merekomendasikan Canggu sebagai tempat yang harus dikunjungi di Bali. Sebab, Seminyak dan Kuta dinilai sudah terlalu ramai.
“The New Seminyak” dengan nuansa yang lebih muda dan kasual, menurut salah satu media.
Cocok bagi yang ingin melarikan diri dari keramaian perkotaan, menggantinya dengan suasana pedesaan yang masih tradisional, pantai asri, cuaca yang cerah, dan biaya hidup rendah.
Hasilnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Canggu pun terus meningkat, didominasi digital nomads—orang-orang yang memanfaatkan teknologi digital untuk bekerja dari mana saja, dengan durasi tinggal sampai berbulan-bulan.

Sumber gambar, Getty Images
Untuk menampung kedatangan turis, vila-vila baru dibangun di lahan kosong hingga persawahan.
Makin banyak pula kendaraan melintas di jalan-jalan yang tidak seberapa besar, menyebabkan kemacetan di beberapa titik.
Melihat perkembangan pariwisata yang begitu pesat hanya dalam beberapa tahun saja, Wayan menduga Canggu mengalami overturisme.
Sebagai orang yang mempelajari ilmu tentang masyarakat, dia ingin melihat seberapa jauh perkembangan pariwisata itu memengaruhi kehidupan warga lokal.
Overturisme terjadi ketika warga setempat merasa kehidupan sehari-hari mereka terganggu akibat kehadiran wisatawan.
Untuk membuktikan dugaan itu, Wayan mewawancarai para warga. Namun, penolakan demi penolakan dia alami, sampai dia sempat merasa putus asa.
Ternyata, bagi warga, kehadiran Wayan berpotensi “menjelek-jelekkan pariwisata”.
“Itu bagi saya–sebagai orang Bali–sesuatu hal yang sangat menyakitkan. Kenapa? Karena kita berupaya untuk mencari solusi terkait dengan masalah-masalah yang ada di situ.”
“Tapi mereka mengatakan siapapun yang merusak pariwisata dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang memang tidak pantas untuk diterima. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu,” kata Wayan.

Sumber gambar, BBC Indonesia
Setelah “dilempar” sana-sini, akhirnya dia bertemu beberapa orang yang mau diwawancarai. Pada tahap itu, ia menyadari satu hal, warga benar-benar menjaga perkataan mereka.
Dari situ Wayan menyimpulkan, warga sebenarnya juga merasakan dampak overturisme, tapi mereka menyembunyikan perasaan itu rapat-rapat.
Sebab, pariwisata Canggu sedang berada di “posisi puncak” dan mendatangkan “keberhasilan”.
“Dalam bayangan mereka, kalau mereka sampai menjelek-jelekkan pariwisata, mereka akan kembali lagi pada tahun 1980–1990, di mana Canggu itu adalah kawasan yang sangat sepi sekali dan tidak seperti sekarang dan yang sangat luar biasa ramainya,” ujar dosen yang mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Brawijaya itu.
“Tapi dalam hatinya, mereka sebenarnya protes.”
Fenomena itu tidak hanya terjadi di Canggu. Di wilayah lain, seperti Denpasar, Ubud, Blahbatuh, BBC News Indonesia juga mengalami kesulitan yang sama ketika menggarap liputan soal overturisme di Bali, yang memang sempat ramai dibahas 2024 lalu.
Tidak mudah menemukan orang Bali yang mau diwawancarai untuk membahas masalah-masalah yang membayangi perkembangan wisata di Pulau Dewata.
Beberapa orang yang ditemui secara langsung menolak pendapatnya dimuat dalam liputan.
Salah satu orang tidak mau berbicara apa pun. Padahal menurut dokumen hukum yang kami dapatkan, orang itu bisa diidentifikasikan sebagai korban pembangunan pariwisata.
Pencarian kami lanjutkan ke dunia maya. Kami mencoba menjangkau beberapa orang melalui pesan pribadi di Instagram dan TikTok.
Mereka mau menyampaikan keluhannya, tapi menolak ketika kami meminta untuk menjadi narasumber berita.
‘Kita harus terima’
Gede adalah orang Bali pertama yang mau menceritakan sisi kelam perkembangan pariwisata di Pulau Dewata.
Syaratnya, dia meminta namanya disamarkan dan identitas lainnya tidak disebutkan karena dia bekerja di sektor itu.
Di satu sisi, Gede merasakan keuntungan dari Bali yang semakin mendunia, dan kunjungan wisatawannya yang semakin banyak.
“Target kerja selalu terpenuhi”, katanya.
Tapi di sisi lain, dia merasa kehadiran para wisatawan juga memengaruhi kehidupannya.
Keresahan pertama bahkan sudah ia rasakan sejak lebih dari sepuluh tahun lalu, saat dia bekerja di industri kreatif.

Sumber gambar, Getty Images
Tiba-tiba saja pekerjaannya “digantikan” oleh wisatawan mancanegara. Padahal, menurut dia, level pekerjaannya itu tidak boleh diisi oleh orang asing.
Keresahan lainnya mulai dirasakan saat berencana membeli rumah sendiri tahun lalu
Gede bekerja di Denpasar. Tadinya, dia berharap punya rumah yang dekat dengan tempat kerjanya.
Tapi kenyataannya, harga rumah-rumah di Denpasar sudah tidak masuk akal buat dia, mencapai Rp1 miliar per 100 meter persegi.
Akhirnya Gede menurunkan standar rumah impiannya. Mencoba lebih realistis.
Dia melebarkan pencarian, ke lokasi-lokasi yang setidaknya bisa ditempuh dalam waktu 30 menit ke kantornya. Namun, hasilnya tetap nihil.
Meski gajinya sudah mencapai Rp17 juta per bulan, hampir enam kali lipat dari upah minimum regional (UMR) di Bali, Gede masih merasa tidak sanggup membeli maupun mencicil properti.
Harapan punya rumah di tanah kelahirannya sendiri kini sudah dia kubur dalam-dalam.
Gede bilang kesulitan yang sama sebenarnya juga dialami teman-teman seangkatannya, tetapi hanya dia yang keras menyuarakan keresahan.
“Saya sih sering menyinggung [masalah ini di tongkrongan], tapi teman saya, ‘ya sudah kalau kita enggak bisa [beli properti], ya enggak apa-apa’, kita harus terima tinggal sama orang tua,” kata Gede menceritakan respons teman-temannya.
Berawal dari perampasan tanah
Jika budaya koh omong sudah menyebar di masyarakat sejak 1965, itu artinya sudah 60 tahun orang Bali hidup dalam trauma kolektif, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.
Dalam kasus di Bali, dan di Indonesia secara umum, pembunuhan massal 1965 disebut sebagai sebagai peristiwa yang melapangkan jalan perampasan tanah warga.
Mengutip Wardana (2024), akibat perampasan tanah, kebijakan-kebijakan Orde Baru tentang pengembangan pariwisata massal di Bali diterapkan tanpa perlawanan yang berarti.
Tidak ada orang yang tampil ‘berbeda’ karena takut dicap ‘komunis’ atau ‘anti-pembangunan’. Jika ada yang ‘berbeda’, tidak hanya diri sendiri yang menerima ganjarannya, tetapi juga keluarga dan harta benda.
Seperti yang terjadi waktu pembangunan kawasan Nusa Dua di Bali Selatan antara 1970-an sampai 1980-an. Di buku yang sama disebutkan, para petani sempat dipaksa menjual tanah pertanian dengan harga lebih murah dari harga pasaran.

Sumber gambar, Getty Images
Merasa keberatan, para petani menolak. Perlawanan itu langsung disambut dengan ‘intimidasi’ oleh pejabat pemerintah.
Salah satu petani mengaku dua kali dipanggil ke kantor kecamatan. Pada masa Orde Baru, dipanggil oleh pegawai pemerintah cukup menakutkan.
Petani itu pasrah. Dia lantas melepaskan tanahnya seluas satu hektare.
Pengalaman itu, dan pengalaman-pengalaman lainnya, akhirnya membentuk masyarakat yang sangat takut jika tidak dianggap pro pembangunan.
Dampaknya, orang Bali menyetujui segala bentuk pembangunan, apalagi untuk kepentingan negara, kata I Wayan Suyadnya.
“Karena begitu mereka dianggap sebagai bagian dari komunis dan sebagainya, mereka enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Termasuk akhirnya mereka menelan saja masalah-masalah [yang mereka hadapi] itu, mereka berupaya untuk selesaikan sendiri,” ujarnya.
Membentuk manusia pariwisata
Setelah tanah-tanah berhasil direbut dan dikuasai, masyarakat menjadi lebih penurut, pembangunan pariwisata pun digenjot habis-habisan, kata Ngurah.
Pemerintah Orde Baru, yang dipimpin Presiden Soeharto, melanjutkan konsep pariwisata di era kolonial.
Pada 1900-an, pemerintah Belanda menggunakan pariwisata untuk membuat dunia lupa atas kekejaman yang sudah mereka lakukan dalam ‘menaklukan’ Bali.
Mereka memasarkan Bali sebagai tempat yang indah, eksotis, dan berbudaya. Ngurah menyebutnya, Bali menjelma “museum hidup”, yang harus dijaga keasliannya, agar bisa “dikonsumsi” untuk kepentingan pariwisata.
“Nah, itu yang dilanjutkan oleh rezim Orde Baru, yang melihat Bali itu harus tertib dan teratur, agar tampak baik, bagus, buat pariwisata,” ujarnya.
Buat mencapai tujuan itu, masyarakat diajak fokus membangun pariwisata, dibentuk sebagai masyarakat yang cinta damai dan rukun, dan kemudian lupa dengan kekejaman yang terjadi pada Tragedi 65.

Sumber gambar, Getty Images
Semua instrumen dikerahkan, mulai di lingkup terkecil seperti keluarga, hingga ke lingkup yang lebih luas, di ranah pendidikan.
Trauma Tragedi 65 membuat ‘penciptaan kondisi” dilakukan bahkan sejak dari rumah. Orang tua melarang anak-anaknya untuk bersikap kritis.
Ngurah menjelaskan, di tingkat desa ada sekaa truna truni, yaitu organisasi pemuda-pemudi yang berfungsi sebagai wadah sosial untuk mengembangkan kreativitas, melestarikan budaya, dan membantu kegiatan desa adat.
Institusi-institusi pendidikan pun, kata Ngurah, lebih fokus ke sektor pariwisata. Ketika anak-anak lulus dari bangku sekolah, mereka dipersiapkan untuk mengisi industri-industri pariwisata.
“Jadi sudah tercipta semacam kondisi untuk mengerahkan semua potensi yang ada di Bali itu untuk kepentingan pariwisata. Anak muda Bali tuh seolah tidak ada imajinasi lain selain berkecimpung dalam industri pariwisata,” kata dia.
‘Mantra’ pariwisata
Meski masyarakat mengalami trauma kolektif, bukan berarti tidak ada yang bersikap kritis sama sekali.
Dalam beberapa momen, orang Bali juga pernah memprotes pembangunan pariwisata, bahkan dalam skala besar.
Biasanya, ketika ada pelanggaran terhadap kesakralan atau kesucian, kata Wayan.
Sekitar tahun 1993-1994, warga menolak pembangunan kompleks resor mewah di dekat Pura Tanah Lot, Tabanan, karena dianggap mengotori kesucian pura.
Walaupun perlawanan warga tidak sanggup menggagalkan proyek itu, gerakan itu menghasilkan Bhisama—ketentuan keagamaan berdasarkan kitab-kitab Hindu—tentang kesucian pura yang mengatur radius kawasan suci berdasarkan klasifikasi hierarki pura.
Pada 2005, Bhisama ini dituangkan dalam tata hukum negara, yakni Perda Rancangan Tata Ruang Wilayah Bali nomor 3 tahun 2015.
Artinya, masyarakat sipil bisa menggunakan ketentuan itu untuk menolak proyek-proyek pembangunan yang dipandang membahayakan kebudayaan dan lingkungan Bali (Wardana, 2024).
Penolakan lainnya muncul setelah Reformasi. Salah satu yang terbesar adalah penolakan reklamasi di Teluk Benoa.
Selain berstatus kawasan konservasi, teluk juga diyakini sebagai kawasan suci.
Sampai saat ini, proyek reklamasi Teluk Benoa masih dinyatakan gagal. Namun, pemberian izin lokasi baru pada 2018 lalu diduga menjadi tanda proyek akan berlanjut.

Sumber gambar, Anadolu Agency/Getty Image
Di tahun selanjutnya, pariwisata Bali semakin maju. Kunjungan wisatawan pada 2019 mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Jumlah wisatawan asing tercatat lebih dari 16 juta dalam setahun, sementara wisatawan lokal ada di angka 10 juta pengunjung.
Namun pada 2020, bak petir di siang bolong, pandemi Covid-19 membuat pariwisata Bali kolaps. Itu menjadi salah satu momen paling suram buat para pelaku wisata.
Pada masa itu, banyak orang menyimpulkan, tanpa pariwisata, Pulau Dewata bukanlah apa-apa.
Beruntung, kondisi itu tidak bertahan lama.
Tahun berikutnya, Bali mulai bangkit lagi, seiring dengan pandemi yang mulai mereda. Turisme kembali melesat, bahkan sampai sekarang.
Tidak ada yang ingin kembali ke masa-masa kelam pandemi. Oleh sebab itu, orang Bali betul-betul menjaga stabilitas di tanahnya. Sebisa mungkin meminimalisasi gangguan yang ada.
Beberapa tahun belakangan, Bali disebut-sebut mengalami overturisme.
Kemacetan, sampah yang menumpuk, perilaku turis asing yang seenaknya, sampai pengrusakan alam demi pariwisata, semuanya mewarnai berita-berita di media sosial.
Namun kebanyakan warga, pelaku pariwisata, sampai pemerintah, kompak menyebut, tidak ada overturisme.
Justru pariwisata Bali harus dikembangkan ke wilayah lain karena Bali selatan, yang selama ini menjadi pusat turisme, sudah terlalu padat. Begitu mereka mendefinisikan overturisme.
Dalam penelitiannya, I Wayan Suyadnya menyimpulkan, pembangunan pariwisata telah menjadi “mantra ampuh” untuk membungkam mereka yang protes.
Masyarakat menyadari bahwa posisi sosial dan nilai tawar mereka lemah terhadap pembangunan pariwisata, menurut Wayan. Sekali lagi, mereka tertawan pariwisata.
Menolak lupa, melawan rapalan mantra
Mantra bisa terus bekerja, selama orang-orang percaya. Mantra bakal kehilangan dayanya, saat akal mulai bertanya.
Pada saat pemerintah sibuk membangun citra Bali sebagai surga pariwisata, membuat masyarakatnya sibuk “mengurus turis”, Agung Alit bergerak melawan arus.
Dia seorang pengusaha, sekaligus tokoh masyarakat. Keluarganya jadi korban kekejaman Tragedi 65. Ayahnya yang seorang guru dibunuh, dituding PKI.
Pada 2005 dia mendirikan Taman 65 sebagai ruang dialog. Delapan tahun kemudian, dia mendirikan Taman Baca Kesiman, untuk tempat membaca dan juga diskusi.
Bagi Agung Alit, membaca dan berdiskusi adalah cara untuk merawat ingatan dan mengembalikan pola pikir kritis khas orang Bali yang pernah ada, tapi lama tertutup trauma.

Sumber gambar, BBC News Indonesia
Dia menilai hilangnya sifat kritis ini membuat masyarakat Bali menjadi apolitis.
“Harapan kami, dengan mereka hadir di taman baca, mereka tambah lebih cerdas. Wawasan lebih terbuka lagi. Terutama untuk mengkritik ketidakadilan yang terjadi dengan hadirnya industri pariwisata Bali,” ujarnya.
Menurut dia, ini bukan lagi saatnya orang Bali menerima kebijakan-kebijakan pariwisata, yang sebenarnya tidak dirancang oleh orang Bali sendiri sebagai tuan rumah, tapi lebih banyak dirancang oleh pemerintah pusat dan dunia internasional.
Sayangnya, niat baik Alit untuk mengembalikan pola pikir kritis di masyarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Taman Baca Kesiman, yang awalnya didirikan buat orang-orang di Kampung Kesiman, nyatanya sampai sekarang belum berhasil membuat warga sekitar berdatangan.
Kebanyakan tamu berasal dari luar Kesiman, bahkan luar negeri.
Perjalanannya masih panjang. Oleh sebab itu, dia berharap banjar-banjar hingga kampus-kampus juga punya semangat yang sama.
Puluhan tahun menyimpan keresahan, kini Alit mulai melihat “sedikit” perubahan yang dibawa oleh generasi-generasi baru.
Mulai ada “suasana perlawanan”, dan itu “sinyal bagus”.
Salah satu yang disoroti Alit adalah waktu Gubernur Bali, I Wayan Koster melemparkan pernyataan kontroversial soal pengelolaan sampah pada awal Agustus lalu.
Waktu itu, pemerintah Bali akan menutup tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Suwung—salah satu TPA terbesar di Bali—karena mencemari lingkungan dan sudah dilarang oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Koster juga melarang warga membuang sampah apapun, terutama sampah organik, ke tempat pembuangan sementara maupun ke tempat pembuangan akhir.
“Ya (warga) olah sendiri (sampahnya). Selesaikan sendiri,” kata Koster dikutip dari detikBali.
Pernyataan itu memantik emosi warga.
“Saya lihat dari komen-komennya, orang-orang mulai bertanya. Jujur, saya senang sekali,” kata Alit.
“Semoga semakin bangkit,” ujarnya.
Anak muda jadi harapan
“Generasi sebelumnya itu enggak paham seberapa kacau kondisinya sekarang karena apatisme, karena berusaha menjadi sentris, berusaha tidak punya posisi sebagai orang Bali, kebiasaan enggak usah ikut politik-politik kayak begitu.”
“Jadi memang anak muda satu-satunya yang bisa mengubah Bali dari kondisi yang sekarang,” kata Cokorda Suryanata, pemuda 32 tahun asal Ubud.
Sebagai generasi milenial, Cokorda diwarisi trauma-trauma kekejaman tahun 60-an itu.
Orang tuanya selalu mengingatkan agar Cokorda tidak usah “ikut-ikut politik”, “jangan demo-demoan”, dan “jangan terlibat isu provokatif”.
Dia patuh. Sampai ketika dia merantau untuk kuliah di Bandung, Jawa Barat, dia mulai mempertanyakan semuanya.
“Itu mungkin sesuatu yang enggak bakal dirasa aneh, enggak kita rasakan ketika kita masih hidup di lingkungan itu. Dan dari saya sendiri memang butuh waktu untuk menghapuskan keyakinan itu,” ujarnya.

Sumber gambar, BBC News Indonesia
Sekarang, Cokorda sudah berhasil melupakan doktrin-doktrin itu dan mau terlibat membawa perubahan.
Bersama tiga temannya, dia membentuk sebuah koalisi yang mengajak masyarakat, khususnya anak muda, untuk bersuara dan mengkritik penguasa.
Dimulai dari isu yang paling dekat, dari kegemaran menggunakan transportasi umum, mereka mengkritik penghentian bus Trans Metro Dewata (TMD) pada awal 2025 lalu.
“Kami ingin memantik aksi, memantik pergerakan, menormalisasi kalau kritik itu bukan berarti benci. Kalau ada yang salah, bukan berarti kita harus diam. Kita bisa ngomong, kita berhak [bersuara],” ujar Cokorda.
Melalui koalisi ini, mereka ingin menyebarkan paham bahwa “kebijakan pemerintah bukan takdir yang tidak bisa diubah”. Juga, menghilangkan kesan bahwa “pejabat-pejabat tidak tersentuh” dan justru merekalah yang harus dicari ketika masalah terjadi di tengah masyarakat.
Cokorda dan teman-temannya ingin “membangunkan” anak-anak muda Bali lainnya, menyadarkan mereka bahwa dengan pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata, kondisi hidup mereka sekarang “tidak layak”.
“Kita berhak mendapatkan yang lebih baik.”

Sumber gambar, BBC News Indonesia
Karena mereka menargetkan anak-anak muda buat ikut bergabung bersama koalisinya, cara yang dipakai lebih kreatif dan inovatif, lewat tulisan dan gambar, yang dikumpulkan dalam bentuk zine.
Zine adalah media cetak alternatif yang diterbitkan dan diedarkan mandiri, biasanya dilakukan oleh perorangan atau kelompok kecil, bersifat nonkomersial dan nonprofit, jumlahnya pun sedikit.
Kumpulan aspirasi itu kemudian mereka sebarkan ke masyarakat, baik secara langsung, maupun lewat media sosial.
“Menurut saya, itu sebuah titik masuk yang bagus untuk memancing, memperkenalkan bahwa kita punya aspirasi, kita bisa menyuarakannya dengan banyak media, banyak cara. Enggak ada salah, enggak ada benar,” kata Sania Saraswati, salah satu inisiator Berhak Bergerak.
Setelah menuntut pemerintah mengoperasikan kembali bus TMD—dan pada April 2025 akhirnya bus itu beroperasi lagi—Koalisi Berhak Bergerak kembali mengajak warga untuk membuat zine lainnya.
Temanya soal menuntut hidup yang lebih layak di Ubud. Berbagai curahan amarah tentang sulitnya akses pejalan kaki, transportasi, hingga masifnya pembangunan pariwisata tertuang dalam gambar maupun tulisan.
Pelan-pelan, Koalisi Berhak Bergerak menggaet partisipan. Pengikut mereka di media sosial pun semakin bertambah.
Mereka berharap gerakan ini semakin meluas. Walaupun di sisi lain mereka juga paham sulit untuk menjaga api terus berkobar pada masing-masing orang, tapi mereka harus optimis.
“Itu satu-satunya cara untuk maju. Justru yang berkuasa tuh pengin kita pesimistis, mereka tuh pengin kita ngerasa enggak punya kekuatan. Saya enggak mau mengikuti mereka,” ujar Cokorda.
‘Bali yang lebih baik’
Seperti Agung Alit, melihat kondisi saat ini, I Ngurah Suryawan yakin kalau suatu hari nanti trauma kolektif itu bisa hilang, orang Bali tidak lagi hidup dalam bayang-bayang mantra pembangunan pariwisata.
Catatannya, harus mempelajari sejarah, tetap mempercayai nilai-nilai leluhur, dan dipadukan dengan pengetahuan modern.
“Saya sangat percaya dengan anak generasi muda Bali yang bisa berpikiran terbuka, hybrid, dan kemudian mengakses berbagai macam perubahan dan pelajaran dari berbagai macam tempat,” kata Ngurah.
“Namun, satu-satunya kekhawatiran saya sebenarnya adalah negara, kekuasaan,” dia menambahkan.
Kemampuan penguasa menghilangkan nilai-nilai dan sejarah demi kepentingan kapital dan kekuasaan, menurut dia, menjadi salah satu energi negatif yang bisa menjadi penghambat.
Tapi, semoga kekhawatiran itu tidak terbukti.
Sebab, sepengamatan Ngurah, sekarang orang Bali mulai berani mengritik pemerintah. Itu bisa dilihat ketika banjir besar menerjang Bali setalan pada pertengahan September ini.
Walaupun sebagian warga masih menganggap banjir sebagai musibah yang tidak bisa ditebak kapan datangnya, sebagian lagi mulai mengkritik kebijakan pemerintah sebagai salah satu penyebabnya.
“Mereka memandang ini bukan hanya musibah alam, tapi juga kelalaian pemerintah, kesalahan kebijakan, dan kapasitas pemerintah menangani masalah ini,” kata Ngurah.
Kapan “Bali yang lebih baik”, seperti harapan Berhak Bergerak dan warga lainnya, akan terwujud?
Wartawan di Bali, Christine Novita Nababan, berpartisipasi dalam liputan ini. Produksi video oleh Ivan Batara dan Andra Anhar.