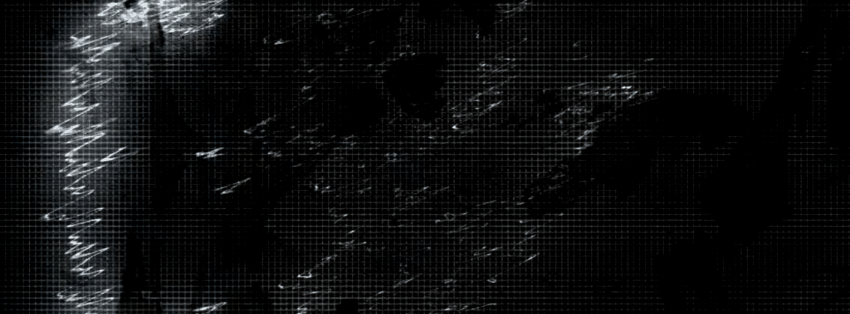-
- Penulis, Faisal Irfani
- Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia
-
Tragedi 1965 di Padang Halaban, Sumatra Utara, menjadi bukti bagaimana negara melalui militer menggunakan propaganda “kejahatan komunis” untuk menangkap dan membunuh warga yang dicurigai sebagai “orang-orang Kiri” tanpa proses hukum, serta merampas lahan pertanian yang sebelumnya digarap oleh masyarakat.
Poniyem tidak sabar menanti kelahiran anak ketiganya yang, menurut perhitungan, akan jatuh pada Oktober 1965. Dia bersama suami, Sabarudin, sangat antusias sebab ini kali pertama mereka akan punya anak laki-laki.
Dua kelahiran terdahulu memberikan mereka keturunan perempuan. Pasangan itu berharap kehadiran seorang putra bakal makin melengkapi keluarga kecil mereka.
Petaka 1965 membuyarkan angan sekaligus rencana Poniyem ke titik yang tidak pernah dia bayangkan.
Jelang malam pada 30 September 1965, tak lama setelah kembali dari ladang, Poniyem mendapat kabar Sabarudin telah ditangkap oleh militer.
“Suamiku itu tidak ikut [kegiatan politik] apa-apa,” jawabnya ketika saya bertanya apakah Sabarudin tergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) atau organisasi massa lain yang terafiliasi dengan partai itu.
“Dia itu kerja di pemerintahan desa. Petugas keamanan. Kalau sekarang [namanya] Satpol [Satuan Polisi] PP [Pamong Praja].”
Tanpa pikir panjang, Poniyem segera mencari keberadaan Sabarudin. Dia mendatangi rumah pejabat desa tempatnya tinggal dan menanyakan posisi suaminya.
Info yang beredar, Sabarudin dibawa ke Rantau Prapat, ibu kota Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, yang berjarak sekitar 50 kilometer dari rumahnya di Marbau.
Keesokan harinya, Poniyem melangkahkan kaki ke Rantau Prapat, menuju kantor koramil—komando rayon militer, satuan teritorial yang berada di tingkat kecamatan.
Di sana, Poniyem bertemu Sabarudin.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Ada sedikit kelegaan di benak Poniyem melihat sang suami dalam keadaan hidup. Namun, Poniyem tak mampu menutupi kekecewaan lantaran Sabarudin ditahan tanpa alasan yang jelas.
“Kalau salah, ditahan tidak apa-apa, tapi jangan pernah dipukul [suami saya],” Poniyem menceritakan ulang kalimat yang dia lontarkan kepada tentara waktu itu.
Saban hari, Poniyem menjenguk Sabarudin, membawakan bekal makanan kesukaannya dengan maksud supaya suaminya tetap waras. Hari ketujuh, ketika tiba di kantor koramil, dia tidak menemukan suaminya.
Tentara yang berjaga memberitahu Poniyem bahwa Sabarudin dipindahkan ke kantor korem—komando resor militer, satuan teritorial di atas koramil.
Sesampainya di kantor korem, Poniyem, yang diselimuti kepanikan, seketika mencecar para tentara dengan pertanyaan mengenai keberadaan suaminya. Tentara menjawab tidak tahu.
Di situlah Poniyem mulai menyadari suaminya “dihilangkan”—dan dibunuh.
“Kamu bunuh suami saya!” Poniyem mengulang kembali yang diucapkan ke tentara kepada saya.
“Kalau tidak dibunuh, suami saya pasti ada!” dia menambahkan dengan nada bergetar.
Poniyem terus berupaya mencari Sabarudin. Dia gigih bertanya ke banyak orang dan mendatangi berbagai kantor pemerintah. Tapi, usahanya sia-sia karena tidak ada satu pun yang tahu keberadaan suaminya.
Jalan yang dilalui Poniyem usai suaminya dihilangkan secara paksa penuh kerikil tajam yang menyakitkan.
Di tengah kalut, Poniyem mesti berjibaku dengan kondisi yang tidak kalah krusial: melahirkan anak ketiganya. Kehilangan Sabarudin membuat Poniyem harus melewati babak penting dalam hidup seorang diri.
Setiap malam, dia selalu teringat Sabarudin, juga rencana-rencana kecil yang sempat mereka bikin kala menikah pada 1958. Hatinya seperti tertusuk bilah belati saat bayangan Sabarudin terbesit di pikirannya.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Duka Poniyem semakin dalam ketika harus menghadapi kenyataan untuk menjelaskan kepada anak-anaknya mengenai hilangnya sang ayah.
“Saya bilang [ke anak-anak] kalau bapak sudah tidak ada. Sudah meninggal,” ujarnya.
Satu hal terus mengganjal tatkala Poniyem berujar soal kematian Sabarudin.
“Kalau meninggal, ada kuburannya. Kami, saya dan anak-anak, juga bisa menjenguk makamnya,” Poniyem berkata.
“Sementara ini tidak ada. Sedihnya luar biasa di situ.”
Cerita Poniyem tidak sebatas kehilangan sosok pasangan hidup, ayah dari ketiga anaknya. Peristiwa 1965 pun bermakna petaka yang lain.
1965 di Padang Halaban: Aksi kekerasan, kerja paksa, dan tentara yang menyisir dalam gelap
Usia Kartini masih 10 tahun saat dia—beserta murid-murid SD yang lain—diminta menghentikan kegiatan belajar, sekitar awal Oktober 1965.
Tidak jauh dari sekolahnya, ada lapangan berukuran cukup luas yang biasanya dipakai untuk bermain sepakbola. Anak-anak di satu sekolah itu lalu diarahkan menuju ke sana.
Di lapangan, Kartini sudah melihat personel organisasi masyarakat (ormas) lokal dan aparat militer berdiri dengan membawa senjata, di samping satu mobil bak terbuka.
Di mobil tersebut, Kartini melihat sosok laki-laki berusia 40-an tahun yang dia kenal sebagai Margolang. Dia tetangga Kartini.
Kartini, mulanya, bingung dan bertanya-tanya mengapa Margolang ditempatkan di atas mobil dengan bak terbuka yang dikelilingi para tentara.
Rasa penasaran langsung berubah kengerian selepas Kartini menyaksikan kedua tangan Margolang diikat ke mobil.
“Pertama, tangan kanan dan kirinya diikat ke mobil, lalu mobilnya menarik tubuh Margolang yang ada di tanah,” kenang Kartini saat kami berjumpa di satu siang yang cukup terik di Padang Halaban, Sumatra Utara, awal Agustus lalu.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
“Mobil lalu berhenti. Dari tangan, giliran kedua kakinya diikat. Mobil lalu jalan lagi dengan Margolang diseret di belakangnya.”
Kartini hanya bisa menahan takut, begitu pula seisi lapangan yang terdiam menonton pertunjukkan teror itu.
Pelaku penyiksaan baru menghentikan aksinya usai memandang Margolang sudah sempoyongan berhadapan dengan kekerasan.
Margolang kemudian diangkat dan dinaikkan kembali ke mobil yang menyeretnya. Di sini, menurut ingatan Kartini, Margolang muntah darah.
Di antara itu, Kartini mendengar suara keras yang muncul dari sebuah toa.
“Bapak Margolang ini antek-antek PKI!”
“Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ikuti jejak Bapak Margolang. Bapak Margolang ini antek PKI!”
Kartini tidak paham apa itu PKI, dan mengapa orang yang dianggap bagian dari PKI diperlakukan selayaknya penjahat. Yang Kartini tahu, kekerasan demi kekerasan lahir mengiringi masa kecilnya pada 1965.
“Pernah suatu waktu saya sedang berangkat sekolah. Di perjalanan ke sekolah, saya melihat orang dipukulin. Saya tanya ke bapak, ‘Itu kenapa dipukulin?’ Bapak tidak menjawab,” ujar Kartini.
Slamet, 71 tahun, juga mengalami kebengisan Tragedi 1965, dan membenarkan cerita Kartini ihwal “pementasan teror” yang menimpa Margolang.
“Nah, itu memang semua anak sekolah, semua orang yang kerja, disuruh nonton di situ [di lapangan] ketika Margolang ditarik mobil, diseret, diputar-putar,” Slamet menjelaskan.
“Memang [dia] tidak mati. Tapi, dedel duel—hancur badannya.”
Kengerian Peristiwa 1965 tak berhenti di situ. Slamet mengisahkan keluarganya menjadi korban langsung dari operasi yang digencarkan tentara.
Empat orang tentara, menurut pengakuan Slamet, mendatangi pamannya di kantor perkebunan tempat dia bekerja.
Slamet yang kala itu berusia 13 tahun, memperoleh kabar pamannya, Rasuan, diciduk dengan kedua tangan diikat tali. Pamannya lalu dibawa ke satu rumah yang dijaga oleh tentara.
Suatu saat Slamet mendapat kesempatan berjumpa dengan sang paman. Dia tak menyangka pertemuan itu bakal menjadi yang terakhir kalinya.
“Saya tengok ke sana, [paman] masih ada. Sore [saat] mengantar nasi, sudah tidak ada. Rupanya uwak—paman—sudah dibawa ke satu daerah. Dimatikanlah [dibunuh] di sana,” tutur Slamet kepada saya.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Tentara menangkap paman Slamet karena tergabung dengan Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) yang terafiliasi PKI.
Pamannya bukan satu-satunya keluarga Slamet yang menjadi anggota Sarbupri. Ayah dan ibu Slamet turut berpartisipasi di organisasi massa tersebut.
Orang tua Slamet bisa dibilang “beruntung” karena tidak ditahan militer. Sayang, status mereka sebagai anggota Sarbupri sudah cukup untuk dicap “terhubung dengan PKI.”
Konsekuensi yang paling jelas dari stempel itu ialah Slamet tidak mampu melanjutkan pendidikan.
Surat keterangan bahwa keluarga Slamet ada kaitan dengan gerakan komunis membuyarkan asanya meraih masa depan yang lebih baik.
“Saya dapat surat dari Medan waktu sekolah, SMP. Setelah dapat surat itu, saya disuruh pulang,” ucap Slamet.
Usai Peristiwa 1965, keluarga Slamet hidup dengan penuh keterbatasan. Untuk makan sehari-hari, Slamet dan keluarganya terpaksa melahap sajian seadanya. Tidak ada nasi, sayur mayur yang lezat, atau buah-buahan.
“Kami hanya makan ubi. Kalau tidak dapat ubi, makan tanaman hijau-hijau yang ada di tanah. Sedapatnya,” kenang Slamet.
“Soal makan memang morat-marit.”
Label “Kiri” menjadi penyebab utama penderitaan yang dialami oleh keluarga Slamet.
Orang tuanya tidak dapat mencari pekerjaan secara layak—ujung-ujungnya hanya buruh serabutan—lantaran khawatir dan takut turut kena dampak dari pemerintah.
“Selama kami hidup, sebelumnya, baru itu kami merasa sangat sengsara,” tegasnya.
Pembersihan terhadap PKI dan semua yang terkoneksi dengannya adalah agenda yang ditempuh rezim militer Orde Baru pasca-1965. Upaya ini dilangsungkan secara sistematis melalui rantai komando yang diturunkan dari pusat ke daerah-daerah.
Implementasi pembersihan komunis, di lain sisi, membuka jalan bagi ormas untuk terlibat. Militer menggandeng ormas-ormas di level lokal, dan ini dijumpai di Sumatra, Jawa, sampai Bali.
Militer, dalam perkembangannya, memasang kategorisasi untuk menyisir dan melenyapkan PKI hingga akar-akarnya. Orde Baru membagi mereka yang berhubungan dengan PKI ke tiga kategori.
Kategori pertama, Golongan A, ialah mereka yang dinilai berpartisipasi langsung dalam usaha pembunuhan perwira TNI AD dan kudeta pemerintahan Sukarno. Ketika berhasil ditangkap aparat, mereka akan diadili di pengadilan.

Sumber gambar, Bettmann Archive/Getty Images
Kelompok kedua, Golongan B, merupakan daftar berisikan orang-orang yang dianggap secara tidak langsung menyokong kudeta.
Peran mereka, militer mengklaim, berupa pemberian dukungan terhadap rencana kudeta—melalui pengerahan massa, misalnya. Hukuman bagi mereka yakni pemenjaraan.
Mereka dapat dibebaskan selama bersedia meninggalkan ideologi komunis dan kembali memeluk nilai-nilai Pancasila.
Sedangkan kategori terakhir, Golongan C, terdiri dari orang-orang yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak terhadap percobaan kudeta 1965. Biasanya, mereka hanya ditangkap untuk diinterogasi sebelum nantinya dibebaskan.
Pembingkaian atas PKI sebagai “dalang” di balik Peristiwa 1965 mewakili bagaimana pendekatan taktik yang diambil militer benar-benar direalisasikan demi satu tujuan: menyingkirkan komunisme.
Dua buku, Pretext for Mass Murder (John Rossa, 2006) & The Army and Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (Jess Melvin, 2018), nyatanya—melalui analisis serta bukti yang saling melengkapi—justru menunjukkan TNI AD sudah sejak jauh-jauh hari mempersiapkan langkah menggoyang kekuasaan Sukarno.

Sumber gambar, Carol Goldstein/Keystone/Getty Images
Akan tetapi, bagi banyak pihak, angka yang dilaporkan Orde Baru itu dinilai tak cocok merepresentasikan fakta di lapangan. Amnesty International, ambil contoh, menyebut jumlah mereka yang dipenjara sebab dituduh bagian dari komunis bisa mencapai lebih dari 100.000 orang.
Dari ketiga golongan yang ditetapkan Orde Baru, mengutip penelitian dosen hukum tata negara dan HAM di UGM, Herlambang Perdana Wiratraman, klasifikasi Golongan C berdampak hebat kepada “orang-orang kecil” di pedesaan hanya karena mereka beririsan dengan Sarbupri atau Barisan Tani Indonesia (BTI).
Dalam keyakinan militer, petani—atau orang ‘biasa’—yang bersinggungan dengan BTI sudah pasti memegang paham komunisme, dan oleh sebabnya wajib dihancurkan.
Akhir cerita dari mereka yang masuk dalam Golongan C tidak sekadar diperiksa dan dilepas setelahnya. Tidak sedikit yang ditahan, disiksa, dibunuh, hingga diminta kerja paksa.
Nyoto termasuk orang yang harus memikul beban kerja paksa tersebut.
Lahir di Kediri, Jawa Timur, Nyoto pertama kali tiba di Sumatra pada 1950 dengan tujuan untuk memperbaiki hidup. Di Jawa, waktu itu, “banyak masyarakat terlantar,” Nyoto menjelaskan.
Dari Kediri, Nyoto awalnya singgah di Padang, Sumatra Barat, sebelum akhirnya menetap di Padang Halaban, Sumatra Utara, dengan bekerja sebagai buruh perkebunan.
Garis takdir tidak ada yang pernah tahu, dan Nyoto bukan pengecualian. Peristiwa 1965, nyatanya, menjauhkan Nyoto dari usaha mengubah nasib.
Nyoto ditahan tentara dan disertakan ke dalam kerja paksa pada 1965.
“Karena saya [anggota] BTI [Barisan Tani Indonesia]. Bapak saya sendiri juga [anggota] Sarbupri [Sarekat Buruh Perkebunan Indonesia],” ujarnya kepada saya, mengungkapkan latar belakang mengapa dia masuk daftar pemerintah.
Nyoto hanya bisa menerima realita tersebut lantaran mengerti betul apabila melawan pemerintah imbasnya akan jauh lebih buruk lagi.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Kerja paksa yang dijalani Nyoto berlangsung kurang lebih selama satu tahun. Militer membagi pekerja ke dalam kelompok yang masing-masing berisikan sekitar 50 orang.
Semuanya adalah mereka yang dituduh mendukung PKI karena bergabung menjadi anggota BTI, Pemuda Rakyat, atau Sarbupri.
Jam kerja paksa dimulai pukul tujuh pagi, Nyoto berkisah, dan berakhir sebelum matahari tenggelam. Rombongan kerja paksa hanya memperoleh jatah makan di siang hari. Mereka tidak diberi upah sama sekali.
Nyoto masih mengingat dengan tajam lokasi dia kerja paksa: Tanjung Harapan, Rantau Prapat, Sumatra Utara. Di sana, Nyoto dan warga lainnya disuruh membabat hutan.
Setelah ditebangi, bekas area hutan itu akan dimanfaatkan menjadi sawah atau perkebunan sawit, Nyoto menerangkan. Keadaan di lokasi kerja paksa begitu tragis.
“Banyak [yang meninggal] karena kelaparan,” ucap Nyoto tanpa menyebut berapa jumlahnya.
“Kekerasan juga ada, oleh militer.”
Penerapan kerja paksa, berdasarkan penuturan Nyoto, berpindah-pindah tempat. Satu bulan selesai di Tanjung Harapan, misalnya, Nyoto lalu digeser ke daerah lainnya.
Pekerjaannya masih sama: membuka lahan yang awalnya hutan dengan pohon-pohon besar nan tinggi.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Warga yang diikutkan dalam kerja paksa berada di bawah tekanan sekaligus ketakutan. Para tentara, yang menenteng senjata laras panjang, mengawal mereka dari keberangkatan, di lokasi, hingga kepulangan.
“Kami tidak berani melawan, apalagi membangkang. Mereka [tentara] ada di mana-mana,” imbuh Nyoto.
“Namanya kami ini rakyat jelata. Mau bilang begini, salah. Begitu, juga salah.”
Selepas kerja paksa, pada 1966, Nyoto balik ke rumahnya di Desa Aek Korsik, Labuhanbatu, Sumatra Utara.
Pada fase ini, Nyoto membawa pulang kartu yang menyatakan dia punya hubungan dengan PKI. Nyoto menyebutnya “kartu hitam.”
Nyoto mengungkapkan “kartu hitam” itu melekat kepada dokumen kependudukan. Modelnya berbeda dengan kartu penduduk sebagaimana umumnya. Kepunyaan Nyoto terdapat cap, stempel, serta lipatan yang menandakan bahwa dia memiliki irisan ke PKI.
“Karena kami sudah dikira PKI. Kami bukan [anggota] PKI,” bantah Nyoto.
Efek dari “kartu hitam” ini tidak main-main. Nyoto mengaku kesulitan mencari pekerjaan dengan status “terhubung ke PKI” yang menempel ke dirinya.
Ketika mengurus keperluan administratif ke pemerintah pun Nyoto terombang-ambing—seolah tidak ada yang bersedia mengurusnya.
Alhasil, untuk bertahan hidup, Nyoto bekerja serabutan, mengikuti satu tuan tanah ke tuan tanah lainnya. Asalkan Nyoto mampu membungkus beras, pekerjaan apa saja dia bakal lakoni.
Dampak negatif turut mengintai keturunan Nyoto. Stempel PKI dari negara membikin anak-anak Nyoto diasingkan dari pergaulan. Baik guru maupun orang tua murid di sekolah tempat anak Nyoto menimba ilmu meminta untuk menjauhi mereka.
“‘Itu anak PKI. Jangan bermain sama mereka’,” Nyoto menceritakan ulang.
“Saya merasa sangat sakit hati.”
Waktu bergulir dan Nyoto berupaya bangkit dari masa lalu kelam tatkala 1965 menghapus banyak hal di hidupnya.
Lengsernya Soeharto pada 1998 turut membuka pintu penghidupan layak untuk korban genosida politik 1965. Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, menggaungkan rekonsiliasi kepada mereka yang terdampak saat menjadi presiden—terpilih lewat Pemilu 1999.
Menurut Nyoto, keputusan rekonsiliasi dari rezim Gus Dur ibarat “membebaskan para korban dari cengkeraman.” Pasalnya, cap PKI tidak lagi dia pikul.
Meski begitu, luka yang merobek batin Nyoto akibat kekerasan 1965 tidak sepenuhnya lenyap. Nyoto senantiasa dihantui mimpi buruk kerja paksa, sementara pada waktu bersamaan keadilan yang dia nanti tidak kunjung tiba.
Keadilan yang dia bayangkan berupa pengusutan kepada mereka yang sudah menghukumnya kerja paksa—dan memberinya cap PKI.
“Dari dulu sampai sekarang, begini saja. Enggak ada keadilan. Rasanya tertekan batin terus,” ungkap pria kelahiran 1934 ini.
Pola perampasan tanah: Memanfaatkan sentimen PKI
Konsekuensi dari Peristiwa 1965 tidak seketika berhenti pada penghilangan paksa suami Poniyem. Setelah suaminya, Sabarudin, dihilangkan, negara merampas tanah miliknya.
Perampasan sekaligus pengusiran yang menimpa Poniyem datang tanpa mengetuk pintu kesiapannya. Satu surat, berisikan permintaan untuk mengosongkan rumahnya, dia dapatkan di tengah situasi diri yang berkecamuk.
“Setelah 30 September [1965] itu, rumahku digusur [oleh tentara],” Poniyem bercerita kepada saya.
Poniyem sempat melontarkan pertanyaan mengapa dia digusur. Pemerintah desa, bersama militer, tidak banyak menjawab selain: ini perintah dari negara. Mereka menambahkan bahwa Poniyem tidak memegang dokumen resmi kepemilikan tanah.
Pencarian dokumen yang diminta aparat bukannya tidak Poniyem lakukan. Hasilnya nihil. Besar kemungkinan, Poniyem menduga, dokumen itu lenyap bersama suaminya.
“Saya bilang ke Pak Camat waktu itu, kalau diusir kami mau ke mana? Anak saya masih kecil, [dan kami] enggak punya tanah. Saya juga bilang kalau tanah ini, dulu, saya beli,” Poniyem mengenang kejadian tersebut.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Aparat yang berdiri di depan Poniyem tidak memberikan respons lebih lanjut. Mereka tetap meminta Poniyem angkat kaki. Poniyem menyadari dirinya, ketika perintah itu turun serta menyeret namanya, tidak mampu berbuat apa-apa.
Terlebih, Poniyem mendengar perkataan apabila tidak mengikuti perintah aparat maka bakal dicap PKI.
Poniyem kalut. Dia tak lagi menentang. Rumahnya—juga tanah—tidak dapat diselamatkan.
Pengalaman yang sama dihadapi Kartini dan keluarganya. Empat tahun selepas tragedi 1965, tentara mendatangi rumahnya dan meminta dokumen tanah serta kependudukan. Dalih aparat ialah “untuk diperbaharui,” terang Kartini.
Tidak lama setelahnya, aparat kembali datang ke rumah Kartini. Bukan untuk mengembalikan dokumen yang dulu diambil, melainkan melakukan penggusuran.
“‘Kok malah diusir kami dari sini?'” Kartini menirukan kalimat yang disampaikan ayahnya kepada aparat.
Ketidaksetujuan ayah Kartini tidak menghentikan usaha aparat untuk mengambil lahan keluarganya. Rumah keluarga Kartini lantas diratakan hingga habis; menyisakan kepedihan yang teramat.
Pengusiran dan perampasan lahan di Padang Halaban, dalam kaitannya dengan 1965, berlangsung secara sistematis.
Padang Halaban merupakan kawasan perkebunan sawit yang punya riwayat sejarah cukup panjang serta kompleks, mengutip makalah yang dirancang antropolog dan peneliti senior Agraria Resource Center (ARC), Dianto Bachriadi.
Pada 1942, bertepatan dengan kedatangan Jepang, warga setempat mulai mengambil alih dan mengolah kembali lahan-lahan perkebunan yang sebelumnya dikuasai oleh pengusaha Eropa.
Dalam kurun waktu tiga tahun, dari 1942 sampai 1945, masyarakat melakukan penguasaan lahan secara bertahap dan berpuncak setelah Indonesia merdeka.
Total lahan yang berhasil direbut seluas 3.000 hektare. Lanskap yang awalnya berbentuk kebun sawit, riset Dianto menjelaskan, berubah menjadi permukiman penduduk.
Di atas tanah 3.000 hektare itu lalu berdiri enam desa yang pembagiannya mengikuti blok-blok kebun sawit. Keenam desa yang dimaksud adalah Desa Sidomulyo, Desa Sidodadi (atau Aek Korsik), Desa Purworejo, Desa Kartosentono (Brusel), Desa Sukadame (Panigoran), serta Desa Karang Anyar.
Kehidupan masyarakat di enam desa ini, seiring berjalannya waktu, terbentuk. Denyut perekonomian berdetak dengan berfungsinya jalur kereta api. Desa-desa tersebut kemudian berperan penting dalam rantai distribusi bahan pangan di Sumatra Utara.
Momentum penting diraih masyarakat di Padang Halaban pada 1954 saat pemerintah lokal—dulu bernama Sumatra Timur—mengeluarkan Kartu Tanda Pendudukan Pendaftaran Tanah (KTPPT).
Dokumen legal ini ditujukan kepada warga sebagai alas bukti penguasaan tanah di Padang Halaban.
Penerbitan surat ini, merujuk penelitian Dianto, merupakan turunan dari diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Penyelesaian Pemakaian Tanah Perkebunan untuk Rakyat.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Garis besarnya, pemerintah diminta menuntaskan masalah penggunaan lahan dengan pemilik perkebunan. Karena pemilik perkebunan—yang berstatus warga negara asing—di Padang Halaban tidak segera mengurus lagi asetnya, maka pemerintah berwenang merilis KTPPT serta menyerahkannya kepada masyarakat.
Kepemilikan dan penguasaan tanah oleh warga, ternyata, hanya bisa bertahan selama satu dekade. Saat 1965 meledak, tanah-tanah warga turut kena sikat tentara.
Di Padang Halaban, penyingkiran serta pembersihan terhadap orang-orang yang dituding bagian dari PKI memudahkan praktik perampasan tanah.
Negara setidaknya memakai beberapa metode dalam memuluskan perampasan.
Pertama, aparat menarik KTPPT yang dimiliki warga dengan alasan “akan diperbaharui.” Jika menolak, ini taktik yang kedua, aparat segera menuduhnya anggota PKI dan menahannya sampai dokumen yang diinginkan diserahkan ke militer.
Pendekatan itu, kata Dianto lewat penelitiannya, memberikan daya teror yang besar kepada masyarakat, termasuk mereka yang sebenarnya tidak ada keterkaitan sama sekali dengan gerakan politik komunis.
Akhirnya, yang ketiga, didorong rasa takut, dokumen diberikan ke militer. Selepas dokumen dipegang, langkah keempat, negara tidak pernah mengembalikannya.
Kepahitan itu dirasakan keluarga Misno, warga Padang Halaban. Sejak Peristiwa 1965, kedua orang tua Misno memperoleh cap “terindikasi PKI” hanya karena mereka bekerja sebagai buruh perkebunan.
“Orang tua saya diminta menandatangani suatu surat dari kepala desa. Orang tua tidak tahu isi surat itu apa, gunanya untuk apa. Yang penting ditandatangani,” Misno memberitahu saya.
“Setelah ditandatangani, orang tua kami ternyata dianggap terindikasi orang terlibat [PKI]. Padahal orang tua kami tidak tahu sama sekali. Tidak pernah melakukan apa pun [kegiatan politik].”
Tiga tahun kemudian, 1968, perwakilan desa, didampingi aparat bersenjata, menyambangi rumah Misno. Mereka meminta dokumen KTPPT. Kalau tidak diiyakan, “dianggap PKI,” tegas Misno.
Kedua orang tua Misno tidak bisa menampik permintaan itu lantaran mereka telah berstatus “terindikasi PKI.” Melawan berarti dipenjara, atau yang paling buruk: hilang nyawa. Dokumen KTPPT pun langsung diserahkan.
“Tapi, setelah itu terkumpul, ternyata, surat itu dimusnahkan. Jadi, [tentara] menghilangkan barang bukti,” ingat Misno.
“Sampai pada 1969 ke 1970, di situlah mulai terjadi penggusuran.”

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Orang tua Misno sempat memohon agar eksekusi lahan ditunda supaya “anak-anak kami masih mempunyai tempat tinggal di waktu Idulfitri [yang waktu itu memang berdekatan],” Misno mengisahkan.
Permintaan orang tua Misno dimentahkan tentara.
Keenam desa yang sebelumnya didirikan oleh masyarakat, digilas tentara. Seluruh warga, berjumlah ribuan orang, dipindahkan ke wilayah luar perkebunan dengan lahan yang diberikan tidaklah seberapa.
Roda penghidupan masyarakat di Padang Halaban tidak sedikit yang kemudian menjelma sengsara.
Misno menyatakan bahwa dua kejadian sekaligus, pemberian cap PKI dan penggusuran, sudah menjerumuskan keluarganya dalam kesulitan. Pendidikan tinggi tidak bisa dia rengkuh, begitu pula pekerjaan yang mencukupi isi perut.
“Kami banyak kehilangan. Seperti tempat tinggal, kehilangan. Masalah pangan, sudah tidak ada. Terlebih lagi pendidikan kami sudah tidak punya,” ucapnya.
Apa yang dilalui Misno kurang lebih menggambarkan potret mayoritas penduduk di Padang Halaban yang beradu dengan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, dari pembantaian, pemenjaraan, sampai pengusiran paksa.
Akarnya ialah propaganda rezim militer yang menahbiskan mereka sebagai musuh yang seperti wajib dibasmi.
Pembacaan konteks atas tragedi di Padang Halaban tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial dan politik sebelum 1965 terjadi, ujar sejarawan yang mengajar di STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh, Sumatra Barat, Fikrul Hanif Sufyan.
Fikrul menerangkan keberadaan para buruh perkebunan di Sumatra Utara, atau Sumatra secara keseluruhan, didorong pembukaan besar-besaran lahan perkebunan oleh pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad 18.
Komoditas yang ditanam merentang dari sawit, teh, kopi, hingga karet.
“Pada umumnya, buruh di Sumatra itu memang didatangkan dari Jawa, dan ini tidak lepas dari soal kebijakan liberalisasi ekonomi Belanda, yang lalu disusul pengenalan terhadap [kegiatan] ekspor,” jelas pengajar tamu di Faculty of Art University of Melbourne ini saat saya wawancarai.
Pemerintah kolonial Belanda, kala itu, berpikir bagaimana caranya menghasilkan laba besar tanpa perlu mengorbankan banyak modal. Dipilihlah strategi mengirim tenaga kerja dari Jawa yang, menurut Belanda, dapat diupah murah.
Proses memboyong penduduk dari Jawa untuk keperluan tenaga kerja ini kelak dikenal sebagai transmigrasi.

Sumber gambar, Bettmann Archive/Getty Images
Sepanjang 1905—saat pertama kali dilakukan—sampai 1941, atau sebelum Jepang masuk ke Indonesia, program transmigrasi sudah mengirim hampir 190.000 orang dari Jawa.
Rata-rata, dalam satu tahun, sekitar 5.000 orang ikut berpartisipasi, dengan angka tertinggi diperoleh pada 1941: 60.000 orang.
Lambat laun, dinamika yang tercipta antara tenaga kerja dengan pemilik perkebunan—notabene Belanda—tidak senantiasa berlangsung mulus, tergambar, salah satunya, melalui tuntutan perbaikan kesejahteraan.
Riset menjelaskan semakin luas perkebunan yang dikelola pemerintah kolonial Belanda, semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya.
Hasil dari perkebunan mayoritas mengalir ke pemilik serta manajemen perkebunan. Buruhnya sendiri, ironisnya, tidak menerima bayaran yang layak.
Dari sinilah, Fikrul mengungkapkan, lahir organisasi serikat atau massa macam Sarbupri, BTI, maupun SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang berfungsi menjadi “wadah” para buruh perkebunan.
“Jadi, organisasi-organisasi itu memang memperjuangkan hak buruh, dan mereka ini militan. Kerangka besarnya adalah bagaimana mereka bisa membela buruh apabila terjadi konflik dengan perusahaan,” papar Fikrul.
“Yang kemudian mereka lakukan adalah aneksasi dengan, misalnya, seperti pemogokan, lalu protes, kepada pimpinan-pimpinan perusahaan.”
Aksi-aksi organisasi buruh atau massa tersebut lantas menarik minat dan perhatian rakyat. Selain itu, mereka dipandang bertindak konkret.
Fikrul mencontohkan Barisan Tani Indonesia (BTI). Berdasarkan penelitiannya di Sumatra Barat, masyarakat setempat begitu terbuka menerima BTI.
BTI, ucap Fikrul, membagikan berbagai perkakas pertanian macam cangkul atau topi caping kepada para petani. Pembagian tersebut “membuat para petani antusias,” sebut Fikrul.
Organisasi-organisasi ini, perlahan, bertransformasi menjadi simpul kekuatan politik, dan D. N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI), melihatnya sebagai peluang yang menguntungkan.
Setelah Peristiwa Madiun 1948 memudarkan pamor PKI, Aidit mulai membangkitkan kembali eksistensi partai. Cara yang dia ambil, menurut Fikrul, ialah dengan menggeser paradigma “PKI lama”—dipegang Semaun & Alimin.
Dalam benak Aidit, kekuatan massa-rakyat—buruh hingga petani—merupakan elemen penting guna merealisasikan ideologi partai.
Maka dari itu, sejak dekade 1950-an, Aidit mulai mengaktifkan sel-sel organisasi massa yang berada di bawah bendera PKI seperti Pemuda Rakyat, menurut Fikrul. Ditambah lagi BTI, juga SOBSI dan Sarbupri.
“Ini dalam rangka apa sebenarnya? Untuk mencapai Pemilu 1955. Tentunya ada motif untuk mengumpulkan suara, di samping membunyikan gerakan Kiri di seluruh Indonesia,” tandas Fikrul.

Sumber gambar, STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh
Pada helatan Pemilu 1955, PKI, yang sebelumnya dibonsai akibat Peristiwa Madiun 1948, duduk di peringkat empat nasional, di bawah PNI, Masyumi, serta NU. Dari Pemilu 1955, kekuatan politik PKI lalu berangsur tegak kembali dan disebut-sebut nyaris mencapi titik puncak pada 1960-an.
Dengan massa yang besar, ditopang eksistensi buruh dan petani di pedesaan, PKI mendorong penerapan kebijakan landreform (reforma agraria) supaya paripurna.
PKI memandang isu agraria sangat relevan untuk para buruh serta petani lantaran kepemilikan tanah, selama ini, tidak pernah berpihak kepada mereka.
“PKI beranggapan kenapa masyarakat kecil ini, selama ini, tidak pernah menjadi pemilik tanah dan hanya menggarap saja. Mereka lalu memperjuangkan itu,” terang Fikrul.
Di lapangan, demi mempercepat landreform, yang turut diimplementasikan lewat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, massa yang terhubung PKI serta organisasi di bawahnya menempuh “aksi sepihak”—merebut dan menguasai lahan dari tuan tanah.
Tidak jarang, aksi sepihak justru melahirkan gesekan dengan kelompok yang lain. Militer merupakan salah satunya.
Kebijakan landreform sendiri karam mengikuti tragedi 1965 karena dianggap buah pemikiran PKI. Nasib PKI beserta organisasi-organisasi yang mendukung haluan ideologi Kiri juga kena parang pemberangusan.
Operasi militer digalakkan secara besar, dari Sumatra hingga Bali, untuk membersihkan semua yang ada relasi ke PKI.
Propaganda kepada gerakan komunis yang dicetuskan militer menjadi pedoman komando, menyasar ratusan ribu, bahkan jutaan orang, untuk dibunuh, dihilangkan, atau dipenjara tanpa melewati peradilan yang sesuai.
Pada saat bersamaan, lahan-lahan yang dimiliki masyarakat dirampas oleh tentara. Melawan berarti termasuk seorang komunis.
“Perampasan lahan pasca-1965 itu merupakan yang terbesar skalanya. Tanah-tanah rakyat diambil oleh tentara dengan memanfaatkan sentimen PKI,” tegas dosen hukum tata negara dan HAM dari Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman.
Tanah yang dirampas tentara dikelola pengusaha
Di Padang Halaban, usai tanah-tanah warga di enam desa dirampas, pemerintah militer Orde Baru menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan perkebunan sawit bernama Plantagen Aktiengeschlischaft (Plantagen AG).
Pada 1972, Plantagen AG mengajukan HGU (Hak Guna Usaha) di atas lahan seluas lebih dari 5.000 hektare—mencakup 3.000 hektare yang sebelumnya berbentuk permukiman di enam desa.
Pencatatan hukum memperlihatkan bukan Plantagen AG yang mengendalikan HGU di Padang Halaban, melainkan PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban.
Perusahaan ini menjadi bagian dari bisnis Sinar Mas—melalui Golden-Agri Resources (GAR)—yang bergerak di industri kelapa sawit.
Kelak, tepatnya pada 1991, PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halaban berubah nama menjadi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT SMART).
HGU yang disodorkan ke PT SMART rutin diperpanjang sampai yang terbaru akan habis pada 2039 mendatang.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Area yang masuk hak pengelolaan luasnya mencapai lebih dari 17.000 hektare. Pada 2011, PT SMART memperoleh sertifikat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) untuk industri sawit yang berkelanjutan.
Pemberian hak penguasaan dan pemanfaatan lahan di Padang Halaban membuktikan bagaimana Soeharto dan Orde Baru membangun poros kekuasaannya dengan para pemodal, papar profesor sejarah di University of Amsterdam, Saskia Wieringa.
Tanah yang direbut paksa dari rakyat memanfaatkan propaganda komunis merupakan bekal Soeharto dalam memasang tali ikat kepada lingkaran pebisnis penopang kerajaannya.
Setelah militer melapangkan karpet untuk merebut kekuatan dari Sukarno (Orde Lama), rencana Soeharto berikutnya ialah mengatur ekonomi, ujar Saskia.
Ketika dia sudah memegang perekonomian, “masyarakat mampu dikendalikan,” tambahnya.
“Soeharto sendiri sangat menyadari bahwa jika dia ingin mempertahankan kekuasaan, dia harus membangun sekelompok pengusaha kaya raya di sekitarnya yang nantinya akan membiayai proyek-proyeknya sekaligus memastikan tentara tetap kuat,” tegas Saskia yang terlibat dalam penulisan buku Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil (2018).
“Jadi, kekuasaan ekonomi dan politik telah, setidaknya sejak saat itu, sangat erat terjalin di Indonesia,” tandas Saskia kepada saya.
Selama masa kekuasaan Soeharto, warga di Padang Halaban terpaksa menunduk dalam upaya pencarian keadilan.
“Tapi, tahu sendiri di zaman itu bagaimana,” ucap Misno.
Titik balik muncul pada 1998, berbarengan turunnya Soeharto dari kursi kekuasaan. Masyarakat di Padang Halaban mulai merapatkan barisan, menuntut pengembalian tanah yang dulu direbut tentara saat tragedi 1965.
“Jadi, eranya pecah Reformasi itu, ketua ataupun orang-orang tua dulu yang masih mempunyai kemauan untuk memperjuangkan hak yang telah diambil paksa itu, itu dicari seluruh masyarakat dari 6 desa itu [sekarang] di mana saja berada,” Misno menerangkan.
Perlawanan masyarakat Padang Halaban pun tumbuh dan menjalar, walaupun tidak (pernah) mudah.
Perlawanan warga Padang Halaban: Menduduki lahan
Misno menuturkan usaha masyarakat di Padang Halaban merebut kembali lahan-lahan yang dirampas negara dimulai tidak lama setelah 1998.
Waktu itu, warga di enam desa yang terdampak penggusuran berkumpul dan melakukan pendudukan di Kayu Putih, masih satu kawasan dengan perkebunan.
“Kami membuat kamp di hamparan jalan, tepi jalan. Kami mau masuk ke lokasi tapi dihadang oleh aparat bersenjata lengkap,” ingat Misno.
“Jadi, setelah itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami lalu mencari cara lain bagaimana supaya kami bisa menguasai lahan.”
Pertengahan 2000-an, warga membentuk Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS). Strategi yang ditempuh lebih bervariasi.
Pada 2009, warga yang tergabung dalam KTPHS, terdiri dari sepuluh kelompok tani, kembali menduduki lahan di sekitar Padang Halaban. Dari yang semula 20 hektare, lahan yang diupayakan lagi hak miliknya membesar menjadi 87 hektare.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
“Ada kesempatan pada waktu itu, tahun 2009, kami masuk kemari. Kami dalam satu pokja [kelompok tani] membuat kamp masing-masing,” tutur Misno yang menjabat Ketua Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPHS).
“Dan kami tetap mendapatkan intimidasi dari pihak aparat. Tapi, kami tidak gentar dan tetap melawan. Itu kira-kira ada hampir lebih kurang dari satu bulan kami mendapatkan intimidasi tadi.”
Pendudukan warga memantik reaksi dari perusahaan, PT SMART, yang kemudian melaporkan aksi mereka ke kepolisian dengan dalih penyerobotan lahan secara ilegal.
Warga tidak terima dan membalasnya secara hukum: menggugat PT SMART ke pengadilan.
Dari lapangan, pertarungan pindah ke ruang-ruang sidang.
Masyarakat meminta pengadilan mencabut HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan kepada perusahaan di atas lahan mereka, seluas 3.000 hektare, dan mengembalikannya sesuai fungsi semula: permukiman.
Sementara pihak perusahaan tak ketinggalan menggugat balik warga dengan pasal “perbuatan melawan hukum” sebab membangun permukiman di tanah perkebunan PT SMART.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Ujung dari proses pengadilan dan saling gugat ini adalah keputusan yang memenangkan PT SMART; bahwa penguasaan lahan di Padang Halaban sah serta berkekuatan hukum tetap. Masyarakat Padang Halaban sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, pada 2012, dan ditolak.
Keputusan MA mempertebal putusan-putusan di tingkat bawahnya yang ditindaklanjuti dengan pengumuman untuk eksekusi lahan yang diduduki masyarakat, tiga tahun berselang, 2015.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam surat rekomendasinya yang dikeluarkan pada Desember 2014, menyatakan meski sudah terdapat perintah eksekusi lahan, PT SMART diminta untuk mengupayakan dialog bersama warga agar tercipta kesepakatan.
“Mengusahakan adanya perdamaian dengan KTPHS terkait lahan seluas 87 hektare di dalam HGU PT SMART yang dihuni KTPHS,” demikian tulis Komnas HAM.
Warga enam desa di Padang Halaban memutuskan tidak beranjak dari lahan yang mereka duduki karena “pada faktanya mereka adalah pemilik lahan itu,” kata pegiat Ikatan Korban Hilang (IKOHI) Sumatra Utara, Suwandi, yang aktif mendampingi masyarakat.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
“Sekalipun ada intimidasi, bahkan dari pengadilan sudah dilakukan teguran hukum, sebagai bentuk peringatan supaya warga meninggalkan lokasi, warga tetap kemudian berusaha untuk mempertahankan,” papar Suwandi kepada saya.
“Mereka melawan dengan cara tidak mau meninggalkan lokasi.”
Putusan hukum yang keluar, Suwandi meneruskan, dimaknai warga di Padang Halaban sebagai “putusan yang belum memiliki keadilan.”
Suwandi mendesak pemerintah tidak sebatas memandang konflik di Padang Halaban semata dari sudut pandang tata kelola agraria.
Permasalahan di Padang Halaban, tegas Suwandi, mempunyai tali hubungan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada 1965.
Jika tetap diselesaikan dalam konsep penegakan hukum, “ini akan mentok,” jelas Suwandi.
“Maka langkah konkretnya negara hadir dan kemudian memberikan reparasi [ganti rugi] untuk warga dalam bentuk, misalnya, distribusi lahan. Negara punya banyak instrumen untuk itu,” tandas Suwandi.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Pemerintah, lewat Kementerian HAM, menyatakan bahwa sedang mengupayakan solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
“Kami akan mencari jalan terbaik bagaimana masalah ini, ke depannya, bisa selesai dengan sebaik-baiknya. Kami berupaya dan sebisa mungkin, dalam persoalan HGU ini, kita juga harus patuh pada aturan hukum,” kata Wakil Menteri HAM, Mugiyanto.
Mugiyanto menekankan semua pihak untuk menghentikan penggunaan cara-cara kekerasan, tidak terkecuali bentuk intimidasi. Pasalnya, konflik di Padang Halaban adalah “persoalan kemanusiaan dan harus diselesaikan dengan langkah-langkah yang baik,” imbuhnya.
Mugiyanto melanjutkan Kementerian HAM berkomitmen meredam konflik melalui jalur dialog, termasuk berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait serta perusahaan atau pihak swasta yang terlibat di dalamnya.
Sinar Mas Agribusiness and Food, dalam tanggapan ke BBC Indonesia, mengatakan perusahaan telah berupaya mencari penyelesaian secara damai melalui proses mediasi di konflik Padang Halaban.
Mereka menambahkan perlindungan HAM merupakan bagian inti dari komitmen keberlanjutan perusahaan.
“Kami tetap berkomitmen pada dialog dan keterlibatan sebagai dasar dalam menangani setiap perhatian yang disampaikan oleh masyarakat,” jelas Sinar Mas.
Mengacu laporan publik, pihak PT SMART meyakini “setiap insiden atau tuduhan sosial soal hak asasi manusia” dapat “berdampak negatif terhadap citra dan reputasi perusahaan.”
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa konflik yang dihadapi masyarakat Padang Halaban akan menemui titik terang.
Misno merasa keadilan tidak berpihak kepada mereka selama persoalan tanah dan ruang penghidupan belum terselesaikan.
“Kami sejak 1960-an, 1970-an, sampai sekarang, itu masih terjajah,” tegasnya.
“Kami kecewa, betul-betul kecewa. Tidak ada keadilan ataupun pemerataan bagi masyarakat. Kalau pemerintah betul-betul peduli, tanah-tanah itu harus dikembalikan kepada kami.”
Jenazah-jenazah di perkebunan sawit
Kartini mengajak saya mengunjungi lokasi yang diketahui menjadi pembuangan jasad mereka yang dianggap anggota atau mendukung PKI.
Tempat yang Kartini maksud berada di antara perkebunan sawit dan aliran sungai, berjarak sekitar 20 menit perjalanan dari permukiman warga.
Di area tersebut, dulu, terdapat satu lubang dengan ukuran tidak kelewat besar. Empat orang dipercaya dibunuh dan dimasukkan ke lubang itu.
“Kalau dilihat dari luar itu yang terlihat cuma kakinya. Jenazahnya berdesak-desakan. Dijejalin jadi satu,” Kartini mengenang.
Kartini berkisah bahwa sebab menjadi lokasi pembuangan mayat korban 1965, orang-orang takut melewati daerah tersebut.
“Anak-anak kecil kalau terpaksa harus lewat di sini, mereka buru-buru naik sepeda,” imbuhnya.
Kartini masih kecil saat 1965 terjadi. Dia tidak tahu sama sekali politik, juga apa itu komunisme.

Sumber gambar, BBC/ANINDITA PRADANA
Yang dia tahu—dan lihat sendiri—tentara menangkapi tetangga yang dia kenali. Ada yang dibawa dengan motor, ditahan di penjara, sampai dihilangkan tanpa jejak.
Keluarga Kartini tidak terlibat, atau berurusan, apa pun dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kenyataan hidup justru membawanya ke pahit yang belum sembuh sampai saat ini.
Setiap Peristiwa 1965 diperingati, dan sekarang telah berusia enam dekade, satu hal yang menurut Kartini selalu absen, mungkin sengaja dilupakan, dalam percakapan.
“Seharusnya negara minta maaf sama keluarga korban,” pungkasnya.
Ini adalah seri kedua Liputan Khusus “Konflik lahan dan Tragedi 65”. Seri pertama, berjudul berjudul Tentara merampas tanah rakyat secara sistematis saat Tragedi 1965 – Dicap komunis, lahannya dipakai berbisnis bisa Anda simak di sini.