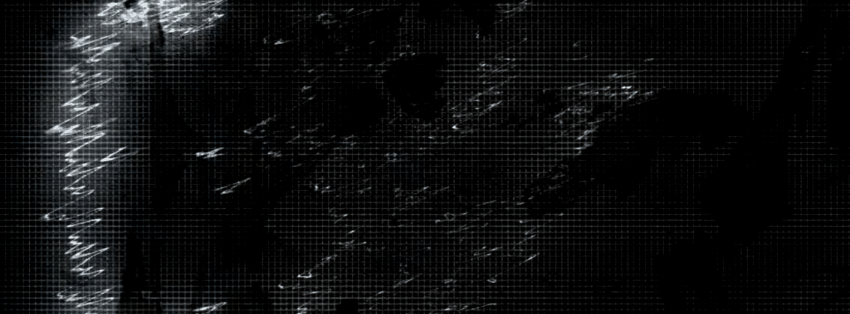Sumber gambar, Dokumen pribadi Zikra, Riska, Arifa
-
- Penulis, Heyder Affan
- Peranan, Wartawan BBC News Indonesia
Tiga perempuan muda Aceh menyuarakan kritik terhadap sebagian pelaksanaan syariat Islam di wilayahnya yang dianggap merendahkan perempuan melalui keahlian mereka di bidang seni.
Seni peran, instalasi serta fotografi, menjadi media bagi tiga perempuan muda ini untuk angkat bicara agar didengar oleh pemerintah dan masyarakatnya.
Zikrayanti, Arifa Safura dan Riska Munawarah—melalui keterampilan dan kemampuannya—juga berusaha menggerakkan banyak orang agar lebih dekat ke arah kesetaraan gender.
Salah-satu langkah terbarunya, mereka berkolaborasi menggelar acara seni guna menafsir ulang sosok pahlawan nasional Cut Nyak Dhien.
Mereka memberi bentuk baru pada sosok itu dari kacamata pengalaman ketubuhan perempuan dan menariknya ke situasi sekarang.

Sumber gambar, Ponjria
Memerankan sosok Cut Nyak dalam pentas monolog, misalnya, Zikra menarik secara kuat karakter sang pahlawan untuk memotret situasi sekarang.
“Yang mau kubilang begini: Bagaimana perjuangan Cut Nyak dulu bisa semodern itu, feminismenya, kekuatan gendernya. Tapi sekarang? Soal ketubuhan kita sebagai perempuan justru dimasalahkan. Kenapa yang disasar perempuan. Jadi aku melihat kayak kita ini mundur, bukan maju,” kata Zikrayanti.
Sementara, Arifa Safura melalui berbagai seni instalasinya, jelas-jelas mengkritik pelaksanaan syariat Islam yang sebagian disebutnya memarjinalkan perempuan.
“Kenapa fokusnya tubuh, tubuh dan tubuh [perempuan], kenapa tidak diurus soal sampah, atau korupsi parah di Aceh,” ujarnya.
Dan, Riska Munawarah—dikenal sebagai fotografer dokumenter—tak kalah lantang: “Di sini jilbab jadi kayak kontrol sosial bagi perempuan.”

Sumber gambar, Reza Saifullah
Karya-karya Zikra, Arifa dan Riska memang menyuarakan keberanian untuk menolak nilai-nilai patriarki yang dianggap masih mendominasi.
Tiga perempuan yang lahir di Aceh ini tumbuh besar saat terjadi perubahan luar biasa di wilayah mereka tinggal.
Diawali tsunami yang meluluhlantakkan Aceh, lalu konflik bersenjata puluhan tahun pun disudahi.
Hingga akhirnya penerapan syariat Islam di tempat mereka lahir dan tumbuh dalam perdebatan yang dianggap belum tuntas.

Sumber gambar, Dokumen pribadi Riska Munawarah
Dua dari tiga perempuan ini, misalnya, ketika masih anak-anak menyaksikan bagaimana ibu-ibu mereka dipaksa mengenakan jilbab.
Mereka lalu bercerita bagaimana persentuhan mereka dengan aturan yang mewajibkan perempuan muslim di Aceh mengenakan jilbab.
Selengkapnya inilah kisah Zikrayanti, Arifa Safura dan Riska Munawarah:

‘Sebelum ada syariat, tidak ada yang mengatur ketubuhan perempuan’
Zikrayanti, seniman pertunjukan
Lebih dari 25 tahun lalu, saat duduk di bangku kelas dua sekolah menengah pertama (SMP), Zikrayanti memutuskan mengenakan jilbab.
“Satu sekolah syok,” Zikra seraya terkekeh mencoba mengingat lagi bagaimana reaksi kawan-kawannya—dan para guru, tentu saja—melihat perubahan pada penampilannya.
“Soalnya, aku paling dianggap ibaratnya-bandel di sekolah,” Zikra kali ini tak kuasa menahan tawa.
“Saya cewek tomboi, begitu ibaratnya.”
Ketika itu, pada 1999, ketika Zikra duduk di bangku SMP, tuntutan kemerdekaan muncul bergelombang di Aceh. Setahun sebelumnya Soeharto mundur dari kursi presiden.

Sumber gambar, Dokumen Zikrayanti
Jakarta kemudian mencoba menawar kemarahan itu dengan memberikan status keistimewaan kepada wilayah di ujung utara Sumatra itu. Aceh lalu diberi hak untuk menerapkan apa yang disebut sebagai syariat Islam.
Jalan keluar yang disorongkan Jakarta guna meredam perlawanan dari Aceh itu, seperti tercatat dalam sejarah, tak digubris oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
GAM tetap menuntut kemerdekaan. Dan mereka beralasan pula bahwa rakyat Aceh sudah lama mempraktikkan—apa yang disebut hukum Islam—dalam hukum adatnya.

Sumber gambar, Ibnu Sina
Toh, sekian tahun kemudian, setelah perdamaian diteken di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005, tidak ada penolakan dari masyarakat Aceh ketika parlemen pusat pada 2006 mengesahkan aturan hukum yang memberi wewenang Aceh untuk menerapkan syariat Islam.
Mulai saat itulah kaum perempuan Aceh diwajibkan mengenakan jilbab di tempat umum—mereka bakal diberi sanksi bila melanggarnya.
Di sinilah, Zikra berkata kepada saya bahwa pilihannya menutup aurat pada 1999 itu dengan kesadaran diri.
Bukan karena keharusan setelah diberlakukan formalisasi syariat Islam di Aceh, katanya berulang-ulang.
“Karena waktu itu syariat belum ada,” tegasnya.

Sumber gambar, Ibnu Sina
Zikra berusia 41 tahun, ibu dari satu anak berusia 13 tahun, berkacamata, dan dikenal sebagai seniman pertunjukan.
Sehari-hari dia adalah dosen di program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Islam Negeri Ar-raniri, Banda Aceh.
Kepada saya, Zikra menyebut dirinya sebagai salah-seorang warga Aceh yang mengkritisi sebagian praktek syariat Islam yang disebutnya “tidak berpihak pada perempuan”.
“Di satu sisi aku tidak menolak syariat Islam,” katanya, seraya menekankan agar saya mencatatnya.
Tapi yang dia tolak adalah beberapa praktik yang disebut Zikra tidak berpihak pada perempuan.

Sumber gambar, Dokumen Zikrayanti
Saya menanyakan ulang penilaiannya itu, dan Zikra menegaskan jawabannya:
“Kalau kita lihat pada konteks dan pada kenyataannya, ketika [formalisasi syariat Islam] dipakai untuk kebutuhan politik dan kebutuhan tertentu, selalu yang diserang kita, perempuan.”
Walaupun sering kali berterus-terang, Zikra memilih bersikap hati-hati ketika pertanyaan saya menyinggung seperti apa wajah Aceh sebelum dan sesudah diterapkan syariat dari pengalamannya sebagai perempuan.
Dan dia mengaku sudah sering membahas pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
“Sebelum syariat, itu tidak ada yang mengatur ketubuhan perempuan,” Zikra berkata.
“Tapi setelah syariat, ketubuhan perempuan selalu jadi sasaran dan menjadi aturan,” tambahnya.

Sumber gambar, Dokumen Zikrayanti
Dia memberikan contoh soal razia oleh polisi syariat yang memasalahkan pakaian perempuan atau larangan perempuan merokok di tempat umum.
“Sampai baju olah raga [untuk perempuan] diatur sampai sedemikian rupa.”
Dari kaca mata ketubuhan perempuan, Zikra lalu mencoba melihat seperti apa Aceh dulu sebelum syariat diformalkan.
Dahulu, demikian Zikra (“dalam ingatan saya,” ujarnya, menekankan), perempuan Aceh bebas memilih atas tubuhnya. Kemudian mereka tidak pernah menjadi obyek, tambahnya.
“Mau jilbab kek mana, mau pake jilbab, tidak pakai jilbab, tapi tetap religius,” katanya.

Sumber gambar, Dokumen Zikrayanti
Zikra lalu teringat pengalamannya dulu menghadiri peringatan Maulud di satu gampong di Banda Aceh. Dalam ingatannya, acara itu dihadiri semua orang, termasuk para perempuan yang tidak berjilbab.
Begitulah cara pandang Zikra. Tapi dia tak semata melontarkan sikap. Dia sudah berbuat. Dalam beberapa potret dirinya yang saya terima, Zikra terlihat mengenakan jilbab yang relatif longgar.
Di sinilah dia kemudian bersikap bahwa tidak perlu ada aturan tentang seperti apa bentuk jilbab yang benar atau sebaliknya.
“Terserah aku menutup aurat dengan caraku, mau pakai gorden, mau pakai selendang, atau pakai topi,” ujarnya lalu tertawa kencang.
“Jadi jangan sampai cara menutup aurat pun harus dipakemkan.”

Sumber gambar, Dokumen Zikrayantri
Meskipun berulangkali menegaskan bahwa dirinya menutup aurat karena meyakininya sebagai kewajibannya sebagai muslim, Zikra menyebutnya sebagai sebuah pilihan.
Dan karena itulah ketika ada perempuan muslim tidak mengenakan jilbab, dia tidak dalam posisi menilainya.
“Itu pilihan, itu persoalannnya dengan Tuhan,” tegasnya.
“Sebagai manusia, sebagai muslim, aku pribadi mungkin dengan orang terdekat, aku boleh menasihati. Tapi aku enggak boleh mengontrol bagaimana cara dia berpikir. Karena dalam Islam yang aku pelajari, perlu mengingatkan sesama Muslim, tapi ada batasannya juga kan,” paparnya.
Di sisi lain, Zikra pun mengkritik sikap sebagian orang yang mempertanyakan pilihannya—dan jutaan perempuan muslim di dunia—untuk mengenakan jilbab.
“Bagiku sebagai muslim, aku percaya dan sudah mempelajari, bahwa menutup aurat itu wajib, ” katanya.

Sumber gambar, Dokumen Zikrayanti
Dan walaupun di sana-sini ada kelemahan dalam praktek syariat Islam yang disebutnya masih merendahkan perempuan, Zikra menunjukkan bahwa dirinya mampu angkat bicara.
Dia ingin suaranya didengar, dan dia berupaya menggerakkan banyak orang lebih dekat ke arah kesetaraan gender.
“Aku cewek berjilbab dengan kesadaran diri, aku menikah di usia 25 tahun, kemudian mendapat rezeki kuliah sarjana strata dua (S2) di Taiwan. Waktu itu anakku baru tiga bulan, tapi aku memilih pendidikan,” suara Zikra terdengar nyaring.
Pengalamannya berinteraksi dengan banyak orang selama sekolah di Taiwan (dia mengambil studi perpustakaan dan ilmu informasi) juga membuatnya mahfum bahwa jilbab atau Islam masih terkadang disalah-pahami.
“Saya satu-satunya yang berjilbab di kampus,” ungkapnya.
Respons seperti itu dia rasakan selama di Taiwan ketika Zikra bercerita bahwa dia meninggalkan sementara suami dan anaknya demi pendidikan.
“Aku ingin menunjukkan perempuan muslim tidak seperti mereka bayangkan,” ungkap anak ketiga dari lima bersaudara ini.
“Walau aku berjilbab, aku tidak pernah dikekang, buktinya aku bisa main teater, olahraga, berkesenian, dan tidak terhambat. Pergi ke mana-mana diberi kebebasan oleh orang tua,” katanya lagi.
Dalam momen-momen seperti itulah, Zikra mengaku beruntung memiliki ayah dan suami yang disebutnya tidak patriarki.

Sumber gambar, Dokumen Zikrayanti
Dan Zikra terus melangkah.
Pada pekan pertama dan kedua September 2025 lalu, Zikra dan dua rekannya sesama seniman asal Aceh, Arifa Safura dan Riska Munawarah, berkolaborasi membikin sebuah acara.
Dipersatukan oleh tema yang sama, yaitu menafsir ulang sosok Cut Nyak Dhien (pahlawan nasional dari Aceh) dari—istilah mereka—kaca mata perempuan, mereka menggelar acaranya di Rumah Cut Nyak Dhien di Desa Lampisang, Aceh Besar.
Zikra mementaskan Monolog Tubuh Cut Nyak dalam sebuah seni pertunjukan.
Lewat gerak tubuh dan minim dialog, Zikra menafsir ulang sang tokoh itu secara imajinatif dan bukan realis.

Sumber gambar, Ibnu Sina
“Secara garis besar, memang aku merefleksikan kisah Cut Nyak secara imajinatif. Aku tidak memasukkan Cut Nyak sebagai tokoh realis. Jadi aku hanya mengambil pergolakan tubuh dia, makanya kubilang monolog tubuh. Aku minim kata-kata,” paparnya kepada saya melalui sambungan telepon, Kamis, 28 Agustus 2025 lalu.
Melalui gerak tubuh dalam beberapa babak, Zikra menunjukkan bagaimana tubuh merespons kesedihan Cut Nyak; bagaimana tubuhnya merespons ketika dia harus ke medan perang; bagaimana tubuhnya merespons ketika dia sudah ditaklukkan, tapi dia tak mau takluk.
“Nah sampai di akhirnya, aku kembali ke konteks bahwa aku mengingatkan bahwa kita adalah Cut Nyak yang sekarang,” jelasnya.
Kepada saya, Zikra berulangkali mengutarakan bahwa pementasan ini dirinya memang berniat mengkritik pada situasi Aceh sekarang.
“Yang mau kubilang begini: Bagaimana perjuangan Cut Nyak dulu bisa semodern itu, feminismenya, kekuatan gendernya. Tapi sekarang? Soal ketubuhan kita sebagai perempuan justru dimasalahkan. Kenapa yang disasar perempuan. Jadi aku melihat kayak kita ini mundur, bukan maju.”
Suara Zikra lagi-lagi nyaring terdengar dan gaungnya saya rasakan hingga sekarang.

‘Saya tidak menolak syariat, tapi kenapa fokusnya ke tubuh perempuan, dan bukan korupsi’
Arifa Safura, seniman instalasi
“Selama ini narasi Cut Nyak Dhien itu dibangun oleh laki-laki…”
Arifa Safura mengutarakan hal itu ketika saya bertanya mengapa dia menawarkan tafsir berbeda dalam melihat sosok pahlawan nasional asal Aceh itu.
“Selama ini,” sambung seniman perempuan asal Aceh kelahiran 1993 ini, “sosoknya dibingkai secara sangat politis sekali.”
Dari zaman kolonial Belanda, zaman kemerdekaan, hingga akhirnya dia mendapat status pahlawan nasional, Arifa menganggap narasi yang mengiringi Cut Nyak Dhien itu “cenderung politis.”

Sumber gambar, Dokumen Arifa Safura
Demikian pula saat Aceh menerapkan formalisasi syariat Islam, sosoknya pun dikaitkan dengan “visi keislaman di Aceh”.
Bagi Arifa, sudah saatnya sosoknya dilihat dari perspektif perempuan.
“Arifa ingin mengenal Cut Nyak Dhien dengan menggalinya langsung dari perspektif perempuan.”
Pekan pertama September 2025 lalu, seniman yang mendalami seni instalasi ini berkolaborasi bersama dua seniman lainnya. Temanya seputar sosok Cut Nyak Dhien dan ketubuhan perempuan.

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
Dua rekannya, Zikrayanti mengeksplorasi sosok itu melalui médium seni pertunjukan, dan Riska Munawarah melalui karya fotografi dokumenter. Adapun Arifa menggunakan medium seni instalasi.
Untuk mengenal luar dalam Cut Nyak, Arifa selama berbulan-bulan melakukan riset.
Dan, awalnya, Arifa merasa kesulitan ketika harus mendefinisikan sosok tersebut dan melukisnya ke dalam kanvas. Ini dialami Arifa lantaran narasi seputar diri Cut Nyak kebanyakan ditulis oleh pria.
“Arifa cuma ketemu novel tentang Cut Nyak Dhien yang [ditulis] Szekely Lulofs,” ungkapnya. Lulofs (1899-1958) adalah penulis asal Belanda.

Sumber gambar, Dokumen Arifa Safura
Tapi proses pencariannya akhirnya membuahkan hasil. Ini dialaminya setelah membaca satu disertasi tentang Cut Nyak Dhien.
Arifa merasa mengenal lebih dalam sosok Cut Nyak Dhien setelah membaca isi disertasi Myra Mentari Abubakar berjudul Cut Nyak Din (1848–1908): A Study of Female Heroism in Indonesia.
Myra adalah perempuan Aceh lulusan S3 di Australian National University. Dan Arifa diizinkan untuk membaca hasil penelitian tersebut.
“Cut Nyak Dhien dikenang secara interkontinental, mulai dari aspirasi feminis Eropa era kolonial, visi nasional tentang persatuan Indonesia, konflik regional hingga visi keislaman lokal di Aceh,” papar Arifa setelah menyelami hasil penelitian Myra.

Sumber gambar, Dokumen Arifa Safura
Arifa menyimpulkan, penelitian Myra itu menunjukkan bahwa citra pahlawan perempuan diciptakan sedemikian rupa untuk melayani kebutuhan politik kontemporer.
Dan seringkali memperkuat gagasan maskulin tentang kepahlawanan, tambahnya.
“Alih-alih memberdayakan perempuan, yang ada hanya memperkuat politik patriarki. Myra juga berpesan agar narasi tentang Cut Nyak Dhien lebih banyak dibangun menurut perspektif perempuan,” ujarnya.

Sumber gambar, Dokumen Museum MACAN/Kompas.com
“Bagi saya Myra adalah kunci dalam proses pengkaryaan ini,” tambah Arifa.
Proses selanjutnya, Arifa mencoba menautkan perspektif Myra itu dengan pengalaman ketubuhan perempuan Aceh. Dia kemudian memilih perempuan Aceh saat wilayah itu dilanda konflik dan setelahnya.
Tapi mengapa pilihan jatuh pada perempuan korban konflik? Tanya saya.
“Karena relevan dengan masa Cut Nyak Dhien dulu,” jawab Arifa.

Sumber gambar, Tropenmuseum/Wikipedia
Seperti diketahui, Cut Nyak hidup pada masa perang, dan menurutnya, fakta ini “sangat terhubung” dengan nasib para perempuan penyintas konflik di Aceh.
Melalui pendekatan sejarah lisan, Arifa kemudian merekam pengalaman ketubuhan para perempuan penyintas konflik. Dia mendatangi salah-satu satu desa di Aceh untuk mewawancarai beberapa di antara mereka.
Selain penyintas perempuan, Arifa juga wawancara eks Inong Balee—istilah yang merujuk para janda yang ditinggal meninggal suaminya akibat konflik, atau para perempuan yang bergabung dalam pasukan bersenjata GAM—, janda, perempuan menikah dan tidak menikah, hingga anak-anak perempuan.
“Tujuannya untuk mengenal lebih dalam sosok Cut Nyak Dhien. Dari proses tersebut, saya merasakan bahwa Cut Nyak Dhien bersemayam di setiap urat nadi Inong [perempuan Aceh],” tegasnya.

Sumber gambar, Dokumen Arifa Safura
Selama berproses, Arifa lalu teringat apa yang diutarakan pelukis legendaris Georgia O’Keeffe. Suatu saat sang perupa berkata “I feel there is something unexplored about woman that only a women can explore.”
“Saya juga merasakan demikian, ketika sosok Cut Nyak Dhien dilukis berdasarkan pengalaman ketubuhan perempuan, khususnya perempuan yang hidup pada masa konflik Aceh,” paparnya.
Dan, “mengilhami pengalaman ketubuhan perempuan, membuat saya berani memulai goresan pertama di canvas. Lahirlah karya Cut Nyak Dhien “Tanoh, Tuboh, Ie Mata, Darah ngoen Nyawoeng (Tanah, Tubuh, Air Mata, Darah dan Nyawa).”

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
Sebagai karya instalasi, Arifa memadu beberapa medium. Pertama dia melukis sosok Cut Nyak dengan cat minyak di atas kanvas. Dia melukis sang tokoh tanpa referensi dari berbagai lukisan Cut Nyak yang sudah beredar di mana-mana.
“Tangan Arif bergerak, ketika mengulang-ulang rekaman-rekaman, pengalaman, ketika Arifa bertemu dengan perempuan-perempuan [penyintas korban konflik di Aceh] hingga inong balee yang Arifa wawancarai. Di situlah, baru mulai bisa bergerak untuk melukis potret Cut Nyak,” paparnya.

Sumber gambar, Dokumen Pribadi Arifa Safura
Selain lukisan, ibu dua anak ini juga menuliskan ‘Tanoh, Tuboh, Ie Mata, Darah ngeun Nyawoeng’ dengan menggunakan aksara Arab Jawi Aceh.
Dia tuliskan itu di sisi kanan lukisan sang tokoh. Pada karya-karyanya yang lain, Arifa beberapa kali menggunakan metode yang sama.
Di atas meja, Arifa meletakkan pula kain goni, lampu teplok, peta Aceh, rempah, serta seutas tali. Benda-benda itu merupakan simbol-simbol, seperti ketidakadilan yang dialami perempuan (goni) hingga kolonialisme (rempah).
Di bagian bawah, Arifa meletakkan sebuah reel tape (alat pemutar musik) berukuran besar. “Arifa pakai kolase suara, bunyi-bunyi dari zaman penjajahan sampai sekarang.”

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
Melalui karya seni instalasi terbarunya, seniman kelahiran Meureudu, Pidie Jaya, Aceh, ini mengaku tidak semata menyoal isu perempuan, tetapi juga makna perihal kolonialisme.
“Kita sekarang masih dalam situasi tersebut,” ujarnya.
Butuh waktu bertahun-tahun bagi dia untuk sampai pada tahap selesai karya tersebut.
Melalui berbagai bacaan (“termasuk novel Han Kang berjudul Human Act (2014),” ujarnya), kehadirannya sebagai seniman kolaborator di Gwangju Biennale 2024 (Gwangju salah-satu kota di Korsel, di mana pada 1980, gerakan mahasiswa di sana melawan rezim otoriter), hingga persentuhannya dengan perjalanan panjang konflik di Aceh, Timor Leste, serta Papua, lahirlah karya tersebut.

Sumber gambar, Dokumen Pribadi Arifa Safura
Karya-karya Arifa memang tidak terlepas dari isu hak asasi manusia, keadilan bagi perempuan, serta—tentu saja—trauma konflik.
Karya instalasinya yang dipamerkan di Rumah Cut Nyak Dhien itu jelas tidak terlepas pula dari pengalaman masa kecilnya ketika Aceh dikoyak konflik.
“Masa kecil Arifa di Meureudu, Pidie Jaya, itu zona merah saat masa konflik,” katanya.
Istilah zona merah itu merujuk pada fakta bahwa wilayah itu dulunya basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Arifa lantas teringat, di masa kanak-kanak, dia tidak pernah melihat upacara bendera Merah Putih di sekolahnya.

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
Dan sulit dia lupakan, saat terdengar baku tembak, guru-guru panik dan menyelamatkan murid-muridnya dengan menggendongnya.
“Kemudian kami berbulan-bulan tidak sekolah. Arifa teringat sekolah kakak dibakar oleh GAM,” ungkap anak kedua dari tiga bersaudara ini.
Dan karena itulah, kali ini sambil menahan tawa, dia mengaku baru bisa berbahasa Indonesia saat di bangku SMP.

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
Memori masa kecilnya yang menjadi latar karyanya itu juga tak terlepas dari sosok ibu (yang bernama Safura) dan neneknya (Halimah).
Arifa lalu berkata bahwa dirinya tumbuh besar dari orang tua tunggal. Merekalah yang membesarkan Arifa dan saudara-saudaranya.
“Rifa lihat sendiri, nenek bisa pasang pagar sendiri. Semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan dia jualan supaya kami bisa sekolah,” katanya.
Kenyataan seperti ini bukan yang hal aneh di kampungnya. “Saya lihat di kampung itu banyak sekali janda, karena suaminya meninggal ketika konflik.”
Di sinilah, Arifa melihat betapa kaum perempuan di kampungnya sudah terbiasa tampil di ruang-ruang publik. Mereka pergi ke sawah hingga memotong pohon.
“Mereka superior di kampungnya. Walau dalam kemiskinan, tapi bisa berdaya tanpa adanya laki-laki,” ujar ibu dari Adam (7 tahun) dan Sulaiman (4 tahun) ini.

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
Begitulah Arifa yang semenjak 2014 mulai aktif berkesenian. Tercatat dalam proses pengkaryaannya, dia disebut menelusuri sosok melalui pendekatan arsip, tutur bunyi, lukisan dan instalasi.
Lima tahun lalu, Arifa mendirikan ‘Perempuan Berbicara’. Di forum itu, dia menjadikannya sebagai medium pemulihan, dan advokasi nonligitasi.
Tujuannya, mencari mitos inferioritas perempuan, serta memperjuangkan kesetaraan, serta kampanye anti kekerasan berbasis gender.
Isu kesetaraan gender memang menjadi salah-satu fokus dalam karya-karya Arifa.

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
Tahun lalu, dalam acara yang digelar komunitas seni Kanot Bu di Banda Aceh, Arifa diundang untuk berkarya.
Di sanalah dia kemudian menampilkan lukisan yang diberi judul ‘Si gadis berambut panjang’.
“Idenya terlintas pada waktu itu adalah hantu di kampung. Dalam bahasa Aceh disebut ‘Si dara panyang ok’. Dulu takut kalau pergi ngaji di malam hari,” ungkapnya seraya tergelak.
Di atas kanvas, dia menampilkan sosok berambut panjang yang terurai. Punggungnya dibiarkan terbuka.
Menjelang pameran, Arifa merasa tidak nyaman lantaran seingatnya banyak pria di komunitas Kanot Bu.

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
“Mereka pasti melihat sosok itu perempuan, bukan hantu,” Arifa mencoba mengingat-ingat lagi.
Dia saat itu juga merasa ketakutan: Apakah karyanya nanti dirazia oleh polisi syariah?
Lalu apa yang dia lakukan? “Saya ambil hijab saya, saya tutupi lukisan itu, tapi saya persilakan [membuka hijab itu] untuk melihatnya.”
Razia itu tak pernah terjadi. Arifa lega lantaran bahkan dia diberi kesempatan untuk menjelaskan arti dan pesan lukisan tersebut.
“Karya ini tersirat makna ketubuhan, ketika tubuh perempuan sering dipolitisasi. Arifa dengan satir menghijabkan sosok tubuh hantu,” jelasnya kepada saya.
Tak bisa dipungkiri karya seni Arifa tak bisa dilepaskan dari konteks di mana dia lahir dan tumbuh besar.
Jelas dia bicara soal pelaksanaan syariat di tanah kelahirannya. Arifa berada di barisan orang-orang di Aceh yang sejak awal mengkritisi sebagian prakteknya yang disebut memarjinalkan perempuan.
“Kenapa fokusnya tubuh, tubuh dan tubuh [perempuan], kenapa tidak diurus soal sampah, atau korupsi parah di Aceh.”
“Dalam karya ini, Arifa juga mengkritik tentang suara perempuan yang jarang didengar. Apakah perempuan harus menjadi hantu dulu supaya ditakuti dan didengar?”

Sumber gambar, Dokumen pribadi Arifa Safura
Dalam keseharian, setidaknya seperti terlihat dalam foto-foto dirinya, Arifa mengenakan kerudung longgar dan membiarkan rambutnya bagian depan terlihat.
Dia memahami benar bagaimana membawa tubuhnya dalam konteks sosial seperti apa di Aceh. Hal ini dia tekankan, walaupun dia mengaku pada awal-awalnya dia mempertanyakannya secara habis-habisan.
“Fakta ada regulasi wajib pakai jilbab, ya aku pakai kalau saat ada di Aceh. Tapi kalau di luar Aceh, ya, tubuhku adalah hak-ku,” kata Arifa yang melakoni profesi advokat ini.
“Setiap orang punya hak atas tubuhnya sendiri,” Arifa, alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, ini menandaskan.


‘Apakah pembatasan menjadikan Aceh ruang aman bagi perempuan? Sayangnya, fakta berkata tidak!’
Riska Munawarah, fotografer
Ada dua peristiwa di masa kecil yang amat membekas dan sulit dilupakan Riska Munawarah.
Kejadian ini kelak ikut mewarnai kesadarannya dalam pilihan-pilihan tema yang menjadi ciri khas karya-karya fotografi dokumenternya.
Pertama, cerita ibunya pernah dicegat oleh polisi syariat di sudut Kota Banda Aceh.
Saat itu, sang ibu—Chairani, kelahiran 1960—tengah mengantar kue untuk dititipkan di toko di depan rumah mereka.
“Tiba-tiba pulang dikasih jilbab,” Riska mencoba mengingat-ingat lagi.

Sumber gambar, Dokumen Riska Munawarah
“Katanya, di depan [rumah] ada ramai-ramai polisi syariat kasih jilbab [kepada warga yang tidak mengenakan jilbab].”
Kedua, peristiwa sang ibu harus membeli seragam baru SD yang sesuai syariat untuk Riska. Padahal Riska sudah dibelikan baju lengan pendek dan rok pendek.
“Jadi kami harus beli baru lagi, pakai rok panjang, baju panjang,” kenang perempuan kelahiran Kota Banda Aceh pada 1998 ini.

Sumber gambar, Dokumen Riska Munawarah
Saat usia Riska memasuki 9 tahun, wajah Aceh memang berubah untuk selamanya.
Sejarah mencatat: Gempa dan tsunami meluluhlantakkan sebagian wilayah Aceh di akhir Desember 2004. Lebih dari seratus lima puluh ribu orang hilang dan meninggal dunia.
Kemudian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia memilih jalan damai pada pertengahan Agustus 2005, setelah lebih dari 29 tahun konflik berdarah-darah membuat Aceh terpuruk.
Kira-kira setahun kemudian, formalisasi syariat Islam mulai dijalankan di wilayah itu dalam sebuah keputusan politik, ketika perdebatan di kalangan para ahli agama tentang hal itu dianggap belum tuntas.

Sumber gambar, Dokumen Riska Munawarah
Pada tahun-tahun itulah, ibunya yang semula tak berjilbab, ‘dipaksa’ otoritas berwenang agar mengenakannya. Demikian pula apa yang dialami Riska kecil.
Kini, hampir 20 tahun kemudian, Riska kepada saya mengaku bahwa dia mengenakan jilbab “karena lingkungan sosial”.
“Saya sendiri mengenakan jilbab, bukan karena [bagian] pencarian jati diri, tapi karena lingkungan sosial, karena sudah terbiasa,” tegasnya.
Baginya proses berjilbab itu “sangat personal”. Dan, dia menekankan, seharusnya tidak ada tekanan untuk mengenakannya atau tidak.

Sumber gambar, Dokumen Riska Munawarah
Lantaran sudah terbiasa, dan lagipula mayoritas masyarakat Aceh berjilbab, Riska merasa kain yang menutupi kepalanya sama-sekali tidak menganggu aktivitasnya sehari-hari.
“Sebaliknya, kalau Riska tidak pakai jilbab, orang-orang melihatnya aneh,” akunya.
Di sinilah dia kemudian teringat pengalaman teman-temannya sesama Muslim di Aceh yang tidak mengenakan jilbab.
Dari kesaksian teman-temannya itu, Riska menangkap kesan bahwa mereka seperti mendapat diskriminasi.

Sumber gambar, Dokumen Riska Munawarah
Dalam momen inilah Riska lalu berkata: “Di sini jilbab jadi kayak kontrol sosial bagi perempuan.”
Penilaian seperti bukan lahir dari ruang kosong. Coba dengarkan pengalaman Riska membuat cerita visual tentang sejumlah perempuan muda Aceh berjilbab yang menggeluti tari Hip Hop.
“Terus setelah berita itu tayang, mereka takut dihujat. Dan iya terjadi. Mereka menunjukkan di sosial medianya, ada yang menghujat ‘ngapain di Aceh ada penari kayak gitu.'”

Sumber gambar, Dokumen Riska Munawarah
Tumbuh dalam tradisi sebagai jurnalis foto, selain sejarah keluarga, perjumpaannya dengan banyak orang dengan latar belakang beraneka, membuat kepekaan sosial dan wawasan keagamaan Riska terus berkembang.
Dia lalu menyebut beberapa nama aktivis, intelektual, atau seniman perempuan Aceh yang terus menginspirasinya.
Ini pula yang sepertinya ikut menumbuhkan kesadarannya dan membuatnya amat peka pada tantangan dan persoalan seputar hak-hak dasar kaum perempuan—utamanya di Aceh, tempatnya lahir dan tumbuh besar hingga sekarang.

Sumber gambar, BBC News Indonesia/Heyder Affan
Dan itu terlihat jelas dalam berbagai penceritaan visual hasil bidikan melalui kameranya.
“Riska masih [fokus] hal-hal yang Riska temui dan ‘dekat’ dengan Riska, seperti cerita-cerita dari teman-teman dekat, cerita personal. Ini yang Riska bahas dalam karya,” jelasnya.
Salah-satu cerita foto karya Riska, yang kemudian mendapat penghargaan internasional, berlatar kisah nyata salah-seorang teman dekatnya asal Aceh.

Sumber gambar, Dokumen pribadi Riska Munawarah
Dalam foto itu, temannya itu berdiri dan menutupi wajahnya dengan memegang tongkat kain pel. Di sini Riska memang membuat potret anonim alias potret tanpa wajah.
“Dia mulai sadar ada struktur patriarki di keluarganya. Dia ingin mengubahnya, maka dia bersuara dan ingin ceritanya itu dibagikan melalui Riska,” ungkapnya.
Nilai-nilai patriarki itu, demikian cerita temannya tadi, terlihat dari posisi figur ayah yang merasa harus diistimewakan.
Suatu hari si ibu sakit, sehingga mau tidak mau si bapak harus beres-beres rumah. Apa yang terjadi?
“Dan ayahnya enggak bisa apa-apa, karena selama ini semuanya dikerjakan ibu. Sampai akhirnya tongkat pel itu patah. Makanya Riska bikin mukanya ditutup pakai pel. Itu ceritanya,” Riska lalu terkekeh.

Sumber gambar, Instagram Riska Munawarah
Begitulah. Diawali melihat langsung aktivitas kakaknya yang mendalami fotografi, Riska kecil mulai tertular dunia itu.
Teori fotografi kemudian dia dapatkan saat kuliah di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh.
Tamat kuliah, Riska terjun sebagai jurnalis foto.
Sebagai fotografer lepas dan stringer sebuah kantor berita yang berpusat di London, karya-karyanya sudah dimuat di berbagai media dan kantor berita di Inggris hingga AS.
Namun ketertarikannya pada foto dokumenter, mulai muncul ketika dia mengikuti Permata PhotoJournalist Grant (PPG) di Jakarta pada 2020.
“Karena di situ [foto dokumenter], kita punya riset yang panjang, kemudian kenal subyeknya lebih dalam,” ujarnya. Dia kini lebih nyaman di sebut sebagai pencerita visual.
Melalui foto dan cerita fotonya, karya-karya Riska Munawarah berulangkali dipamerkan di berbagai ajang internasional.
Misalnya saja, karya foto dokumenternya dipamerkan di Jakarta International Photo Festival 2025 dan 2022, Angkor Photo Festival 2023, Recontres d’Arles 2024, hingga Tbilisi Photo Multimedia 2025.
Dan lebih dari itu, beberapa hasil jepretan Riska Munawarah telah diganjar berbagai penghargaan di luar negeri.
Di antaranya dari Prince Claus Seed Award dan Picture Of The Year (POY) Asia Contest 2023.

Sumber gambar, Riska Munawarah/Reuters
Seperti dimuat dalam situs resmi POY Asia Contest, karya foto dokumenter Riska yang berjudul ‘This Is Us’ berhasil masuk sebagai finalis.
Dalam pengantar karyanya itu, seperti dikutip panitia penyelenggara ajang itu, Riska mengatakan bahwa dirinya mengamati gaya hidup masyarakat Aceh yang disebutnya berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.
“Karena pengaruh syariat Islam yang kuat,” kata Riska.
Hal itu itu diatur dalam peraturan daerah alias Qanun, yang berfungsi sebagai landasan hukum.

Sumber gambar, Riska Munawarah/Reuters
Riska lalu menjelaskan seperti apa isi aturan tersebut, misalnya saja soal kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan Aceh.
Dia lalu mengungkap bahwa pemerintah setempat kemudian membentuk polisi syariat.
“Untuk memastikan kepatuhan, melakukan pemeriksaan guna menegakkan aturan jilbab,” ujarnya.
Meskipun aturan ini disebutnya bertujuan untuk hasil yang positif, dalam praktiknya kadang-kadang peraturan ini membuat laki-laki berada di posisi ‘berkuasa’ untuk menghakimi perempuan secara tidak adil.

Sumber gambar, Riska Munawarah/Reuters
“Pemerintah [Aceh] juga mengatur pembatasan interaksi laki-laki dan perempuan di ruang publik,” demikian Riska, seperti dikutip dalam laman resmi POY.
Menurutnya, inspeksi berkala oleh polisi syariah itu digelar untuk memastikan kepatuhan.
Di sinilah Riska lalu berujar: Negara mengatur segala urusan ibadah pribadi-pribadi. “Dan [apabila melanggar] hukumannya adalah cambuk.”
Namun, apakah pembatasan yang berorientasi gender telah menjadikan Aceh ruang aman bagi perempuan? Riska balik bertanya.
“Sayangnya, fakta berkata tidak,” tulis Riska.

Sumber gambar, Instagram Riska Munawarah
Dia merujuk pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, bahwa Aceh tetap menjadi provinsi keempat dengan tingkat kekerasan tertinggi di Indonesia dalam hal pelecehan seksual.
Dalam bagian lain catatan itu, Riska berkata bahwa seri foto dokumenter itu menawarkan respons visual terhadap tantangan yang saya hadapi bersama teman-teman perempuan saya dalam konteks penerapan hukum Islam di Aceh.
“Saya memulai seri ini dengan membuat karya seni dari arsip keluarga yang menggambarkan busana perempuan Aceh sebelum hukum Islam diterapkan di Aceh,” ungkapnya.
Riska kemudian memperkenalkan potret tanpa wajah sebagai reaksi terhadap pembatasan ruang gerak perempuan oleh pemerintah.
“Sekaligus menggambarkan mereka sebagai simbol pasif dalam komunitas Islam di Aceh,” tegasnya.
Dia lalu berujar, kondisi sosial Aceh menjadi pendorong utama baginya untuk berkarya dan menyuarakan pendapat.
“Karena saya perempuan, saya lahir di Aceh, saya tumbuh besar di Aceh, Aceh adalah bagian dari hidup saya, dan saya harus mengakui bahwa terkadang lingkungan terdekat saya justru menghalangi saya untuk melakukan hal-hal tertentu,” jelasnya.
“Dengan menggunakan fotografi sebagai medium,” demikian tandas Riska, “saya mengadvokasi kehidupan perempuan di Aceh.”

Sumber gambar, Instagram Ruan Puan Kolektif
Dan awal September 2025 lalu, Riska terlibat kerja bareng dengan dua seniman perempuan Aceh. Mereka adalah Zikrayanti, seniman pertunjukan, dan Arifa Safura, seniman instalasi.
Di ajang ini, Riska kembali menghadirkan seri foto dokumenter ‘This Is Us’.
Dalam seri foto itulah, pengalaman pribadinya serta cerita ibunya dipaksa mengenakan jilbab di awal-awal penerapan syariat ikut mewarnai.
Demikian pula kisah personal kawan-kawan perempuannya dalam menghadapi sistem patriarki di dalam tembok keluarga, dia terjemahkan dalam bidikan kamera.
Belasan fotonya dicetak dalam ukuran besar di pajang di ruangan Rumah Cut Nyak Dhien di Aceh Besar.

Sumber gambar, Instagram Riska Munawarah/Sophie’s Sunset Library
Ini untuk pertama kalinya karya-karyanya dipamerkan di Aceh, tanah kelahiran dan tempatnya tumbuh-besar hingga sekarang.
“Sebenarnya agak takut,” kata Riska, seraya tertawa pendek.
“Karena saya kan mengkritik bagaimana penerapan syariat Islam di sini.”
Itu dia utarakan kepada saya dalam wawancara melalui telepon sekitar sepekan sebelum karyanya dipamerkan.
Dia berharap karyanya yang dipamerkan itu dapat membuka dialog dengan para pengunjung.
“Enggak mencari mana yang benar, mana yang salah. Tapi membuka kembali ruang dialog: Sebenarnya kita ini siapa, di mana kita ingin diperlakukan.” Suara Riska terdengar dari ujung telepon.
Dialog itu amatlah penting, karena sangat mungkin sikapnya berbeda dengan sikap sebagian perempuan Aceh lainnya.
“Saya juga ingin mendengar perspektif perempuan lain yang hadir,” ujarnya.
Di bagian bawah foto-foto yang dicetak dalam ukuran besar, pengunjung pameran dapat menulis komentar terkait isi atau pesan dari karyanya.
“Isu ini sangat penting. Tujuan saya adalah membuka ruang dialog dan mengubah persepsi orang terhadap perempuan, sekaligus mendiskusikannya,” tandas Riska Munawarah.