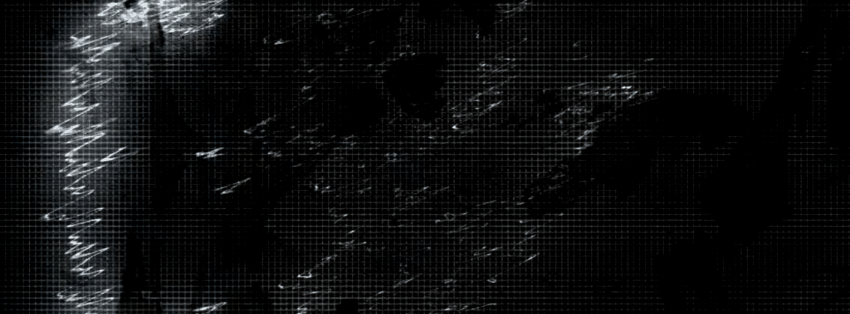Sumber gambar, Dasril Roszandi/NurPhoto melalui Getty Images
Peringatan: Artikel ini memuat penuturan kekerasan seksual yang dapat mengganggu kenyamanan Anda.
Perkara kekerasan seksual di pondok pesantren merupakan problem besar, bukan masalah yang dibesar-besarkan media. Apalagi para pengambil kebijakan bahkan di tingkat nasional belum serius menangani kekerasan seksual dengan berlandaskan perspektif korban, kata pengamat.
Pada 14 Oktober 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kejahatan seksual di pondok pesantren dibesar-besarkan oleh media mengingat hanya sedikit jumlahnya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah pegiat hak asasi manusia, Yuniyanti Chuzaifah.
“Ini bukan persoalan yang sederhana. Karena kekerasan seksual ini bukan isu personal melainkan isu sosial yang dampaknya masif. Tidak bisa dibilang dibesar-besarkan oleh media karena ini memang kasus besar,” ucapnya kepada BBC News Indonesia.
Sebelum respons dari Menteri Agama tersebut, pemerintah pernah membatalkan pencabutan izin operasional pondok pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur, yang pengasuh pesantrennya melakukan kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santri.
Di tengah hukuman pidana yang masih berjalan terhadap pelaku, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru berkunjung ke pondok pesantren ini dalam rangka silaturahmi.
“Itu secara sosiologi korbannya bagaimana? Jadi sebenarnya memang di level nasional sendiri itu dalam menyikapi persoalan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren ada konflik moralitas juga para petingginya,” ujar Direktur Women Crisis Center, Ana Abdillah.

Sumber gambar, Anton Raharjo/Anadolu Agency via Getty Images
Padahal temuan Pusat Pengkajian Islam & Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta mendapati 43.497 santri berpotensi rentan terhadap kekerasan seksual.
Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendata sebanyak 20% dari 573 korban kekerasan seksual berasal dari pondok pesantren. Jumlah korban yang terungkap diduga meningkat pada 2025 karena hingga Juni lalu ada sekitar 130-an kasus.
Kementerian Agama pernah mengeluarkan sejumlah peraturan pencegahan dan peta jalan pengembangan Pesantren Ramah Anak pada 2022 dan 2025 sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan.
Para pengasuh pondok pesantren juga berupaya keras mencegah kekerasan seksual di dalam lingkungan pesantren dengan berbagai langkah dan menyediakan ruang aman bagi siapa pun untuk bersuara.
“Tidak bisa digeneralisir semua pesantren berpotensi demikian (terjadi kekerasan seksual). Di tempat saya tumbuh, belajar, dan mengabdi sangat ketat batasannya,” ujar pengasuh Pesantren Putri Al Ihsan Lirboyo, Kediri, Ning Imas Fatimatus Zahra.
‘Diminta jadi istri kedua hingga iming-iming berkat’
Pada Juni 2025, belasan perempuan mengaku mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pemilik sekaligus pengurus salah satu pondok pesantren di Pulau Kangean, Sumenep, Jawa Timur. Peristiwanya terjadi ketika para korban masih menjadi santri sekitar 2016-2024.
Rata-rata para korban mengaku mengalami kekerasan lebih dari satu kali.
Dari kesaksian di persidangan yang sudah berjalan sejak 29 Juli 2025, para korban yang saat kejadian masih duduk di bangku SMP diminta mengantarkan air minum ke kamar pemimpin pesantren, Moh. Sahnan (51).
Setelah diminta mengantarkan air minum, korban mengaku diancam lalu disetubuhi. Setelah itu, korban mengaku dibedaki dengan bedak bayi seluruh tubuhnya atau hanya wajah saja. Sebelum keluar, para korban mengaku diancam jika menceritakan yang terjadi kepada siapa pun maka tidak akan berumur panjang.
Ini juga dibenarkan oleh kuasa hukum korban, Salamet Riadi. Selanjutnya, dikabarkan ada mediasi mengenai kesepakatan restitusi.
Dalam kasus lainnya, tindak pidana kekerasan seksual dilakukan Herry Wirawan pemilik Tahfidz Madani.
Sebagaimana dipaparkan dalam berkas putusan sidang pada 2022, ia memaksa para santri yang usianya sekitar 13-16 tahun dengan dalih dirinya merupakan seorang ayah sehingga tak akan merusak masa depan anaknya.
Namun dia meminta korban memijat, menemani bercerita tentang persoalan keluarganya, seraya mengintimidasi sehingga korban takut.
Herry melakukan kekerasan seksual pada 13 orang santri putri dan sebagian besar hamil saat itu. Herry dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya.

Sumber gambar, Dasril Roszandi/NurPhoto melalui Getty Images
Kasus berikutnya terjadi di pondok pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur.
Moch Subchi Azal Tzani atau Bechi, putra pengasuh ponpes tersebut, dituduh menggunakan kuasanya untuk memanipulasi korban yang merupakan santri.
Bechi mengambil kesempatan ketika mewawancara sejumlah santri untuk kebutuhan operasional klinik kesehatan di Jombang.
Dari berkas putusan pengadilan, Bechi menyatakan ingin menjadikan korban sebagai istri kedua saat sesi wawancara. Meski korban menolak, Bechi disebut memanipulasi dengan menyatakan hendak “menetralkan” korban dengan syarat membuka pakaian.
Pascakejadian hari itu, Bechi dikatakan kembali meminta korban menemuinya dan mengancam korban akan menyesal seumur hidup jika tak menurutinya.
Dengan ketakutan, korban mengaku datang lalu dimaki-maki dan diperkosa. Saat korban mulai mencari perlindungan selepas kejadian, ia dikeluarkan dari tempatnya mondok.
Korban melaporkan Bechi ke Polres Jombang pada Oktober 2019, tapi kasus ini baru diproses pada 2022 hingga putusan di pengadilan tingkat pertama dinilai mengecewakan yakni hukuman tujuh tahun penjara.
Dengan pertimbangan hakim, pelaku masih muda dan punya kesempatan untuk memperbaiki. Kemudian, pelaku juga disebut sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki anak kecil yang butuh figur ayah.
Berdasarkan informasi, diduga pelaku kini tidak lagi berada di Lapas Medaeng.
Di Lombok Barat, sebanyak 22 santri putri juga dilecehkan pengasuh pondok pesantren dengan dalih memberkati keturunan masa depan korban.
Kasus ini terungkap pada April 2025.
Mengapa kekerasan seksual masih langgeng di lingkungan keagamaan?
Yuniyanti Chuzaifah yang pernah menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan 2010-2014 berkata kekerasan seksual di pesantren terjadi karena banyak persoalan yang berkelindan dan ini tidak mudah diurai. Bahkan, menurutnya, belum tentu dapat dituntaskan dengan kebijakan atau lahirnya beleid.
Hal serupa juga diungkap Direktur Women Crisis Center Ana Abdillah dan para peneliti dari PPIM UIN Jakarta, salah satunya melalui tulisan Windy Triana bertajuk Bayang Otoritas, Independensi, dan Produksi Ilmu Pengetahuan yang masuk dalam buku Menjaga Marwah Pesantren: Refleksi Penelitian Kekerasan Seksual di Pesantren.
- Feodalisme patriarki, relasi kuasa, dan budaya impunitas
Yuniyanti menyampaikan feodalisme patriarki mengukuhkan beberapa lapis relasi kuasa.
“Ada relasi kuasa berbasis kelas, misal yang miskin dijanjikan dibiayai. Lalu, ada relasi kuasa berbasis spiritual karena dia tokoh agama. Satu lagi, relasi kuasa dia sebagai laki-laki,” ucap Yuniyanti yang juga pernah mengenyam pendidikan di pesantren.
“Dulu, temuan Komnas Perempuan yang berjudul Memecah Kebisuan itu ada rayuan-rayuan spiritual pakai justifikasi agama. Jadi, agama juga dimanipulasi untuk kekerasan seksual.”
Bentuk patriarki dibalut agama yang menyasar pada relasi kuasa ini juga diwarnai dengan pengultusan tokoh. Lantaran hal ini, rumah kyai pun akan dirasa magis sehingga santri bangga saat diminta tolong oleh kiai untuk membersihkan rumah bahkan membawakan minum.
“Ini kemudian berpotensi terjadi kekerasan seksual karena rumah itu termasuk ruang tertutup. Jadi, menurut saya untuk juga menjaga marwahnya kyai tidak perlu lagi ada hal demikian.”
Munculnya ancaman dan dianggap melawan jika menolak juga kerap menjadi kuncian pelaku agar korban bersedia menuruti kemauan pelaku. Apalagi jika pelaku punya jaringan luas atau orang berpengaruh, seperti pemilik pondok, keturunannya, atau guru yang senior.
Tidak hanya itu, orang-orang semacam ini juga terlindungi karena budaya impunitas terhadap pelaku.
“Jadi dia berpikir tidak akan terungkap. Dia tidak paham dunia sudah berubah. Anak-anak atau orang tua bahkan dari kalangan miskin pun paham martabat itu lebih penting,” kata Yuniyanti.
Meski begitu, melawan impunitas ini tidak mudah meski kesadaran bertumbuh.
Ana Abdillah yang menjadi pendamping korban dalam perkara kekerasan seksual yang dilakukan anak pengasuh pondok pesantren di Jombang mengungkapkan ancaman dialami korban, keluarganya, hingga para pendamping.
Biasanya, keluarga atau korban diintimidasi untuk mencabut laporan atau diberi imbalan uang hingga tekanan sosial di lingkungan masyarakat yang menimbulkan stigma bagi korban dan keluarga.
“Saya sebagai pendamping dan teman-teman dikirimi pesan ancaman dari whatsapp, ditelpon, kantor ada orang mencurigakan, sampai doxing dengan narasi yang mendiskreditkan. Itu mengkhawatirkan,” ujar Ana.
“Akhirnya, kami pasang CCTV di kantor. Teman-teman kantor tidak pulang malam. Saya juga akhirnya karena sering dicari orang tidak dikenal di kantor akhirnya mengurangi waktu untuk bekerja di kantor dan lebih sering di pengadilan.

Sumber gambar, INA Photo Agency/Universal Images Group melalui Getty Images
- Ketertutupan pesantren dan diskoneksi dengan dinamika luar
Windy dalam tulisannya menuangkan ketertutupan pesantren di satu sisi merupakan bentuk independensi yang dijaga sejak pesantren berdiri sebelum kemerdekaan Indonesia. Namun di sisi lain, ketertutupan pesantren dipengaruhi oleh struktur relasi kuasa dalam pesantren sehingga bukan semata sikap individu.
Budaya hormat, tulis Windy, sering juga menghambat kritik terhadap otoritas, yang kemudian didukung oleh ketiadaan mekanisme pelaporan dan pendampingan yang memadai. Ini kemudian menyulitkan penanganan saat kekerasan seksual terjadi di dalamnya. Bahkan upaya pembentukan kebijakan dari eksternal juga sukar menembus.
Yuniyanti menambahkan paparan berlakunya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak sepenuhnya diketahui para pengampu pondok pesantren.
“Sosialisasi dari pembentuk undang-undang juga minim. Civil society dan media sebenarnya yang gencar, tapi keterjangkauan sampai ke pesantren itu tidak terlalu banyak.”
Selain itu, dinamika di luar pesantren kadang tidak mudah menelusup masuk. Ia mengakui banyak juga pesantren modern yang selalu mencoba terpapar isu terbaru, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pesantren. Namun ada juga pesantren lain yang tidak demikian.
Salah satu akibatnya, kekerasan seksual pun dipandang sebagai isu personal. Padahal, ini merupakan isu sosial mengingat dampaknya yang sangat besar. Dirunut dari korban yang menanggung trauma dan stigma, keluarga yang juga terluka dan menanggung dampaknya, termasuk saat korban hamil dan menggugurkannya dianggap dosa.
“Persepsinya ‘oh aku sudah berzina’, padahal dia korban. Belum lagi orang tuanya. Kalau harus mengugurkan, ada rasa bersalah dan persepsi menjadi ahli neraka. Padahal traumanya jauh dari sembuh. Ini dampaknya cukup serius kepada para korban,” tutur Yuniyanti.
Dampak lain, kepercayaan terhadap pesantren akan menurun. Hal ini tentu tidak diinginkan.
“Saya mendapati sejumlah pesantren itu turun santrinya karena orang tuanya ketakutan untuk menyekolahkan anaknya ke pesantren.”
Keluarga pelaku yang tak tahu kelakuan predator seksual ini juga menanggung beban.
“Saya pernah ketemu sama keluarga pelaku. Itu istrinya pernah mengiba-iba ke Komnas Perempuan terkait suaminya. Istrinya itu di depan untuk menjadi tameng. Belum lagi organisasi besar yang terafiliasi ikut terbawa,” kata Yuniyanti.
- Minimnya kontrol seksualitas
Yuniyanti menyoroti juga kontrol seksualitas yang minim. Ini terlihat dari satu pelaku menyasar banyak korban kekerasan seksual di pesantren bahkan lingkungan keagamaan secara luas.
Bahkan korban tidak hanya perempuan. Badan Keahlian DPR pada Januari 2025 mengabarkan kekerasan seksual di Duren Sawit, Jakarta Timur yang korbannya tujuh anak laki-laki.

Sumber gambar, Evan Praditya/INA Photo Agency/Universal Images Group melalui Getty Images
Dari riset yang dilakukan PPIM UIN Jakarta, kerentanan kekerasan seksual lebih banyak menyasar pada santri putra yakni sebanyak 40.689 orang dan santri putri sebanyak 3.923 orang. Sementara itu, sebanyak 793.188 santri pernah melihat temannya mengalami kekerasan seksual.
“Seksualitas itu sesuatu yang bisa dikontrol. Karena itu, UU TPKS ini bisa menjadi batasan karena bisa dilaporkan dan mendapat hukuman. Bahkan hanya jawil-jawil itu bisa berdampak pada korban,” kata Yuniyanti.
Di sisi lain, tradisi poligami dengan dalih agama disebutnya sebagai bentuk permisif agar bisa berhubungan seksual lebih dari satu orang. Jadi, ada problem teologi yang perlu dipersoalkan.”
Apa tawaran solusinya?
Yuniyanti pun menawarkan solusi yang sepatutnya diambil adalah membongkar feodalisme patriarki sehingga relasi kuasa mengikis.
Ketertutupan pesantren dan diskonektivitas dengan dinamika di luar pesantren, menurutnya, harus bertransformasi mengingat era kini identik dengan transparansi, terlebih terkait kasus kekerasan seksual.
Dalam kerangka hak asasi manusia, semua agama termasuk Islam justru banyak mengajarkan. Ini yang semestinya ditafsirkan dengan tepat, bukan menjadi pembenaran untuk tindakan yang malah identik dengan kekerasan.

Sumber gambar, Garry Lotulung/Anadolu Agency melalui Getty Images
Dia menambahkan, UU TPKS harus gencar disosialisasikan masuk dalam ranah pesantren. Ini bisa membantu perlindungan untuk korban. “Ada soal produksi undang-undang yang hanya dilahirkan, tapi sosialisasi tidak optimal.”
Padahal dengan penerapan ini secara optimal para korban bisa dipastikan untuk mendapatkan kompensasi maupun restitusi karena dalam UU TPKS, harta pelaku bisa disita.
“Tujuannya karena korban kan sering ditinggalin dengan punya anak. Dari upaya ini, harapannya bisa melanjutkan hidupnya. Penting untuk korban juga benar-benar bisa menjalankan fungsinya lagi,” ujarnya.
Tapi, Yuniyanti melanjutkan, kebijakan saja tidak cukup. Menurut dia, permasalahan kebijakan saat ini tidak dibarengi dengan transisi kultural. Apalagi di lingkungan keagamaan, termasuk pesantren, perubahan kultural ini penting.
Pemahaman mengenai UU TPKS, soal otonomi tubuh, kesehatan reproduksi, dan seksualitas penting juga bagi para pemimpin agama.
Selain itu, dekonstruksi peran sosial politik para tokoh agama juga mendesak.
“Tokoh sentris, sering sedikit-sedikit tokoh agama atau tokoh masyarakat sehingga tokoh bilang apa, rakyat itu disuruh jadi bebek,” ujar Yuniyanti.
‘Aturan ketat di sejumlah pesantren’
Maya, yang merupakan alumni di salah satu pesantren di Pati, Jawa Tengah menceritakan kembali pengalamannya ketika menghabiskan waktu enam tahun di pondok pesantren pada usia remaja.
Saat itu, periode 2000-an, ia menyebut edukasi mengenai batasan dan kekerasan seksual tidak gencar seperti saat ini sehingga ada gestur yang bisa jadi tidak disadari.
Pelajaran fikih yang diajarkan di pesantrennya lebih berkaitan dengan tata cara dan adab berkaitan dengan ibadah. Mengenai sikap, Maya diajarkan untuk menundukkan pandangan pada lawan jenis.
“Ketemu atau berpapasan dengan lawan jenis saat hari jumat yaitu libur sekolah. Karena gedung pesantren santri putra dan putri terpisah, begitu pun dengan sekolah,” ujar Maya.
Ia menambahkan ada regulasi tidak boleh menjalin hubungan dengan lawan jenis, termasuk larangan bertemu tanpa ada tujuan jelas seperti koordinasi kegiatan sekolah/pesantren.
“Ini juga tetap dengan pengawasan. Dengan sesama perempuan saja, batasan di pesantren itu ketat. Misalnya, tidak boleh sekamar mandi bareng.”
Ia juga menuturkan santri tidak diperbolehkan untuk memasuki ruang pribadi kyai, seperti kamar. Saat mengaji juga dilakukan di ruang terbuka, seperti di aula.
Sepanjang menghabiskan jenjang pendidikan di pondok pesantren, ia tidak menemui kekerasan seksual di lingkungannya.

Sumber gambar, Garry Lotulung/NurPhoto melalui Getty Images
Tiara Norma Yunita (19), santri Ma’had Al-Jami’ah UIN Sunan Ampel Surabaya mengungkapkan hal serupa. “Jadi tidak dibolehkan kami untuk bertemu walaupun hanya sekedar satu detik tidak boleh,” ucap Tiara.
Ia mengakui mendengar banyak berita kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren. Namun sejauh ia tinggal di pesantren, ia tidak pernah mengalami hal tersebut atau mendengar terjadi di lingkungan tempatnya “mondok”.
“Kami punya aturan serta tata tertib yang tegas untuk membantu penanganan ataupun pencegahan atas permasalahan kekerasan seksual atau bullying. Ada juga pendekatan psikologis kepada korban supaya tidak merasa traumatis seandainya terjadi. Sejauh ini tapi tidak ada,” ucap Tiara.
Perempuan yang juga alumni Pesantren Putri Al-mawaddah, Ponorogo, Jawa Timur menuturkan banyak hal yang diperoleh selama “nyantri”. Tidak hanya ilmu agama, tapi juga tata krama dan nilai kebersamaan.
Aryati yang merupakan orang tua santri mengakui berita-berita membuatnya melakukan riset mendalam ketika ingin memasukkan kedua anaknya di pesantren.
Pilihannya jatuh pada pesantren di Gunung Sindur, Jawa Barat. Ia memastikan ada aturan anti kekerasan dan pencegahan kekerasan seksual.
“Anak-anak cerita senang di sana. Interaksi dengan lawan jenis, baik teman maupun ustadz atau pengajar hanya ada di kelas. Orang tua lawan jenis kalau jenguk juga tidak boleh masuk asrama, ada ruangan terbuka. Anak juga ada waktu telpon orang tua. Kami juga bisa rutin menanyakan kondisi anak pada pengasuhnya langsung,” papar Aryati.
Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan dari pesantren?
Pengasuh Pesantren Putri Al Ihsan Lirboyo, Kediri, Ning Imas Fatimatus Zahra berkata tidak semua pesantren berpotensi terjadi kekerasan seksual. Bahkan di tempatnya kini mengabdi, Imas menyebut tidak pernah ada kejadian kekerasan seksual. “Itu merupakan oknum.”
Jumlah santri saat ini di Indonesia mencapai lebih dari empat juta orang yang tersebar di lebih dari 42.000 pondok pesantren.
Ia menjelaskan “ada sekat tebal” di antara santri putra dan putri, guru putra dan putri, bahkan ketika ada kepengurusan yang melibatkan putra dan putri juga dilakukan dengan pengawasan ketat.
Kendati demikian, pihak tetap berupaya melakukan pencegahan dan penanggulangan. Antara lain, evaluasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga bisa terpetakan segala potensi yang bisa menuju ke arah kekerasan.
“Kami juga melakukan workshop dengan Mbak Alissa Wahid, membedah satu per satu masalah di pesantren. Lalu, bagaimana meningkatkan rasa aman dan kesadaran pentingnya menjaga diri dari potensi kekerasan seksual,” ujar Imas.
Sejalan dengan pendidikan fikih, para santri juga diajarkan sikap-sikap yang masuk dalam kategori pelecehan seksual. Secara syariat, Imas menyampaikan sudah ada aturan yang jelas seperti tidak boleh berjabat tangan.
“Apalagi pegang-pegang, tapi tetap dijelaskan bagian tubuh mana pun tidak boleh disentuh jika belum ada ikatan pernikahan.”
Para pemangku kebijakan, kata Imas, juga selalu diingatkan mengenai relasi kuasa agar tidak melegitimasi perilaku semena-mena.
“Meski guru punya tanggung jawab untuk mendidik santri tapi bukan berarti guru bebas dari tanggung jawab moral sehingga harus terus memposisikan diri dengan cara yang patut dan layak, bahkan tidak bersedia dikultuskan, misalnya.”
Ujaran seksis juga disebutnya sebagai materi yang acap kali diingatkan pada para santri dan para guru agar tidak lagi melontarkannya pada siapa pun karena itu masuk bagian kekerasan seksual.
Ruang aman pun tersedia dengan jaminan perlindungan sehingga jika ada santri yang ingin mengadu bisa merasa tenang dan aman tanpa dihakimi.

Sumber gambar, Garry Lotulung/Anadolu Agency melalui Getty Images
Secara terpisah, pengasuh Pondok Pesantren Assirojiyyah, Sampang, Kyai Haji Itqon Busyiri berkata memiliki larangan 3P yaitu larangan untuk perkelahian, percintaan, dan pencurian.
“Nah kalau nanti ada laporan-laporan, ya kita bela. Atau kalau perlu, wali muridnya dipanggil. Karena kita tidak punya aturan-aturan seperti buku KUHP gitu,” ujar Itqon.
“Kalau ada yang tersakiti, ya kita lindungi. Kalau orang tuanya mau mengambil anaknya atau dipindahkan ke pondok lain, ya kami melepaskan.”
Mengenai keberadaan ruang aman dan perlindungan bagi santri apabila terjadi kekerasan seksual, Itqon tidak secara terang menjelaskan.
“Ruangan aman, ya yang pasti ada lah. Mereka cari perlindungan sendiri, ada kakak seniornya yang melindungi dan seterusnya. Mereka saling menjaga. Karena predator ini nggak mungkin bisa disembuhkan, kecuali ada efek jera. Kita kan nggak mungkin dengan kekerasan juga.”
Apa langkah pemerintah?
Kementerian Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 soal Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di Kementerian Agama.
Kemudian, ada juga Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Program Pengembangan Pesantren Ramah Anak. Sejumlah kebijakan ini disebut sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Basnang Said, berkata Pesantren Ramah Anak ini sudah berjalan dengan 512 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjadi percontohan.
Sesuai dengan peta jalannya, pengembangan infrastruktur program Pesantren ramah Anak ini mulai dijalankan 2024. Tahun ini, strateginya adalah penguatan perspektif Pesantren ramah Anak dengan uji coba. Transformasinya disasar pada 2026. Lini masanya ditargetkan hingga 2029 dengan strategi akhir yakni pesantren sebagai model institusi pendidikan ramah anak.
“Kami tidak jalan di tempat. Sudah ada tahun per tahun apa yang harus dikerjakan. Tapi memang kami terus upayakan untuk percepatan demi melindungi anak dari kekerasan apapun yang berpengaruh pada psikologis mereka. Jangan sampai anak-anak merosot semangatnya dan psikologisnya,” kata Basnang.
Pengasuh Pondok Pesantren Assirojiyyah, Sampang, Kyai Haji Itqon Busyiri menyatakan ramah anak itu normatif.
“Kami melakukan ramah anak itu kayak gimana? Di pesantren itu masih lho jewer-jewer. Kalau enggak jewer itu enggak sukses gitu,” ujar Itqon.
Untuk antisipasi kekerasan, pihaknya bergerak jika ada laporan dan menindaklanjuti dengan memanggil wali murid.
“Kadang-kadang predator itu awalnya bukan pelaku, dia korban juga. Kalau ketemu, ya kita peringati, kita panggil orang tuanya.”
Pengasuh Pesantren Putri Al Ihsan Lirboyo, Kediri, Ning Imas Fatimatus Zahra, menanggapi anak-anak di pesantrennya dibagi sesuai jenjang dengan keberadaan ibu kamar di tiap kamar.
Kebutuhan gizi, kebutuhan psikologis melalui kegiatan yang menyenangkan, opsi kebebasan menjalankan hobi dari olahraga, IT, hingga public speaking berupaya dipenuhi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
“Pesantren ini lembaga yang sudah eksis lebih lama dari republik ini. Relevansi terus kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan akomodir. Niat kami menjadi lentera bagi mereka yang menginginkan cahaya itu,” ungkapnya.
Wartawan Ahmad Mustofa di Surabaya berkontribusi dalam artikel ini.